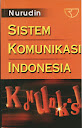Kompas (30/11/10) memberitakan keluhan warga Malang berkaitan dengan berita-berita media massa (cetak dan elektornik) yang berlebihan tentang aktivitas gunung Bromo. Akibat pemberitaan yang berlebihan tersebut pendapatan ekonomi yang dihasilkan mereka menurun drastis. Pertanyaan kita adalah mengapa masyarakat menjadikan media massa sebagai “kambing hitam? Apakah yang diberitakan oleh media kita itu memang realitas sebenarnya yang terjadi?
Realitas Kedua
Media massa itu hanya mengonstruksi realitas yang terjadi di lapangan. Namanya mengonstruksi, jadi tidak semua yang diberitakan di lapangan itu bisa dilaporkan. Media mempunyai pilihan-pilihan untuk memberitakan fakta yang dilihatnya, melalui seorang wartawan. Lalu apakah wartawan yang memberitakan sebuah kejadian itu memberitakan realitas? Ia memberitakan realitas, tetapi realitas media bukan realitas sebenarnya.
Penjelasannya begini. Aktivitas gunung Bromo itu sebuah realitas. Sebut saja realitas pertama (first reality). Sebagai realitas pertama ia tampil apa adanya. Ketika seorang melihat sendiri aktivitas gunung Bromo berarti ia melihat realitas senyatanya atau realitas pertama. Dalam posisi ini, fakta-fakta terjadi begitu saja sesuai “hukum alam”. Dengan kata lain, realitas pertama tentang aktivitas gunung Bromo seperti yang dilihat oleh masing-masing orang, termasuk para wartawan.
Kemudian, dengan kemampuan yang dimiliki para wartawan itu merekam setiap kejadian dalam otaknya melalui alat bantu, entah menulis langsung, merekam pakai kamera atau memotretnya. Apa yang dicatat dan direkam wartawan ini tentu saja sangat tergantung dari filter masing-masing wartawan. Filter dalam kajian komunikasi massa bisa berwujud kondisi psikologis, jenjang pendidikan, pandangan politik, emosi, kepentingan, budaya atau sekadar kondisi fisik. Filter-filter itu harus diakui memengaruhi apa yang wartawan catat dan rekam.
Kalau sudah begini apakah yang diberitakan oleh wartawan tersebut sebuah realitas? Wartawan memang melaporkan realitas yang direkam dan dicatatnya karena ia memberitakan fakta-fakta di lapangan. Namun demikian realitas yang sudah diberitakan itu sangat dipengaruhi dan tergantung pada filter yang dipunyai masing-masing wartawan. Jadi, wartawan itu tetap memberitakan realitas tetapi realitas yang sudah dikonstruksi. Sebut saja realitas kedua (second reality).
Dengan demikian, wartawan yang memberitakan aktivitas gunung Bromo sampai menimbulkan kecemasan masyarakat itu sebuah realitas, tetapi realitas kedua yang sudah bercampur dengan banyak aspek.
Subjektivitas
Kalau sudah begitu apakah yang diberitakan media massa itu subjektif karena sangat tergantung dari sang wartawan? Untuk menjawab ini ada baiknya kita mengutip pendapat Jakob Oetama. Dalam buku saya berjudul Jurnalisme Kemanusiaan, Membongkar Pemikiran Jakob Oetama tentang Pers dan Jurnalisme (2010) terungkap bahwa pemberitaan media massa itu objektivitas yang subjektif. Semua kejadian yang diberitakan media itu merupakan sesuatu yang objektif. Sedangkan bagaimana kejadian itu dipilih menjadi berita atau dilaporkan sebagai berita, jelas sesuatu yang subjektif.
Berita itu bukanlah kejadianya itu sendiri, tetapi berita ialah laporan tentang sesuatu kejadian aktual yang sudah melalui beberapa tahapan dan proses sampai menjadi sebuah berita yang muncul di media. Kejadian adalah realitas pertama (sebagaimana disebutkan di bagian awal), sementara berita adalah realitas kedua (ada yang menyebut realitas media).
Diakui atau tidak, faktor subjektivitas sering muncul dalam pembuatan sebuah berita. Ini tak lain karena dalam pembuatan berita, faktor pribadi wartawan terlibat jauh dalam pemilihan fakta-fakta di lapangan. Wartawan menulis berita apa adanya saja sudah subjektif karena ia memilih dan memilah fakta-fakta yang disajikan (bukan fakta keseluruhan). Apalagi kepentingan media ikut memengaruhinya.
Contoh kecil saja begini. Ketika memberitakan korban kecelakaan yang dialami oleh seorang perempuan umur 25 tahun, masing-masing wartawan bisa membuat profiling (pelabelan) yang berbeda satu sama lain. Bisa jadi seorang perempuan itu disebut dengan “perempuan karir”, perempuan yang bertubuh bahenol”, wanita yang punya rambut terurai panjang”, atau wanita yang berwajah manis”. Itu semua sangat tergantung dari persepsi, latar belakang, pengalaman, tuntutan kerja wartawan dan misi-visi medianya. Apalagi jika wartawan yang menulis itu punya kepentingan pribadi di balik pembuatan sebuah berita.
Berkaitan dengan itu, Dennis McQuail (2000) pernah juga mengungkapkan tentang peran media yakni as a window on events and experience dan as a mirror of events in society. Media itu seperti sebuah jendela. Ketika seseorang membuka jendela rumah, ia bisa memandang peristiwa di luar jendela itu. Namun demikian, peristiwa yang ada hanya sebatas sudut pandang jendela tersebut dan bukan semua peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Jendela juga bisa dianalogikan sebagai sebuah jendela. Melalui “jendela itu” kita bisa membaca peristiwa tentang aktivitas gunung Bromo. Tetapi sekali lagi, bukan semua peristiwa yang terjadi tetapi hanya sebatas sudut pandang yang bisa ditangkap media (realitas kedua).
Sementara itu, media juga bisa sebuah cermin peristiwa di masyarakat (a mirror of events in society). Cermin hanya sebuah pantulan dari kejadian, sama seperti kalau kita sedang bercermin. Apa yang tersaji dalam cermin bukan kenyataan sesungguhnya, tetapi sekadar pantulan dari fakta. Sebagai cermin, media pun hanya mampu memantulkan sebagian kecil dari kejadian yang berlangsung di masyarakat dan tak mampu memenuhi seluruh keinginan manusia.
Catatan Penting
Jadi, kecemasan masyarakat atas pemberitaan berlebihan dari media tidak serta merta harus digeneralisasi. Sebab, masing-masing media mencoba mengungkapkan realitas berdasar realitas kedua atau realitas media. Sementara itu, masing-masing media mempunyai realitas yang berbeda-beda.
Catatan penting yang bisa digarisbawahi adalah bahwa kecemasan masyarakat atas pemberitaan media justru menjadi bukti bahwa media memang mempunyai kekuatan dalam membentuk opini publik. Masyarakat tidak perlu terlalu cemas, begitu pula wartawan juga bisa lebih bijak dalam membuat berita karena pemberitaannya berdampak hebat di masyarakat.
Type rest of the post here
Readmore »»
Gejolak Timteng dan Kemenangan Jejaring Sosial

(Tulisan ini bagian dari naskah buku "Internet Menuju Cyber Village")
Timur Tengah (Timteng) tengah diguncang prahara. Setelah Zine al-Abidine Ben Ali (Tunisia) turun dari jabatannya pada tanggal 14 Januari dan Hosni Mubarak (Mesir) pada tanggal 11 Februari tumbang, Moammar Khadafy (Libya) digoncang. Khadafy sendiri bereaksi keras atas protes pada dirinya. Peristiwa itu membuka mata para pemimpin Timteng untuk melakukan langkah-langkah baru. Ali Abdullah (presiden Yaman), Omar Hasan (presiden Sudan), buru-buru tidak mencalonkan lagi sebagai kandidat pada Pemilu mendatang. Raja Bahrain, Sheikh Hamad, dengan cepat melakukan dialog dengan oposisi untuk mengantisipasi keadaan.
Tidak bisa dipungkiri meluasnya protes dan tergulingnya dua presiden di Timteng tersebut akibat dari pengaruh teknologi komunikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube dan Flickr. Teknologi komunikasi itu telah memberikan pengaruh pada pola pikir, sikap, dan perilaku warganya (klik: buku)
Dunia Arab yang dikenal dengan budaya Islamnya telah terpengaruh film-film Hollywood dari budaya Barat serta internet yang membuat kehidupan masyarakatnya semakin terbuka dan demokratis. Apalagi, saat ini keberadaan jejaring sosial sudah menjadi keniscayaan. Meskipun berada dalam sebuah negara dengan budaya tertentu, mereka bisa berhubungan dan mengakses informasi dari luar. Ini akan menggesek budaya lokal.
Imperialisme Jejaring Sosial
Berkaitan dengan itu, ada sebuah pendapat yang pernah dikatakan oleh Herb Schiller dalam tulisannya berjudul Communication and Cultural Domination. Kajian Schiller ini melihat peran media massa Barat yang dituduh melakukan imperialisme budaya pada media massa dunia ketiga (berkembang).
Alasannya, media Barat mempunyai efek yang kuat untuk memengaruhi media dunia ketiga. Dengan kata lain, media Barat sangat mengesankan bagi media di dunia ketiga. Sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Dalam perspektif ini, ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi ‘penghancuran” budaya asli di negara ketiga.
Apalagi untuk saat sekarang, berbagai bentuk imperialisme budaya bisa diperluas lewat jejaring sosial. Lihat kasus yang terjadi di Mesir beberapa waktu lalu. Begitu ada gejolak protes di alun-alun Tahrir, banyak saksi mata melihat, merekam dan menulis. Fakta-fakta itu kemudian disiarkan oleh tidak saja stasiun televisi Al Jazeera tetapi juga CNN. Bahkan begitu aksi muncul, kita bisa membaca peristiwa demi peristiwa dalam situs jejaring sosial. Peristiwa ini bisa diakses pula oleh mereka yang tidak hadir dalam demonstrasi di lapangan itu. Tetapi mereka ini ikut menyebarkan gagasan-gagasan akan pentingnya Mubarak mundur dari jabatannya lewat jejaring sosial itu.
Memang, teknologi itu sendiri tidak membuat gerakan. Tetapi orang-orang yang memanfaatkan teknologi jejaring sosial itu dengan antusias memanfaatkannya. Dalam kajian komunikasi kenyataan itu sering disebut dengan communication technological animal.
Communication technological animal berarti individu-individu yang menjadikan teknologi sebagai sangat fundamental bagi humanitasnya. Bagi mereka, teknologi adalah faktor utama dalam melakukan perubahan. Bahkan teknologi komunikasi seperti jejaring sosial dipercaya sebagai alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya.
Jejaring sosial telah memungkinkan sesuatu yang selama ini dipendam, misalnya kecurangan presiden, bisa diungkap secara transparan. Barangkali, awalnya sekadar informasi yang disebar, tetapi informasi yang disebar dalam jejaring sosial itu telah membuka mata banyak orang untuk ikut menyebarkannya.
Fenomena di Indonesia juga bisa dijadikan contoh. Berapa banyak kasus-kasus yang diungkap, dipercepat penyelesaiannya, undangan simpati dibangun melalui jejaring sosial? Gerakan sejuta Facebooker pendukung Priya Mulyasari atau gerakan mendukung ditetapkannya Sultan Yogya sebagai gubernur menyebar luas diketahui dari jejaring sosial.
Begitu juga, kepemimpinan tangan besi yang dilakukan mantan presiden Mesir dan Tunisia telah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di dua negara itu. Ketidakpuasan ini kemudian ditulis dalam jejaring sosial. Dengan cepat hal itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lihat pula aksi brutal pemimpin Libya Moammar Khadafy yang memerintahkan pasukannya menghalau protes massa dengan rudal antipesawat. Bahkan 1000 orang lebih sudah tewas sejak marak aksi protes di negara yang beribukota Tripoli tersebut. Semua itu bisa diakses melalui jejaring sosial.
Pelajaran Berharga
Pelajaran yang bisa dipetik dari meluasnya jejaring sosial itu antara lain; pertama, tidak ada sesuatu rahasia politik yang terus menerus tersimpan rapat. Para diktator dan pemerintahan tangan besi lambat atau cepat akan digugaut oleh people power. Kedua, penting kiranya pemerintah Indonesia segera untuk melakukan demokratisasi dan penegakan hukum disegala bidang sebelum gerakan rakyat semakin luas. Mereka tidak digerakkan oleh pihak lain, tetapi bergerak sendiri karena solidaritas dan ketidakpuasan atas peristiwa yang menimpanya.
Kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat negara lambat atau cepat akan terus terungkap. Jika ini tidak diantisipasi gelombang protes rakyat akan semakin luas. Lihat kasus demonstrasi menentang PSSI? Itu salah satu contoh kecil solidaritas gerakan yang tidak bisa dipungkiri konsekuensi dari jejaring sosial.
Jejaring sosial yang mempunyai pengaruh hebat untuk melakukan perubahan telah menjadi kekuatan penekan baru (new pressure group) dalam usaha melawan pemerintah. Maka, perubahan yang terjadi di Timteng bukan kemenangan rakyat saja, tetapi juga kemenangan jejaring sosial (Facebook, Twitter, Youtube dan Flickr).
Type rest of the post here Readmore »»
Kamis, Oktober 28, 2010
Buku Citizen Journalism Sebagai Katarsis Baru Masyarakat

Judul: Citizen Journalism Sebagai Katarsis Baru Masyarakat
Penulis: Nurudin
Penerbit: Buku Litera, DP2M DIKTI, DP2M UMM
Thn Terbit: November 2010
Munculnya blog adalah keniscayaan sejarah. Penyebaran pesan yang sebelumnya dimonopoli wartawan profesional, saat ini bisa dilakukan warga negara biasa. Inilah yang disebut dengan citizen journalism. Bahkan mereka bisa menyalurkan uneg-uneg, ketidakpuasan, ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya secara bebas. Inilah revolusi baru penyebaran pesan.
Buku yang berasal dari hasil penelitian ini mengungkap bahwa ada fenomena menarik berkaitan dengan pemanfaatan blog sebagai katarsis baru masyarakat. Melihat perkembangan citizen journalism yang kian berkembang, dalam jangka panjang mainstream media akan tertantang untuk melakukan kebijakan ulang berkaitan dengan penyebaran pesan itu. Tak sedikit mereka memunculkan rubrik atau tayangan “citizen journalism” versi mainstream media. Sebuah tantangan kritis, tidak saja bagi praktisi jurnalis profesional, tetapi juga para peneliti, akademisi yang selama ini mengamati perkembangan media massa. Buku ini juga mengkritisi teori uses and gratification yang selama ini hanya bicara tentang dampak media saja.
Note: pesan terhadap buku ini, dilayani via e-mail. silakan kirim e-mail ke: nurud70@yahoo.com atau via inbox FB di home blog ini. thanks.
Readmore »»
Minggu, Juni 27, 2010
Mahasiswa Komunikasi UMM Telanjangi Infotainment
Sumber: Okezone
MALANG - Acara infotainment yang marak di stasiun televisi kita dewasa ini sangat membodohi masyarakat. Bahkan, media yang getol menyiarkan bisa dianggap telah ikut membunuh masyarakat.
Itulah di antara pendapat yang muncul dalam launching buku Menelanjangi Infotainment dan Media-Media Pembunuh Masyarakat karya mahasiswa Jurnalistik dan Studi Media Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Coffee Time, Malang, Sabtu (26/6/2010).
Hadir sebagai pembicara dalam acara itu Abdi Purnomo (Ketua AJI Malang) dan Nurudin (dosen pembina penulisan dari UMM). Acara dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan orang tua wali mahasiswa.
Berkaitan dengan buku dan praktik infotainment, Abdi Purnomo, ketua AJI Malang dalam acara launching mengungkapkan, “Infotainment disuka dan dibenci. Infotainment pemberitaanya suka lebay dalam menyiarkan isu yang tidak faktual. Persepsi galak mengenai infotainment dapat dibaca dalam buku ini. Buku Menelanjangi Infotainment menegaskan tayangan infotainment harus ditingkatkan sesuai undang-undang dan kode etik”.
Secara singkat buku Menelanjangi Infotainment mengupas bahwa acara infotaiment di televisi swasta Indonesia sudah jauh dari ideal. Bahkan menyebarkan berita-berita bohong. Buku ini juga mengatakan bahwa infotainment itu bukan jurnalisme. Akibat kenyataan itu, buku-buku yang ditulis mahasiswa tepat kehadirannya. “Kekuatan media televisi harus dilawan dengan kekritisan audiens. Para audiens mencoba bersikap kritis pada ketidakadilan itu. Mahasiswa bagian dari audiens tersebut, “kata Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UMM, Frida Kusumastuti menanggapi terbitnya buku-buku mahasiswa itu.
Sebenarnya, tidak saja infotainment yang membodohi masyarakat, media-media lain juga bisa menjadi pembunuh masyarakat. Nurudin, dosen pembina penulisan dari Ilmu Komunikasi UMM, mengambil contoh buku Media-Media Pembunuh Masyarakat. “Media yang yang tidak memberitakan secara seimbang, menutupi fakta yang sebenarnya layak diketahui masyarakat, sarat dengan kepentingan sepihak adalah fakta-fakta pembunuhan masyarakat. Bahkan pembunuhan itu dirayakan besar-besaran dan dengan gegap gempita."
“Jadi, jika tidak dilakukan rekonstruksi besar-besaran dan masyarakat begitu apatisnya pada acara yang tidak mendidik, termasuk infotainment, media kita telah berusaha membunuh masyarakat beramai-remai. Bahkan semua itu dilegalkan dengan sebuah acara, “tegas Nurudin yang sudah menulis puluhan buku itu kepada okezone.
Masih kata Nurudin, buku itu akan menjadi daya dobrak kebekuan penulisan di kalangan sivitas akademika. Bahkan buku karya mahasiswa itu menyindir dosen-dosen yang selama ini tidak punya karya. “Buku ini juga menjadi kritikan pedas pada tayangan infotainment yang selama ini tidak lagi mendidik karena hanya menyiarkan informasi 'sampah', “tandas dosen yang juga telah menulis puluhan buku itu.
Ketika dimintai tanggapannya soal terbitnya buku itu, Ditalia I Mufrida, salah seorang mahasiswa penulis buku Menelanjangi Infotainment mengatakan, “Saya sangat termotivasi dengan terbitnya buku ini. Saya juga tidak membayangkan bisa mempunyai karya yang bisa diterbitkan. Sebagai wujud semangat itu, saya akan mempelopori pendirian Jurnalistik Club di jurusan komunikasi bersama teman-teman."
Hal senada diungkapkan mahasiswa bernama Tri Sulistiowati yang mengatakan bahwa dia terbakar dengan motto dosennya yang berbunyi "Publikasikan atau Menyingkirlah." “Itu sangat menohok saya tentunya. Dan saya mencoba membuktikannya,” tandasnya.
Buku ini melengkapi 3 karya buku sebelumnya yakni Kutu-kutu Media Massa, Seksualitas dalam Globalisasi Media, Kuda Troya Media Massa dan Jejak Pers, Tapak-tapak Kaki Para Kuli Tinta Mencari Jati Diri, Antara Idealisme Vs Komersialisasi. (mbs)
Readmore »»
MALANG - Acara infotainment yang marak di stasiun televisi kita dewasa ini sangat membodohi masyarakat. Bahkan, media yang getol menyiarkan bisa dianggap telah ikut membunuh masyarakat.
Itulah di antara pendapat yang muncul dalam launching buku Menelanjangi Infotainment dan Media-Media Pembunuh Masyarakat karya mahasiswa Jurnalistik dan Studi Media Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Coffee Time, Malang, Sabtu (26/6/2010).
Hadir sebagai pembicara dalam acara itu Abdi Purnomo (Ketua AJI Malang) dan Nurudin (dosen pembina penulisan dari UMM). Acara dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan orang tua wali mahasiswa.
Berkaitan dengan buku dan praktik infotainment, Abdi Purnomo, ketua AJI Malang dalam acara launching mengungkapkan, “Infotainment disuka dan dibenci. Infotainment pemberitaanya suka lebay dalam menyiarkan isu yang tidak faktual. Persepsi galak mengenai infotainment dapat dibaca dalam buku ini. Buku Menelanjangi Infotainment menegaskan tayangan infotainment harus ditingkatkan sesuai undang-undang dan kode etik”.
Secara singkat buku Menelanjangi Infotainment mengupas bahwa acara infotaiment di televisi swasta Indonesia sudah jauh dari ideal. Bahkan menyebarkan berita-berita bohong. Buku ini juga mengatakan bahwa infotainment itu bukan jurnalisme. Akibat kenyataan itu, buku-buku yang ditulis mahasiswa tepat kehadirannya. “Kekuatan media televisi harus dilawan dengan kekritisan audiens. Para audiens mencoba bersikap kritis pada ketidakadilan itu. Mahasiswa bagian dari audiens tersebut, “kata Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UMM, Frida Kusumastuti menanggapi terbitnya buku-buku mahasiswa itu.
Sebenarnya, tidak saja infotainment yang membodohi masyarakat, media-media lain juga bisa menjadi pembunuh masyarakat. Nurudin, dosen pembina penulisan dari Ilmu Komunikasi UMM, mengambil contoh buku Media-Media Pembunuh Masyarakat. “Media yang yang tidak memberitakan secara seimbang, menutupi fakta yang sebenarnya layak diketahui masyarakat, sarat dengan kepentingan sepihak adalah fakta-fakta pembunuhan masyarakat. Bahkan pembunuhan itu dirayakan besar-besaran dan dengan gegap gempita."
“Jadi, jika tidak dilakukan rekonstruksi besar-besaran dan masyarakat begitu apatisnya pada acara yang tidak mendidik, termasuk infotainment, media kita telah berusaha membunuh masyarakat beramai-remai. Bahkan semua itu dilegalkan dengan sebuah acara, “tegas Nurudin yang sudah menulis puluhan buku itu kepada okezone.
Masih kata Nurudin, buku itu akan menjadi daya dobrak kebekuan penulisan di kalangan sivitas akademika. Bahkan buku karya mahasiswa itu menyindir dosen-dosen yang selama ini tidak punya karya. “Buku ini juga menjadi kritikan pedas pada tayangan infotainment yang selama ini tidak lagi mendidik karena hanya menyiarkan informasi 'sampah', “tandas dosen yang juga telah menulis puluhan buku itu.
Ketika dimintai tanggapannya soal terbitnya buku itu, Ditalia I Mufrida, salah seorang mahasiswa penulis buku Menelanjangi Infotainment mengatakan, “Saya sangat termotivasi dengan terbitnya buku ini. Saya juga tidak membayangkan bisa mempunyai karya yang bisa diterbitkan. Sebagai wujud semangat itu, saya akan mempelopori pendirian Jurnalistik Club di jurusan komunikasi bersama teman-teman."
Hal senada diungkapkan mahasiswa bernama Tri Sulistiowati yang mengatakan bahwa dia terbakar dengan motto dosennya yang berbunyi "Publikasikan atau Menyingkirlah." “Itu sangat menohok saya tentunya. Dan saya mencoba membuktikannya,” tandasnya.
Buku ini melengkapi 3 karya buku sebelumnya yakni Kutu-kutu Media Massa, Seksualitas dalam Globalisasi Media, Kuda Troya Media Massa dan Jejak Pers, Tapak-tapak Kaki Para Kuli Tinta Mencari Jati Diri, Antara Idealisme Vs Komersialisasi. (mbs)
Readmore »»
Sabtu, Mei 22, 2010
Pilkada Berkualitas
Oleh Nurudin
(Radar Surabaya, Sabtu: 22 Mei 2010)
Sejumlah daerah di Jawa Timur akan dan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagaimana pemilihan selama ini, gebyar untuk menyambut pesta demokrasi daerah itu sudah dilakukan. Tak jarang karena semangatnya, para kandidat yang belum tentu menjadi calon sudah memasang baliho di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, karena tujuannya mengenalkan diri pada pemilih, sering tidak memperhatikan estetika pemasangan, melanggar ruang publik, dan merusak pemandangan. Semua itu dilakukan untuk menyambut Pilkada.
Menyambut Pilkada dengan gebyar yang heboh memang tidak salah. Tetapi, mencoba berpikir lebih jernih agar kualitas Pilkada menjadi lebih baik suatu keharusan. Sayang, tak banyak – untuk menyebutkan tidak ada – para calon yang berpikir dalam jangka panjang. Umumnya, mereka berpikir dalam jangka pendek yakni bagaimana caranya menang.
Akar persoalan
Pola pikir dan kegiatan bagaimana agar pasangan kandidat bisa menang sangat membuka peluang munculnya konflik di seputar Pilkada. Jika diamati lebih jeli, sebab munculnya konflik paling tidak akan disebabkan oleh beberapa hal. Munculnya konflik biasanya diawali dari proses rekrutmen pasangan calon pada partai/gabungan partai, kesalahan penyusunan daftar pemilih sementara/tetap, kesalahan rekapitulasi suara, masalah netralitas PNS, penyalahgunaan wewenang, kurangnya profesional dan independen KPUD/Panwas, keterlambatan pengiriman logistik kelengkapan di TPS, pemberian honor PPK, PPS, dan KPPS, serta praktik politik uang.
Rekrutmen yang tidak transparan dan dengan semangat “yang penting menang” menjadi sumbu awal munculnya konflik. Bahkan, ada calon yang merasa akan lolos menjadi calon jadi ternyata tidak jadi juga memicu munculnya konflik. Ini bisa muncul jika ada campur tangan struktur di atasnya. Misalnya, partai “x” menjagokan kandidat dari pimpinan partai di daerahnya, ternyata itu tidak disetujui oleh pimpinan wilayah atau pusat. Lalu, muncullah konflik. Konflik ini akan terus berlanjut sampai selesai Pilkada, apalagi calon yang “direstui” atasan akhirnya keluar sebagai pemenang.
Penyusunan daftar pemilih juga rawan konflik. Misalnya, di sebuah daerah yang menjadi basis partai tertentu, ternyata daftar pemilihnya banyak yang salah atau tidak terdaftar. Calon dari partai yang mengharapkan bisa mendulang suara dari daerah ini tentu tidak akan menerimanya.
Yang agak rawan saat rekapitulasi suara. Bagi pasangan yang secara ekspos media gencar dengan pendukung banyak saat kampanye tapi ternyata kalah akan menduga ada kecurangan dibalik penghitungan suara. Padahal, realitas sebelum dan saat pemungutan suara punya perbedaan yang signifikan. Bisa jadi seorang yang sebelumnya mendukung pasangan kandidat, tetapi pada hari pemungutan suara justru mendukung pasangan kandidat yang lain.
Netralitas dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi problem tersendiri. Lihat saja di Pilkada Ngawi. Hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Ngawi ditolak oleh empat pasangan calon bupati-wakil bupati. Bahkan, pasangan yang memprotes merasa menemukan penyalahgunaan wewenang pasangan kandidat. Pasangan kandidat yang menang dituduh memanfaatkan fasilitas sebagai pejabat untuk meraih keuntungan pribadi. Pertanyaannya, mengapa baru dimunculkan saat pasangan itu meraih suara terbanyak? Orang akan menganggp karena empat pasangan itu kalah, memprotes dan mencari-cari kesalahan pasangan yang memang, meskipun pasangan yang menang itu bisa jadi melakukan kecurangan.
Yang krusial dan belum bisa ditemukan penyelesaian yang tepat adalah soal politik uang (money politics). Politik uang adalah cara yang jitu untuk memenangkan pertarungan, meskipun tidak elegan. Tetapi, semua pasangan jika mampu menggunakan uang, mereka akan menggunakannya. Mereka yang protes pada politik uang biasanya mereka yang tidak terlalu banyak menggunakan uang untuk memenangkan perharungan, meskipun juga tidak bisa dikatakan bersih dapi permainan politik uang.
Agar Berkualitas
Lantas, bagaimana agar Pilkada bisa berkualitas? Menghilangkan kecurangan-kecurangan saat pemilihan kepala daerah memang tidak gampang dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah dengan menekan kecurangan itu. Mengapa susah? Sebab, Pilkada itu proses politik yang (sering) “menghalalkan” segala cara untuk menang. Semua kandidat, diakui atau tidak, punya kecenderungan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Entah mencampuradukkan jabatannya sebagai pegawai pemerintah, pemimpin organisasi tertentu atau cara lain yang lebih halus yang tujuannya mengenalkan pasangan kandidat. Jika cara-cara ini tidak bisa ditekan, kecurangan dan konflik akan terus terbuka lebar.
KPU dan Panwas juga tidak bisa steril dari kecurangan. Di sinilah dibutuhkan lembaga independen yang kredibel dan diisi oleh orang-orang yang profesional. Sangat sulit sebagai lembaga independen jika tahap pemilihannya juga sarat politik.
Yang tak kalah krusialnya adalah jabatan politik di Indonesia masih dijadikan alat untuk mencari popularitas dan mendapatkan pendapatan (pekerjaan). Karena tujuannya untuk mendapatkan popularitas dan gaji, apapun dan cara bagaimanapun akan dilakukan. Lepas dari motif yang melatarbelakanginya, mengapa kedua istri bupati Kediri maju menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerh kediri? Mengapa pula banyak para istri dan keluarga kepala daerah perlu ikut-ikutan menjadi calon pemimpin di daerah? Bukti bahwa jabatan kepala daerah sangat diminati meskipun bisa menyilaukan mata.
Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Barangkali pendapat Lord Acton itu sampai saat ini masih relevan. Jadi, menjadi kepala daerah terbuka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bukan?.
Penulis, staf pengajar Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan pegiat di Rumah Baca Cerdas (RBC)
Sumber Radar Surabaya, Sabtu: 22 Mei 2010
Type rest of the post here Readmore »»
(Radar Surabaya, Sabtu: 22 Mei 2010)
Sejumlah daerah di Jawa Timur akan dan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagaimana pemilihan selama ini, gebyar untuk menyambut pesta demokrasi daerah itu sudah dilakukan. Tak jarang karena semangatnya, para kandidat yang belum tentu menjadi calon sudah memasang baliho di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, karena tujuannya mengenalkan diri pada pemilih, sering tidak memperhatikan estetika pemasangan, melanggar ruang publik, dan merusak pemandangan. Semua itu dilakukan untuk menyambut Pilkada.
Menyambut Pilkada dengan gebyar yang heboh memang tidak salah. Tetapi, mencoba berpikir lebih jernih agar kualitas Pilkada menjadi lebih baik suatu keharusan. Sayang, tak banyak – untuk menyebutkan tidak ada – para calon yang berpikir dalam jangka panjang. Umumnya, mereka berpikir dalam jangka pendek yakni bagaimana caranya menang.
Akar persoalan
Pola pikir dan kegiatan bagaimana agar pasangan kandidat bisa menang sangat membuka peluang munculnya konflik di seputar Pilkada. Jika diamati lebih jeli, sebab munculnya konflik paling tidak akan disebabkan oleh beberapa hal. Munculnya konflik biasanya diawali dari proses rekrutmen pasangan calon pada partai/gabungan partai, kesalahan penyusunan daftar pemilih sementara/tetap, kesalahan rekapitulasi suara, masalah netralitas PNS, penyalahgunaan wewenang, kurangnya profesional dan independen KPUD/Panwas, keterlambatan pengiriman logistik kelengkapan di TPS, pemberian honor PPK, PPS, dan KPPS, serta praktik politik uang.
Rekrutmen yang tidak transparan dan dengan semangat “yang penting menang” menjadi sumbu awal munculnya konflik. Bahkan, ada calon yang merasa akan lolos menjadi calon jadi ternyata tidak jadi juga memicu munculnya konflik. Ini bisa muncul jika ada campur tangan struktur di atasnya. Misalnya, partai “x” menjagokan kandidat dari pimpinan partai di daerahnya, ternyata itu tidak disetujui oleh pimpinan wilayah atau pusat. Lalu, muncullah konflik. Konflik ini akan terus berlanjut sampai selesai Pilkada, apalagi calon yang “direstui” atasan akhirnya keluar sebagai pemenang.
Penyusunan daftar pemilih juga rawan konflik. Misalnya, di sebuah daerah yang menjadi basis partai tertentu, ternyata daftar pemilihnya banyak yang salah atau tidak terdaftar. Calon dari partai yang mengharapkan bisa mendulang suara dari daerah ini tentu tidak akan menerimanya.
Yang agak rawan saat rekapitulasi suara. Bagi pasangan yang secara ekspos media gencar dengan pendukung banyak saat kampanye tapi ternyata kalah akan menduga ada kecurangan dibalik penghitungan suara. Padahal, realitas sebelum dan saat pemungutan suara punya perbedaan yang signifikan. Bisa jadi seorang yang sebelumnya mendukung pasangan kandidat, tetapi pada hari pemungutan suara justru mendukung pasangan kandidat yang lain.
Netralitas dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi problem tersendiri. Lihat saja di Pilkada Ngawi. Hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Ngawi ditolak oleh empat pasangan calon bupati-wakil bupati. Bahkan, pasangan yang memprotes merasa menemukan penyalahgunaan wewenang pasangan kandidat. Pasangan kandidat yang menang dituduh memanfaatkan fasilitas sebagai pejabat untuk meraih keuntungan pribadi. Pertanyaannya, mengapa baru dimunculkan saat pasangan itu meraih suara terbanyak? Orang akan menganggp karena empat pasangan itu kalah, memprotes dan mencari-cari kesalahan pasangan yang memang, meskipun pasangan yang menang itu bisa jadi melakukan kecurangan.
Yang krusial dan belum bisa ditemukan penyelesaian yang tepat adalah soal politik uang (money politics). Politik uang adalah cara yang jitu untuk memenangkan pertarungan, meskipun tidak elegan. Tetapi, semua pasangan jika mampu menggunakan uang, mereka akan menggunakannya. Mereka yang protes pada politik uang biasanya mereka yang tidak terlalu banyak menggunakan uang untuk memenangkan perharungan, meskipun juga tidak bisa dikatakan bersih dapi permainan politik uang.
Agar Berkualitas
Lantas, bagaimana agar Pilkada bisa berkualitas? Menghilangkan kecurangan-kecurangan saat pemilihan kepala daerah memang tidak gampang dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah dengan menekan kecurangan itu. Mengapa susah? Sebab, Pilkada itu proses politik yang (sering) “menghalalkan” segala cara untuk menang. Semua kandidat, diakui atau tidak, punya kecenderungan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Entah mencampuradukkan jabatannya sebagai pegawai pemerintah, pemimpin organisasi tertentu atau cara lain yang lebih halus yang tujuannya mengenalkan pasangan kandidat. Jika cara-cara ini tidak bisa ditekan, kecurangan dan konflik akan terus terbuka lebar.
KPU dan Panwas juga tidak bisa steril dari kecurangan. Di sinilah dibutuhkan lembaga independen yang kredibel dan diisi oleh orang-orang yang profesional. Sangat sulit sebagai lembaga independen jika tahap pemilihannya juga sarat politik.
Yang tak kalah krusialnya adalah jabatan politik di Indonesia masih dijadikan alat untuk mencari popularitas dan mendapatkan pendapatan (pekerjaan). Karena tujuannya untuk mendapatkan popularitas dan gaji, apapun dan cara bagaimanapun akan dilakukan. Lepas dari motif yang melatarbelakanginya, mengapa kedua istri bupati Kediri maju menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerh kediri? Mengapa pula banyak para istri dan keluarga kepala daerah perlu ikut-ikutan menjadi calon pemimpin di daerah? Bukti bahwa jabatan kepala daerah sangat diminati meskipun bisa menyilaukan mata.
Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Barangkali pendapat Lord Acton itu sampai saat ini masih relevan. Jadi, menjadi kepala daerah terbuka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bukan?.
Penulis, staf pengajar Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan pegiat di Rumah Baca Cerdas (RBC)
Sumber Radar Surabaya, Sabtu: 22 Mei 2010
Type rest of the post here Readmore »»
Langganan:
Postingan (Atom)