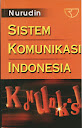PERUBAHAN peta koa-lisi menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak lagi dihitung dengan harian, bahkan setiap jam. Setiap saat para elite politik sibuk dengan urusan bagaimana membangun koalisi yang menguntungkan. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan koalisi. Semangat untuk melakukan koalisi adalah ”Saya mendapatkan apa, dan apa yang bisa saya manfaatkan dari orang lain”.
Koalisi adalah cara untuk membangun pemerintahan yang kuat. Ini dimungkinkan karena tak ada partai politik yang menang mutlak. Sehingga koalisi menjadi sebuah keniscayaan. Koalisi juga membuat para elite politik dilatih untuk berbagi dan tidak egois karena akan terjadi tarik ulur antara ambisi, hak, dan kerelaan berbagi satu sama lain.
Menggugat Koalisi
Namun demikian, melihat proses terjadinya koalisi antar elite politik selama ini, koalisi yang dibangun sudah ”jauh panggang dari api”. Beberapa catatan yang bisa dikemukakan antara lain; pertama, koalisi masih bersifat elitis. Proses koalisi hanya melibatkan segelintir orang saja. Bahkan hanya melibatkan salah satu orang saja.
Lihat misalnya beberapa partai besar (misalnya Partai Demokrat, PDI-P) memberikan mandat kepada calonnya untuk menentukan cawapres sendiri. Seolah urusan koalisi hanya urusan pribadi. Bisa jadi sebagai sebuah penghormatan pada sang calon, tetapi itu seolah menempatkan urusan partai dan koalisi hanya pada elite parpol yang bersangkutan.
Memang, itu adalah risiko demokrasi perwakilan. Artinya, rakyat menitipkan suaranya pada para elite politik tertentu (parpol atau caleg). Dalam posisi ini, urusan rakyat dianggap sudah selesai ketika ia telah menggunakan hak pilihnya. Ini sangat berbeda dengan saat menjelang ”hari pencontrengan”. Seolah-olah para elite politik itu merasa harus dekat, dan membutuhkan (bahkan sampai mengemis) dukungan rakyat. Apa pun dilakukan, termasuk dengan politik uang.
Tetapi, setelah masyarakat penggunaan hak pilih, urusan dianggap sudah selesai. Mereka yang hiruk pikuk minta dukungan rakyat sekarang sudah tiarap. Dengan kata lain, para elite politik itu sudah tidak lagi membutuhkan suara mereka. Tak heran, jika koalisi sangat bersifat elitis sekali karena hanya dilakukan sejumlah orang dengan mengebiri hak-hak rakyat yang memilihnya.
Kedua, koalisi hanya bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Yang ada dalam benak para elite politik itu adalah kekuasaan. Buntut perbedaan pendapat yang melanda sejumlah parpol (Partai Golkar, PAN, PPP) ujungnya juga pada kekuasaan tersebut.
Itu juga termasuk ketika dalam koalisi akan terjadi kesepakatan-kesepakatan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Kalau sebuah parpol ikut dalam koalisi, maka ia akan ”meminta jatah” jabatan tertentu, entah menteri atau jabatan politik lainnya.
Sementara itu, parpol kuat atau peraih paling banyak diantara peserta koalisi harus rela membagi kekuasaan dengan parpol lain. Ia tidak bisa mengangkangi kekuasaan sendiri saja. Terhadap kasus ini, rakyat tidak punya kekuasaan apa-apa. Semua sudah dilakukan elite politik, bahkan ”atas nama” rakyat.
Ketiga, koalisi menyakiti hati rakyat. Rakyat yang mempunyai republik ini harus dikebiri hak-haknya sedemikian rupa di bawah segelintir elite politik. Barangkali, saat ini rakyat belum merasakan apa-apa. Namun demikian, jika nanti para peserta koalisi itu sudah berkuasa dan tidak memikirkan kepentingan, hajat hidup, dan aspirasi rakyat, mereka baru akan merasakan ketidakberpihakan elite politik itu pada rakyatnya.
Dengan kata lain, mereka sebenarnya sudah menyakiti hari rakyatnya saat membangun koalisi, suatu saat akan diulang dengan perangkat kebijakan yang tak memihak ke rakyatnya.
Sejarah republik ini sudah menunjukkan bukti-bukti empirik ketika para elite politik sudah lupa pada rakyatnya. Mereka yang pernah meneriakkan demi rakyat, berjanji untuk kepentingan rakyat sudah hilang. Mereka, juga akan enggan untuk terjun langsung (layaknya saat kampanye) ketika sudah menduduki jabatan politik tertentu.
Mereka akan mementingkan diri dan kelompoknya, tidak peduli bagaimana susahnya rakyat. Lihat saja, bagaimana para anggota DPR periode sebelum ini meminta kenaikan gaji yang drastis sementara krisis ekonomi sedang melanda bangsa ini?
Banyak Belajar
Koalisi sebenarnya adalah sebuah proses ketika elite politik perlu belajar bagaimana merumuskan kesepakatan bersama di tengah kepentingan yang berbeda. Koalisi sebenarnya menganggap bahwa para politisi itu belum dianggap dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga, mereka diharuskan untuk saling belajar. Inilah keuntungannya jika Pemilu tidak menghasilkan pemenang mayoritas.
Zaman Orde Baru (Orba) tidak pernah mengajarkan pada elite politik bagaimana saling berbagi kekuasaan satu sama lain. Semua diputuskan secara individual dan kelompok tertentu dengan terus mengebiri kepentingan rakyat dan kemerdekaan elite politik itu sendiri dalam menentukan pilihan.
Itulah kenapa koalisi seharusnya memberikan banyak pelajaran pada elite politik. Hanya masalahnya, koalisi dianggap selesai setelah kesepakatan terjadi. Entah apakah kesepakatan itu akan dipatuhi atau tidak. Jika koalisi didasari oleh keinginan untuk benar sendiri, hasil koalisi itu tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik, baik menyangkut kepentingan mereka yang terlibat koalisi, pemerintahan, dan apalagi rakyat.
Koalisi sering dianggap hanya sekadar kumpul-kumpul untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Jika kue yang diperebutkan sedikit dan ada yang serakah, maka dengan mudahnya kesepakatan koalisi dilanggar.
Rakyat yang mempunyai republik ini telah dikebiri hak-haknya sedemikian rupa
di bawah segelintir elite politik.Barangkali, saat ini rakyat belum merasakan apa-apa. Namun demikian, mereka baru akan merasakan ketidakberpihakan elite politik.
Dalam koalisi sering sudah ada kesepakatan, partai ini akan mendapat jatah menteri sekian, partai lain mendapat jatah menteri juga sekian. Dalam posisi ini, koalisi dianggap hanya jatah menjatah kekuasaan, parpol mana yang mendapat jatah menteri paling banyak dan mana yang paling sedikit dan mana yang tidak mendapat. Jika ada parpol mendapatkan suara banyak sementara mendapat jatah menteri sedikit, jelas parpol itu tidak akan setuju, untuk tak mengatakan akan memberontak.
Maka, koalisi harus dikembalikan pada makna sebenarnya. Ia adalah sebuah kesepatan politik (entah untuk bagi-bagi kekuasaan, wewenang, ucapan terima kasih atau apapun istilahnya) yang tujuan utamanya tetap pada kemaslahatan rakyat. Artinya, kepentingan rakyat adalah nomor satu. Sering kali, ide ini hanya ada dalam wacana, seminar-seminar dan materi kuliah. Dalam praktiknya sulit dilaksanakan. Tetapi ini tidak berarti bahwa ide untuk mengingatkan agar koalisi dikembalikan pada posisi sebenarnya harus berhenti kerena tidak sesuai dengan praktik nyata. Sekecil apa pun suara untuk mengembalikan pada posisi sebenarnya tetap penting. Ia ibarat oase di tengah padang pasir yang tandus.
Koalisi memang kepentingan, tetapi kepentingan yang harus diletakkan pada kepentingan rakyat. Jika tidak, maka rakyat yang pada dasarnya sudah ”dikebiri” kepentingannya saat koalisi terjadi, akan semakin menjadi sakit hati. Untuk itulah mereka tidak boleh menyakitinya untuk yang kedua kalinya setelah koalisi terbentuk. Dengan kata lain, pemerintahan hasil koalisi harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Hanya pemerintahan seperti itulah yang akan mendapatkan mandat tulus dari rakyatnya. Semoga para elite politik yang terlibat koalisi dan berpeluang menduduki jabatan politik seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati, Prabowo, dan Wiranto masih berkhidmat pada kepentingan rakyat dan bangsa ini. (80)
sumber: harian Suara Merdeka, 30 April 2009.
Readmore »»
Kamis, April 23, 2009
Partai Golkar Sebagai Oposisi?
Setelah Pemilihan legislatif usai, salah satu partai politik (parpol) yang mengalami kebimbangan adalah Partai Golkar (PG). Sebab, inilah pemilihan legislatif yang memberikan dampak di luar prediksi sebelumnya. Golkar pada Pemilu 2004 mampu meraih 21,6 persen suara. Sementara itu dalam penghitungan sementara Pemilu 2009 perolehan suara PG belum melebihi 15 persen, bahkan sulit menembus 20-an persen lagi. Pada posisi yang berbeda Partai Demokrat yang pada Pemilu 2004 hanya memperoleh suara 7,5 persen, sekarang melonjak menjadi 20 persen.
Untuk itu, PG dihinggapi kebimbangan. Target sebelumnya, PG berkeinginan mendudukkan wakilnya sebagai calon presiden (capres) dengan mencari calon wakil presiden (cawapres) dari partai lain. Bayangannya, akan mencapai 20 persen seperti 5 tahun lalu. Tetapi saat ini PG harus realistis dengan tidak terlalu ngotot menempatkan wakilnya sebagai capres, tetapi cawapres.
Dua Pilihan
Maka, ada dua pilihan yang akan dihadapi PG; pertama, menempatkan wakilnya sebagai cawapres. Kedua, menjadi partai oposisi. Dua pilihan itu akan menjadi wacana aktual peta perpolitikan PG dalam waktu dekat.
Jika alternatif pertama yang dipilih, maka PG kemungkinan akan ikut mengelola negara ini kembali. Ia akan menjadi partai pemerintah. Tetapi, melihat perolehan suara yang didapat, maka ia sangat mungkin menjadi “ban serep” partai lain yang lebih besar dalam perolehan suaranya.
Keuntungan pilihan pertama ini, PG masih bisa ikut mengelola negara. Wakil PG yang kebetulan menjadi cawapres misalnya, akan mudah mendapatkan popularitas sebagai pejabat publik. Lima tahun berikutnya, PG akan bisa menentukan calonnya sebagai presiden. Tentu dengan syarat memperoleh suara yang signifikan. Ini tentu peluang besar. Sebab, tidak mungkin SBY akan menjadi calon untuk ketiga kalinya (jika seandainya ia terpilih kembali pada tahun ini).
Jika PG ikut dalam pemerintahan, maka perolehan suara lima tahun mendatang bisa jadi mengalami penurunan. Mengapa? Positioning PG sebagai partai pemerintah dan pernah berkuasan di zaman orde baru (Orba) dengan segala “kejahatannya” masih melekat di benak masyarakat. Era Orba, PG (waktu itu masih bernama Golkar) punya mesin kuat yakni ABRI, Birokrasi, dan Golkar sendiri (ABG). Golkar selalu mengklaim sebagai satau-satunya partai yang membangun bangsa ini. Nyatanya, memang bangsa ini waktu itu sedang membangun, sementara Golkar sedang berkuasa.
Tetapi untuk saat sekarang, apa yang akan “dijual” oleh PG? Masyarakat tidak akan percaya begitu saja jika partai itu melakukan pengklaiman sepihak atas keberhasilan pembangunan seperti zaman Orba. Apalagi perolehan suaranya tidak sebanyak pada era itu. Sementara itu, partai-partai lain sudah punya klaim masing-masing, baik menyangkut partai wong cilik, partai Islam, nasionalis, pluralis dan lain-lain. Dalam posisi inilah PG akan kehilangan isu yang akan digarap. Ini pulalah yang dirasakan PG selama ini.
Oposisi
Pilihan yang kedua adalah menjadi partai oposisi. Keuntungan menjadi partai oposisi antara lain; pertama, menunjukkan pada masyarakat sebagai partai yang kritis untuk meraih simpati rakyat. Jika PG menjadi partai oposisi, ia akan sibuk untuk menjadi partner pemerintah di luar pemerintahan. Ia akan menjadi penyeimbang, mengkritik, dan meluruskan yang bengkok terhadap kebijakan pemerintah. Jika pemerintah melakukan tindakan yang merugikan pemerintah, ia harus tampil di muka.
Namun kelemahannya, PG akan dianggap sebagai “partai barisan sakit hati” karena gagal terlibat dalam pemerintahan. Sehingga, bisanya “menganggu” pemerintah saja. Namun demikian, oposisi di sini harus dilakukan dengan cerdas, bukan sekadar hantam kromo saja. Masyarakat sudah semakin maju tingkat pendidikannya dan tahu mana yang sekadar mengkritik dengan kebencian, mana yang mengkritik untuk membangun.
Dari pilihan ini, diharapkan simpati masyarakat kian meningkat pula. Tentu saja dengan terus memperlebar jaringan, mengokohkan akar di grass root, dan memunculkan isu-isu yang cerdas menyangkut masyarakat. Sebab jika tidak hati-hati, justru masyarakat akan semakin muak karena ia menjadi partai oposisi yang asal beda, mengkritik saja, dan mencari-cari kesalahan pemerintah disebabkan “sakit hati”. Padahal partai itu kalah dalam kompetisi politik dalam Pemilu 2009.
Kedua, menghilangkan beban masa lalu. Tidak bisa dipungkiri masyarakat masih menyimpan trauma atas keberadaan PG. Ia adalah partai penguasa Orba dengan segala “keserakahannya”. Kalau PG mendapatkan suara banyak selama ini karena jaringan “mesin” politiknya saja. Ia telah dikenal masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Sementara partai-partai baru belum dikenalnya.
Dengan menjadi oposisi, maka beban masa lalu PG akan sedikit hilang dalam ingatan masyarakat. Sebab, bangsa ini terkenal dengan bangsa pelupa. Hal ini pernah disindir Milan Kundera. Dalam bukunya The Books of Laughter and Forgetting, ia pernah mengatakan bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa. Bangsa ini sering dituduh sebagai bangsa yang gampang melupakan dosa-dosa masa lalu, kekerasan masa lalu, kejahatan masa lalu dan penyimpangan lain di masa lalu.
Agaknya, sindiran Kundera itu begitu mengena pada diri bangsa Indonesia. Ada banyak peristiwa yang dilupakan atau sengaja dilupakan hanya karena kita ingin disebut sebagai bangsa baik hati atau karena terlalu picik. Bagaimana kelanjutan proses kasus KKN yang melibatkan pemimpin era Orba?
Untuk itulah, kenyataan ini bisa dimanfaatkan PG dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita setuju untuk “mengubur” kebobrokan” masa lalu. Tetapi, bangsa ini memang menjadi bangsa pelupa. PG bisa menjadikan momentum ini untuk mundur terlebih dulu, kemudian maju selangkah demi selangkah untuk meraih kemenangan. Tentu, ia membutuhkan proses yang tidak singkat.
Masalahnya, menjadi oposisi jelas akan ditentang oleh fungsionaris PG yang punya ambisi jabatan atau ingin ikut berkuasa. Orang-orang ini jelas akan mendukung PG sebagai partai yang terus ikut memerintah. Alasannya, mereka bisa menjadi menteri atau pejabat tinggi lain. Kalau sudah begini, kemunduran PG di masa datang tinggal menunggu waktu saja. Ia akan menjadi partai pemerintah yang akan terus disorot publik dengan segala keburukannya.
Sumber: Harian Joglosemar, 23 April 2009
Readmore »»
Untuk itu, PG dihinggapi kebimbangan. Target sebelumnya, PG berkeinginan mendudukkan wakilnya sebagai calon presiden (capres) dengan mencari calon wakil presiden (cawapres) dari partai lain. Bayangannya, akan mencapai 20 persen seperti 5 tahun lalu. Tetapi saat ini PG harus realistis dengan tidak terlalu ngotot menempatkan wakilnya sebagai capres, tetapi cawapres.
Dua Pilihan
Maka, ada dua pilihan yang akan dihadapi PG; pertama, menempatkan wakilnya sebagai cawapres. Kedua, menjadi partai oposisi. Dua pilihan itu akan menjadi wacana aktual peta perpolitikan PG dalam waktu dekat.
Jika alternatif pertama yang dipilih, maka PG kemungkinan akan ikut mengelola negara ini kembali. Ia akan menjadi partai pemerintah. Tetapi, melihat perolehan suara yang didapat, maka ia sangat mungkin menjadi “ban serep” partai lain yang lebih besar dalam perolehan suaranya.
Keuntungan pilihan pertama ini, PG masih bisa ikut mengelola negara. Wakil PG yang kebetulan menjadi cawapres misalnya, akan mudah mendapatkan popularitas sebagai pejabat publik. Lima tahun berikutnya, PG akan bisa menentukan calonnya sebagai presiden. Tentu dengan syarat memperoleh suara yang signifikan. Ini tentu peluang besar. Sebab, tidak mungkin SBY akan menjadi calon untuk ketiga kalinya (jika seandainya ia terpilih kembali pada tahun ini).
Jika PG ikut dalam pemerintahan, maka perolehan suara lima tahun mendatang bisa jadi mengalami penurunan. Mengapa? Positioning PG sebagai partai pemerintah dan pernah berkuasan di zaman orde baru (Orba) dengan segala “kejahatannya” masih melekat di benak masyarakat. Era Orba, PG (waktu itu masih bernama Golkar) punya mesin kuat yakni ABRI, Birokrasi, dan Golkar sendiri (ABG). Golkar selalu mengklaim sebagai satau-satunya partai yang membangun bangsa ini. Nyatanya, memang bangsa ini waktu itu sedang membangun, sementara Golkar sedang berkuasa.
Tetapi untuk saat sekarang, apa yang akan “dijual” oleh PG? Masyarakat tidak akan percaya begitu saja jika partai itu melakukan pengklaiman sepihak atas keberhasilan pembangunan seperti zaman Orba. Apalagi perolehan suaranya tidak sebanyak pada era itu. Sementara itu, partai-partai lain sudah punya klaim masing-masing, baik menyangkut partai wong cilik, partai Islam, nasionalis, pluralis dan lain-lain. Dalam posisi inilah PG akan kehilangan isu yang akan digarap. Ini pulalah yang dirasakan PG selama ini.
Oposisi
Pilihan yang kedua adalah menjadi partai oposisi. Keuntungan menjadi partai oposisi antara lain; pertama, menunjukkan pada masyarakat sebagai partai yang kritis untuk meraih simpati rakyat. Jika PG menjadi partai oposisi, ia akan sibuk untuk menjadi partner pemerintah di luar pemerintahan. Ia akan menjadi penyeimbang, mengkritik, dan meluruskan yang bengkok terhadap kebijakan pemerintah. Jika pemerintah melakukan tindakan yang merugikan pemerintah, ia harus tampil di muka.
Namun kelemahannya, PG akan dianggap sebagai “partai barisan sakit hati” karena gagal terlibat dalam pemerintahan. Sehingga, bisanya “menganggu” pemerintah saja. Namun demikian, oposisi di sini harus dilakukan dengan cerdas, bukan sekadar hantam kromo saja. Masyarakat sudah semakin maju tingkat pendidikannya dan tahu mana yang sekadar mengkritik dengan kebencian, mana yang mengkritik untuk membangun.
Dari pilihan ini, diharapkan simpati masyarakat kian meningkat pula. Tentu saja dengan terus memperlebar jaringan, mengokohkan akar di grass root, dan memunculkan isu-isu yang cerdas menyangkut masyarakat. Sebab jika tidak hati-hati, justru masyarakat akan semakin muak karena ia menjadi partai oposisi yang asal beda, mengkritik saja, dan mencari-cari kesalahan pemerintah disebabkan “sakit hati”. Padahal partai itu kalah dalam kompetisi politik dalam Pemilu 2009.
Kedua, menghilangkan beban masa lalu. Tidak bisa dipungkiri masyarakat masih menyimpan trauma atas keberadaan PG. Ia adalah partai penguasa Orba dengan segala “keserakahannya”. Kalau PG mendapatkan suara banyak selama ini karena jaringan “mesin” politiknya saja. Ia telah dikenal masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Sementara partai-partai baru belum dikenalnya.
Dengan menjadi oposisi, maka beban masa lalu PG akan sedikit hilang dalam ingatan masyarakat. Sebab, bangsa ini terkenal dengan bangsa pelupa. Hal ini pernah disindir Milan Kundera. Dalam bukunya The Books of Laughter and Forgetting, ia pernah mengatakan bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa. Bangsa ini sering dituduh sebagai bangsa yang gampang melupakan dosa-dosa masa lalu, kekerasan masa lalu, kejahatan masa lalu dan penyimpangan lain di masa lalu.
Agaknya, sindiran Kundera itu begitu mengena pada diri bangsa Indonesia. Ada banyak peristiwa yang dilupakan atau sengaja dilupakan hanya karena kita ingin disebut sebagai bangsa baik hati atau karena terlalu picik. Bagaimana kelanjutan proses kasus KKN yang melibatkan pemimpin era Orba?
Untuk itulah, kenyataan ini bisa dimanfaatkan PG dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita setuju untuk “mengubur” kebobrokan” masa lalu. Tetapi, bangsa ini memang menjadi bangsa pelupa. PG bisa menjadikan momentum ini untuk mundur terlebih dulu, kemudian maju selangkah demi selangkah untuk meraih kemenangan. Tentu, ia membutuhkan proses yang tidak singkat.
Masalahnya, menjadi oposisi jelas akan ditentang oleh fungsionaris PG yang punya ambisi jabatan atau ingin ikut berkuasa. Orang-orang ini jelas akan mendukung PG sebagai partai yang terus ikut memerintah. Alasannya, mereka bisa menjadi menteri atau pejabat tinggi lain. Kalau sudah begini, kemunduran PG di masa datang tinggal menunggu waktu saja. Ia akan menjadi partai pemerintah yang akan terus disorot publik dengan segala keburukannya.
Sumber: Harian Joglosemar, 23 April 2009
Readmore »»
Minggu, Maret 29, 2009
Diskusi Sebagai Sumber Gagasan Menulis
Siang itu jam menunjukkan pukul 10.30 WIB. Saya ada di laboratorium komputer kampus Fisip UNS. Saya dan teman di laboratorium itu sedang mengerjakan tugas. Saya sedang mengetik naskah untuk persiapan penerbitan majalah Visi Fisip UNS. Mendadak ada seorang teman memecah kesunyian.
“Eh, aku cabut dulu, ya?”, kata Upik.
“Kemana?”, tanya saya lebih lanjut.
“Mau lihat tivi”.
“Emangnya ada acara apa Pik?”
“Kassandra”
“Alah....” gerutu teman-teman saya agak berbarengan.
Setelah saya pulang ke kos-kosan saya jadi berpikir, mengapa teman-teman mahasiswi itu sangat menyukai telenovela? Bahkan ibu-ibu rumah tangga saat Maria Mercedes diputar jam 5 sore, sibuk memelototi pesawat televisi. Seolah tidak ingin ketinggalan ceritanya. Mengapa pula banyak televisi swasta memutar telenovela? Per
tanyaan saya tersebut di atas semakin mendesak untuk dicarikan jawabannya.
Rasa penasaran itu memuncak ketika saya ingin mengeluarkan uneg-uneg tersebut dalam sebuah artikel. Tetapi, saya tidak punya banyak referensi untuk membahas masalah telenovela. Acara itu digemari para ibu-ibu dan remaja putri saya tahu, tetapi berbagai macam data berkaitan dengannya saya sangat kurang.
Maka, saya memutuskan untuk main ke teman kos yang saat itu suka telenovela. Setelah sampai di kosnya, saya terlibat diskusi dengan dia.
“Telenovela itu kan membodohi penonton, apa alasannya sampai kamu tergila-gila?” tanya saya sok tahu.
“Kata siapa? Telenovela itu kan hiburan, kita harus tempatkan acara seperti itu sebagai hiburan juga,” jawabnya agak sewot.
“Bisa juga sih, tapi coba lihat dampaknya?”
“Karena hiburan, maka porsi menghiburkan juga besar. Kita harus tahu itu. Perkara ada yang kecanduan, itu soal lain. Kalau saya kan tidak”
“Lalu?”
“Kenapa banyak yang menonton, itu kan cermin masyarakat kita yang memang masih seperti itu. Artinya, masyarakat menempatkan TV sebagai barang tontotan untuk mencari hiburan, lainnya tidak. Apalagi, pengelola TV juga berlomba-lomba membuat acara seperti itu. Lihat berapa banyak telenovela diputar di stasiun televisi swasta kita. Banyak kan? Padahal sebelumnya hanya coba-coba”
“Baik, tapi begini. Telenovela telah berdampak negatif pada ibu-ibu rumah tangga. Setiap jam lima sore mereka nongkrong di pesawat televisi untuk menonton telenovela. Mereka mengorbankan kegiatan keluarga juga, “ tanya saya sok tahu.
“Ya itulah yang saya katakan tadi, cermin masyarakat kita yang masih seperti itu. Yang terjadi di telenovela seolah melekat dan menjadi impian para remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga. Lihat telenovela Kassandra yang disiarkan SCTV itu. Si gadis Gypsi (Corraima Tores) aslinya kan anak orang kaya. Ia hanya dibuang sama tantenya sendiri gara-gara si tante ingin warisan Kassandra jatuh ke anaknya (Osvaldo Rios). Tapi namanya juga nasib, Kassandra balik lagi ke lingkungan keluarganya sendiri, tanpa dia tahu kalau Kassandra adalah pewaris tunggal harta orang tuanya. Siapa tahu penonton ingin punya nasib baik seperti Kassandra. Masyarakat kan jadi punya mimpi-mimpi, sementara pemerintah tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka? Jadi, jangan hanya salahkan masyarakat, coba salahkan pemerintah dan juga pengelola televisi yang hanya mau untungnya saja”.
Setelah selesai berdiskusi, saya memutuskan untuk meninggalkan kos Upik. Saya baru saja mendapatkan pencerahan tentang telenovela yang sedang digandrungi mahasiswi dan ibu rumah tangga akhir-akhir ini. Tetapi, saya masih bingung. Bukankah tulisan yang saya dasarkan dari diskusi dengan Upik tersebut terkesan berat sebelah? Mungkin. Sebab, Upik adalah pembela tayangan telenovela.
Agar tulisan saya lebih berimbang saya harus pergi ke teman lain yang tidak suka telenovela. Kebetulan saya punya teman yang aktivis. Saya akan mencari keterangan tentang telenovela dari teman saya itu, sebut saja namanya Dini.
“Kenapa kamu tidak suka telenovela layaknya para perempuan saat ini?” tanya saya.
“Ah, enggak. Untuk apa?. Wong telenovela hanya menjual mimpi-mimpi saja kok,” jawab dia agak ketus.
“Ah masak?” saya pura-pura tidak tahu.
“Coba lihat. Apakah yang diceritakan dalam telenovela itu sesuai kenyataan dalam masyarakat. Kan tidak? Perhatikan lagi, ceritanya menjual mimpi saja. Ceritanya sudah bisa ditebak, mesti ada perempuan yang hidupnya sengsara. Dieksploitasi kesengsaraannya itu, dibumbui dengan konflik cinta dengan anak orang kaya. Perempuan tadi harus menerima perlakukan kasar dari calon pasangan anak orang kaya tadi. Kemudian, ada konflik masalah harta. Itu saja”.
“Lho bukankah hal demikian juga terjadi pada masyarakat kita?”
“Begini. Alur cerita telenovela itu hampir seragam dan cenderung dibuat-buat. Kalau tidak menyangkut percintaan, konflik orang tua dengan anak, masalah harta, selingkuh, hamil di luar nikah. Apakah itu budaya kita saat ini? Itu kan sama saja menjual mimpi? Atau jangan-jangan masyarakat kita terobsesi dengan bintang-bintangnya yang cantik atau ganteng?”
“Terus?”
“Ya, intinya menjual mimpi lah.”
“Tapi kan semua televisi swasta kita menanyangkan telenovela tersebut. Televisi kan cermin masyarakat?”
“Ya itu. Televisi kita sangat kapitalis, mementingkan modal tanpa melihat dampak tayangan. Bukankah seperti itu? Jika ada tayangan yang laku, mesti akan diikuti oleh TV-TV lain. Lihatlah dan buktikan. Kayak telenovela akhir-akhir ini, bukan?”
“Ya jangan sewot gitu ah,”
“Gak sewot gimana. Memang acara televisi kita umumnya cenderung membodohi penonton kok. Mau dikatakan bagaimana?”
Setelah berdiskusi agak lama, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Bahan untuk membuat tulisan tentang telenovela juga sudah cukup dari dua pihak.
Setelah sampai di kos. Saya kemudian membuka komputer. Lalu saya menulis apa yang yang sudah saya dapatkan dari diskusi dengan dua teman di atas. Menulis terasa cair, lancar dan tanpa hambatan.
Yang ingin saya tekankan adalah bahwa untuk menulis, diskusi dengan orang lain akan menjadi sumber gagasan yang penting. Ini penting dilakukan saat kita dalam keadaan bingung apa yang akan ditulis sementara sudah punya keinginan kuat untuk menulis. Diskusi juga akan membuat beragam perspektif ada dalam pikiran kita. Paling tidak, pikiran kita sendiri, dan apa yang didapat dari diskusi tersebut.
Masalahnya, tidak semua orang senang dengan diskusi. Sebab, untuk bisa berdiskusi kita harus punya kemampuan mendengar dan bukan kemampuan berbicara saja. Untuk ikut diskusi, kita tidak harus menguasai persoalan. Memang lebih bagus bisa menguasai persoalan, tetapi jangan hanya gara-gara tidak menguasai persoalan kita tidak mau ikut diskusi.
Diskusi juga bisa disengaja dengan melibatkan orang untuk diajak diskusi atau menjadi pendengar pasif. Yang penting, ikut dalam atmosfir diskusi, itu saja. Anggap saja kita sedang memasukkan sumber-sumber gagasan dalam pikiran. Dengan demikian, diskusi tidak harus diikuti ketika kita sedang mau menulis. Maka, banyaklah ikut diskusi, seminar, lokakarya dan semacamnya. Ada banyak sumber-sumber gagasan dalam acara-acara tersebut.
Apakah yang saya lakukan di atas bukan plagiat pikiran orang lain? Sebenarnya, apa yang ditulis oleh para penulis terkenal itu juga awalnya hanya meniru apa yang pernah dia baca, lihat, dengar dan alami sendiri. Kemudian sejalan dengan peningkatan skills menulis dan pengatahuan dia mempunyai “ramuan” sendiri, dan gaya sendiri dalam menulis. Kegiatan ini hampir sama seperti seorang bayi. Saat belajar jalan, ia akan meniru apa yang dilihatnya. Apakah ini tidak boleh? Dalam menulis, tidak jauh berbeda. Tapi, kita harus selalu berusaha melepasan bayang-bayang orang yang kita tiru itu secepat mungkin. Suatu saat, kita akan mempunyai gaya penulisan sendiri. Sekarang pilih mana, meniru gaya penulisan orang yang membuat kita belajar, dengan tidak pernah meniru tetapi kita tidak pernah bisa menulis?
Agar ide yang berasal dari orang lain tersebut tidak dikatakan plagiat, kita perlu mengolahnya dengan kata-kata dan kalimat kita sendiri. Karenanya, meniru suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi tetap berusaha untuk lepas dari kungkungan yang kita tiru tersebut.
Sebagai ucapan terima kasih pada teman yang kita ajak diskusi tersebut minimal berikan ucapan terima kasih karena telah membantu menulis. Atau traktir mereka makan juga tidak masalah. Ini lebih dari cukup. Bukankah kita bisa menulis juga karena peran mereka? Mengeluarkan uang untuk alokasi dan ke orang lain jangan dianggap pemborosan. Pahami pula bahwa itu sebuah investasi yang kita akan memetiknya di masa datang dalam jumlah yang lebih besar. Biarkan orang lain juga ikut menikmati rejeki yang kita dapatkan.
Readmore »»
“Eh, aku cabut dulu, ya?”, kata Upik.
“Kemana?”, tanya saya lebih lanjut.
“Mau lihat tivi”.
“Emangnya ada acara apa Pik?”
“Kassandra”
“Alah....” gerutu teman-teman saya agak berbarengan.
Setelah saya pulang ke kos-kosan saya jadi berpikir, mengapa teman-teman mahasiswi itu sangat menyukai telenovela? Bahkan ibu-ibu rumah tangga saat Maria Mercedes diputar jam 5 sore, sibuk memelototi pesawat televisi. Seolah tidak ingin ketinggalan ceritanya. Mengapa pula banyak televisi swasta memutar telenovela? Per
tanyaan saya tersebut di atas semakin mendesak untuk dicarikan jawabannya.
Rasa penasaran itu memuncak ketika saya ingin mengeluarkan uneg-uneg tersebut dalam sebuah artikel. Tetapi, saya tidak punya banyak referensi untuk membahas masalah telenovela. Acara itu digemari para ibu-ibu dan remaja putri saya tahu, tetapi berbagai macam data berkaitan dengannya saya sangat kurang.
Maka, saya memutuskan untuk main ke teman kos yang saat itu suka telenovela. Setelah sampai di kosnya, saya terlibat diskusi dengan dia.
“Telenovela itu kan membodohi penonton, apa alasannya sampai kamu tergila-gila?” tanya saya sok tahu.
“Kata siapa? Telenovela itu kan hiburan, kita harus tempatkan acara seperti itu sebagai hiburan juga,” jawabnya agak sewot.
“Bisa juga sih, tapi coba lihat dampaknya?”
“Karena hiburan, maka porsi menghiburkan juga besar. Kita harus tahu itu. Perkara ada yang kecanduan, itu soal lain. Kalau saya kan tidak”
“Lalu?”
“Kenapa banyak yang menonton, itu kan cermin masyarakat kita yang memang masih seperti itu. Artinya, masyarakat menempatkan TV sebagai barang tontotan untuk mencari hiburan, lainnya tidak. Apalagi, pengelola TV juga berlomba-lomba membuat acara seperti itu. Lihat berapa banyak telenovela diputar di stasiun televisi swasta kita. Banyak kan? Padahal sebelumnya hanya coba-coba”
“Baik, tapi begini. Telenovela telah berdampak negatif pada ibu-ibu rumah tangga. Setiap jam lima sore mereka nongkrong di pesawat televisi untuk menonton telenovela. Mereka mengorbankan kegiatan keluarga juga, “ tanya saya sok tahu.
“Ya itulah yang saya katakan tadi, cermin masyarakat kita yang masih seperti itu. Yang terjadi di telenovela seolah melekat dan menjadi impian para remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga. Lihat telenovela Kassandra yang disiarkan SCTV itu. Si gadis Gypsi (Corraima Tores) aslinya kan anak orang kaya. Ia hanya dibuang sama tantenya sendiri gara-gara si tante ingin warisan Kassandra jatuh ke anaknya (Osvaldo Rios). Tapi namanya juga nasib, Kassandra balik lagi ke lingkungan keluarganya sendiri, tanpa dia tahu kalau Kassandra adalah pewaris tunggal harta orang tuanya. Siapa tahu penonton ingin punya nasib baik seperti Kassandra. Masyarakat kan jadi punya mimpi-mimpi, sementara pemerintah tidak bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka? Jadi, jangan hanya salahkan masyarakat, coba salahkan pemerintah dan juga pengelola televisi yang hanya mau untungnya saja”.
Setelah selesai berdiskusi, saya memutuskan untuk meninggalkan kos Upik. Saya baru saja mendapatkan pencerahan tentang telenovela yang sedang digandrungi mahasiswi dan ibu rumah tangga akhir-akhir ini. Tetapi, saya masih bingung. Bukankah tulisan yang saya dasarkan dari diskusi dengan Upik tersebut terkesan berat sebelah? Mungkin. Sebab, Upik adalah pembela tayangan telenovela.
Agar tulisan saya lebih berimbang saya harus pergi ke teman lain yang tidak suka telenovela. Kebetulan saya punya teman yang aktivis. Saya akan mencari keterangan tentang telenovela dari teman saya itu, sebut saja namanya Dini.
“Kenapa kamu tidak suka telenovela layaknya para perempuan saat ini?” tanya saya.
“Ah, enggak. Untuk apa?. Wong telenovela hanya menjual mimpi-mimpi saja kok,” jawab dia agak ketus.
“Ah masak?” saya pura-pura tidak tahu.
“Coba lihat. Apakah yang diceritakan dalam telenovela itu sesuai kenyataan dalam masyarakat. Kan tidak? Perhatikan lagi, ceritanya menjual mimpi saja. Ceritanya sudah bisa ditebak, mesti ada perempuan yang hidupnya sengsara. Dieksploitasi kesengsaraannya itu, dibumbui dengan konflik cinta dengan anak orang kaya. Perempuan tadi harus menerima perlakukan kasar dari calon pasangan anak orang kaya tadi. Kemudian, ada konflik masalah harta. Itu saja”.
“Lho bukankah hal demikian juga terjadi pada masyarakat kita?”
“Begini. Alur cerita telenovela itu hampir seragam dan cenderung dibuat-buat. Kalau tidak menyangkut percintaan, konflik orang tua dengan anak, masalah harta, selingkuh, hamil di luar nikah. Apakah itu budaya kita saat ini? Itu kan sama saja menjual mimpi? Atau jangan-jangan masyarakat kita terobsesi dengan bintang-bintangnya yang cantik atau ganteng?”
“Terus?”
“Ya, intinya menjual mimpi lah.”
“Tapi kan semua televisi swasta kita menanyangkan telenovela tersebut. Televisi kan cermin masyarakat?”
“Ya itu. Televisi kita sangat kapitalis, mementingkan modal tanpa melihat dampak tayangan. Bukankah seperti itu? Jika ada tayangan yang laku, mesti akan diikuti oleh TV-TV lain. Lihatlah dan buktikan. Kayak telenovela akhir-akhir ini, bukan?”
“Ya jangan sewot gitu ah,”
“Gak sewot gimana. Memang acara televisi kita umumnya cenderung membodohi penonton kok. Mau dikatakan bagaimana?”
Setelah berdiskusi agak lama, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Bahan untuk membuat tulisan tentang telenovela juga sudah cukup dari dua pihak.
Setelah sampai di kos. Saya kemudian membuka komputer. Lalu saya menulis apa yang yang sudah saya dapatkan dari diskusi dengan dua teman di atas. Menulis terasa cair, lancar dan tanpa hambatan.
Yang ingin saya tekankan adalah bahwa untuk menulis, diskusi dengan orang lain akan menjadi sumber gagasan yang penting. Ini penting dilakukan saat kita dalam keadaan bingung apa yang akan ditulis sementara sudah punya keinginan kuat untuk menulis. Diskusi juga akan membuat beragam perspektif ada dalam pikiran kita. Paling tidak, pikiran kita sendiri, dan apa yang didapat dari diskusi tersebut.
Masalahnya, tidak semua orang senang dengan diskusi. Sebab, untuk bisa berdiskusi kita harus punya kemampuan mendengar dan bukan kemampuan berbicara saja. Untuk ikut diskusi, kita tidak harus menguasai persoalan. Memang lebih bagus bisa menguasai persoalan, tetapi jangan hanya gara-gara tidak menguasai persoalan kita tidak mau ikut diskusi.
Diskusi juga bisa disengaja dengan melibatkan orang untuk diajak diskusi atau menjadi pendengar pasif. Yang penting, ikut dalam atmosfir diskusi, itu saja. Anggap saja kita sedang memasukkan sumber-sumber gagasan dalam pikiran. Dengan demikian, diskusi tidak harus diikuti ketika kita sedang mau menulis. Maka, banyaklah ikut diskusi, seminar, lokakarya dan semacamnya. Ada banyak sumber-sumber gagasan dalam acara-acara tersebut.
Apakah yang saya lakukan di atas bukan plagiat pikiran orang lain? Sebenarnya, apa yang ditulis oleh para penulis terkenal itu juga awalnya hanya meniru apa yang pernah dia baca, lihat, dengar dan alami sendiri. Kemudian sejalan dengan peningkatan skills menulis dan pengatahuan dia mempunyai “ramuan” sendiri, dan gaya sendiri dalam menulis. Kegiatan ini hampir sama seperti seorang bayi. Saat belajar jalan, ia akan meniru apa yang dilihatnya. Apakah ini tidak boleh? Dalam menulis, tidak jauh berbeda. Tapi, kita harus selalu berusaha melepasan bayang-bayang orang yang kita tiru itu secepat mungkin. Suatu saat, kita akan mempunyai gaya penulisan sendiri. Sekarang pilih mana, meniru gaya penulisan orang yang membuat kita belajar, dengan tidak pernah meniru tetapi kita tidak pernah bisa menulis?
Agar ide yang berasal dari orang lain tersebut tidak dikatakan plagiat, kita perlu mengolahnya dengan kata-kata dan kalimat kita sendiri. Karenanya, meniru suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi tetap berusaha untuk lepas dari kungkungan yang kita tiru tersebut.
Sebagai ucapan terima kasih pada teman yang kita ajak diskusi tersebut minimal berikan ucapan terima kasih karena telah membantu menulis. Atau traktir mereka makan juga tidak masalah. Ini lebih dari cukup. Bukankah kita bisa menulis juga karena peran mereka? Mengeluarkan uang untuk alokasi dan ke orang lain jangan dianggap pemborosan. Pahami pula bahwa itu sebuah investasi yang kita akan memetiknya di masa datang dalam jumlah yang lebih besar. Biarkan orang lain juga ikut menikmati rejeki yang kita dapatkan.
Readmore »»
Kamis, Maret 26, 2009
Dari Mana Sumber Gagasan Menulis Muncul?

Pada bulan April 2008, saya menjadi pembicara dalam acara teknik menulis di Averroes Malang. Di awal acara, saya membagikan kertas kepada para peserta. Setelah mereka saya pastikan mendapatkan kertas, dan juga menyiapkan pulpen, kemudian saya memberi instruksi.
“Semua sudah mendapat kertas?” kata saya menegaskan.
“Sudah, “jawab mereka serentak.
“Sekarang, silakan kalian membuat sebuah tulisan singkat. Cukup satu alenia saja. Tulisan itu harus menjawab pertanyaan bagaimana cara mengaspal jalan!”
“Ah, yang benar saja pak?” tanya mereka lebih lanjut.
“Benar, jangan banyak omong segera menulis. Waktu kalian Cuma 15 menit saja”.
Dengan agak menggeruti, bahkan ada yang nggerundel mereka toh akhirnya menulis juga. Tapi ada juga yang masih bengong, apa yang akan ditulis.
“Ayo, segera ditulis, “perintah saya.
Setelah 15 menit kemudian.
“Sekarang kumpulkan ke saya”
“Wah, pak belum selesai nih?”
“Pokoknya kumpulkan saja, selesai dan tidak selesai”.
Akhirnya, tulisan dikumpulkan. Setelah saya baca memang terkesan lucu-lucu. Ada yang bercerita tentang mengaspal jalan yang dimulai dengan membersihkan jalan. Ada juga yang menceritakan mengaspal jalan tidaklah mudah. Ada lagi yang cerita justru kesan terhadap jalan yang aan diaspal. Setelah saya baca sekilas, saya bertanya?
“Sekarang saya akan bertanya, apa yang kalian pikirkan ketika saya menugaskan untuk membuat tulisan bagaimana cara mengaspal jalan?”
“Wah, tema itu terlalu dipaksakan, “ jawab seseorang.
“Saya tidak bisa menulis secara baik karena saya tidak pernah mengetahui bagaimana mengaspal jalan, “jawab yang lain.
“Bagaimana mungkin kita bisa mengaspal jalan? Wong kita bukan para buruh yang biasa mengaspal jalan itu, kok,”imbuh seseorang.
Setelah saya melihat bagaimana kesulitan mereka menulis dari apa yang saya tugaskan, kemudian saya menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis.
Seseorang tidak akan pernah bisa menulis kalo ia tidak punya gagasan-gagasan apa yang akan ditulis. Gagasan-gagasan inilah yang akan diolah dan dibuat sebuah tulisan. Jika tidak punya gagasan yang akan dituangkan, bagaimana seseorang akan bisa menulis? Dari situ saya memahami mengapa peserta pelatihan menulis itu mengalami kesulitan ketika saya suruh menulis bagaimana cara mengaspal jalan. Ini hampir sama dengan seseorang yang disuruh menulis tentang teknologi ruang angkasa? Apa yang akan ditulis? Dari mana informasi yang bisa dijadikan untuk menulis? Di sinilah diperlukan sumber-sumber gagasan.
Bagi peserta pelatihan, ia tidak akan pernah mengalami kesulitan manakala ia pernah punya pengalaman mengaspal jalan. Seseorang yang pernah punya pengalaman mengaspal jalan, ia mempunyai sumber gagasan yakni pengalaman. Seseorang, tentu akan mudah menulis jika ia menulis tentang pengalamannya, bukan?
Coba, Anda sekarang menulis tentang bagaimana cara mengaspal jalan dengan menulis pengalaman masa kecil. Lebih mudah mana? Saya yakin, Anda akan lebih mudah menulis pengalaman masa kecil itu daripada disuruh menulis bagaimana cara mengaspal jalan.
Barangkali Anda pernah membaca buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Katanya, ia tidak pernah membayangkan bisa menulis novel. Buku yang ditulisnya itu hanya untuk dihadiahkan kepada gurunya, yakni bu Muslimah. Tetapi, ia dengan gampangnya menulis karena yang ditulis itu hanya pengalaman-pengalamannya saat sekolah. Untungnya, saat ia sekolah mempunyai sejarah yang unik, susah, penuh harapan dan cita-cita, dikelilingi oleh ketidakadilan dan semangat yang menggebu-gebu dari gurunya. Ini tentu akan sama dengan pengalaman-pengalaman Anda di sekolah dasar. Hanya pengalaman Anda tidak setragis Andrea Hirata. Tragis, hampir putus asa yang menjadi sumber gagasannya untuk menulis.
Sumber gagasan yang lain adalah dengan membaca. Anda akan dengan mudah menulis bagaimana cara mengaspal jalan jika pernah membaca buku yang berkaitan dengannya. Anda yang dari jurusan ilmu komunikasi misalnya, akan dengan mudah menulis masalah komunikasi lisan karena pernah membaca buku tentang itu, bukan? Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah membaca buku komunikasi lisan? Jelas, ia akan mengalami kesulitan yang luar biasa.
Masalahnya, apa yang harus kita baca? Pengalaman saya mengatakan, membaca apa saja akan berguna. Cuma, kita sering punya penyakit. Membaca hanya yang bisa menguntungkan sesaat saja. Mahasiswa yang tergolong aktivis senang membaca buku-buku yang bisa dipaki untuk aktualisasi diri dalam diskusi. Ini tidak salah. Hanya, kita tidak boleh terkungkung dengan membaca dari satu permasalahan saja. Membacalah banyak hal. Calon penulis harus yakin, bahwa apa yang kita baca akan berguna di masa datang. Cepat atau lambat.
Suatu saat, saya mengajar mata kuliah Dasar-dasar Penulisan. Saya memerintahkan mahasiswa untuk membuat sebuah tulisan, setelah saya bagikan kertas.
“Coba, silakan Anda menulis apa yang bisa Anda amati atas kehidupan malam mahasiswa.”
“Itu gampang pak, daripada disuruh menulis tentang Gender,” kata seorang mahasiswa antusias.
Sebagai catatan, minggu sebelumnya saya menugaskan mereka untuk menulis masalah gender. Kesulitan luar biasa menghantui mahasiswa semester dua itu.
Setelah mereka menulis dengan batas waktu yang saya tentukan, ternyata mereka lebih mudah menuliskan tentang pengamatan kehidupan malam mahasiswa dari pada disuruh menulis masalah gender.
Tentu saja, macam-macam hasil yang dia bisa amati. Ada mahasiswa yang sering pulang malam, bahkan dinihari karena dia kerja di diskotik. Ada juga yang jarang pulang, karena menjadi “ayam kampus” dan diajak pergi jalan-jalan. Ada juga mahasiswa yanag sedang dibooking oleh dosennya sendiri. Ada yang berjam-jam nongkrong di warung kopi, diskusi, dan lain sebagainya.
Lepas dari apa hasil pengamatannya, yang jelas, pengamatan menjadi sumber gagasan untuk menulis. Maka, mengamati dengan seksama kejadian-kejadian di sekitar kita adalah hal yang dianjurkan bagi calon penulis. Akan lebih baik jika hasil pengamatan itu ditulis dalam buku harian atau diketik dalam komputer. Pengalaman, sumber gagasan.
Apakah Anda mengenal Raditya Dika? Penulis buku Kambing Jantan itu juga tak pernah membayangkan kalau catatan harian yang ditulisnya di blog bisa diterbitkan menjadi buku, bahkan sudah puluhan kali cetak ulang. Bahasanya memang kacau karena “catatan harian”. Barangkali kalau diteliti oleh ahli bahasa, ia tidak lulus mata pelajaran itu. Tapi, kita tetap salut, ia cerdas menulis pengamatan (termasuk pengalaman) sehari-harinya dalam blog, tanpa tahu tulisan-tulisannya akan diterbitkan menjadi buku atau tidak. Yang penting, dia tetap menulis. Mungkin hanya untuk menyalurkan uneg-uneg. Bahkan, bukunya Kambing Jantan itu diangkat menjadi sebuah film. Luar biasa bukan?
Nah, calon penulis perlu meniru apa yang dilakukan Raditya Dika tersebut. Maka, perkaya sumber-sumber gagasan Anda. Tak ada cara lain. Titik.
Readmore »»
Rabu, Januari 14, 2009
Pro Kontra Tayangan Infotainment: Menggugat Liputan Cover Both Sides
Penonton televisi Indonesia, akhir-akhir ini disuguhi berita “serial” tentang kasus Marcella Zalianty Vs Agung Setiawan. Marcella dituduh melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Marcella tidak sendiri. Ia juga menyeret Ananda Mikola (pembalap nasional). Berita tentang kasus itu semakin “panas” setelah banyak orang ikut berkomentar soal tersebut.
Kasus pun kian melebar. Kasus yang awalnya memberitakan penganiayaan seksual atas diri Agung dan menjadikan Marcella terdakwa kasus itu berubah drastis. Acara-acara infotainment yang awalnya menyelidiki kasus itu justru berbalik arah untuk mengupas dan menyudutkan Agus. Tak berhenti di situ saja, latar belakang hubungan Ananda Mikola dengan Mercella juga dikupas habis.
Yang lebih mengejutkan, Agus yang awalnya sebagai orang yang dianiaya, berubah menjadi orang pesakitan. Infotainment kemudian menginvestigasi latar balakang Agus sebagai orang yang pernah berbuat jahat dan punya kelainan seksual. Bahkan ada acara infotainment yang harus mendatangi rumah orang tua Agus di Bantul, Yogyakarta. Berita bahwa Agus juga pernah menghuni LP Wirogunan juga tak kalah dahsyatnya.
Berimbang Saja?
Mengapa acara infotainment yang awalnya mengupas tindak kekerasan Marcella, kemudian menjadikan Agung sebagai terduduh juga dalam kasus tersebut? Alasan klasik yang seringkali kita dengar adalah televisi ingin menyajikan laporan berimbang. Artinya, ia tidak ingin dituduh masyarakat sebagai pihak yang terlalu membela Agus dan menyudutkan Marcella. Alasan inilah yang kemudian dijadikan pembenar untuk melakukan investigasi dua pihak yang berbeda secara seimbang (cover both sides). Namun demikian, permasalahan cover both sides ternyata tidak berhenti ketika media massa telah melakukan laporan berimbang.
Setidak-tidaknya, beberapa problem baru yang muncul antara lain. Pertama, infotainment tidak sadar jika pemberitaannya justru memperlebar permasalahan dari konteks sebenarnya. Permasalahan Marcella dan Agung adalah soal pelecehan seksual dan tindak kekerasan. Di sini, Marcella dan Ananda sebagai tertuduh, sementara Agung sebagai korban. Sudah jelas persoalan itu sebenarnya, tinggal dicari bukti-bukti di lapangan.
Tetapi, persoalan semakin ruwet ketika infotainment mengupas latar belakang kedua orang itu (Marcella dan Agung), menyangkut kehidupan pribadinya. Baik menyangkut percintaan atau masalah seks dan lain-lainya. Masalah pelecehan seksual dan kekerasan yang menjadi fokus utamanya, akhirnya menjadi kabur. Pihak Marcella tentu akan membela habis-habisan terdakwa itu, bagaimanapun caranya.
Kedua, peliputan berita yang hanya mengandalkan cover both sides kadang juga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kasus Marcella di atas bisa dijadikan contoh. Pihak pengelola infotainment atau televisi yang menyiarkan acara itu bisa jadi sudah terhindar dengan mengatakan ia telah melakukan reportase berimbang. Misalnya, ia tidak hanya mengupas Marcella, tetapi juga Agung.
Peliputan yang berimbang hanya menekankan pada kuantitas saja, sementara kualitas dan orientasi permasalahan sebenarnya kurang ditekankan. Bagaimana mungkin infotainment sampai mengupas masalah pribadi kedua orang itu (Marcella dan Agung) berkaitan dengan masa lalunya? Jawaban yang membuat orang sering maklum karena infotainment memang “menjual” sensasi dan berorientasi pada kepentingan pasar saja. Infotainment sudah merasa bertanggung jawab ketika sudah menampilkan dua sisi yang berbeda, padahal tidak sesederhana itu.
Prinsip Keadilan
Bagaimana dengan prinsip keadilan? Di sinilah cover both sides sering menemukan batu sandungannya. Misalnya, terjadi konflik antara walikota dengan anggota dewan di daerah. Kalau peliputan hanya mengandalkan cover both sides, maka media massa sudah merasa cukup jika meliput dua sisi yang berbeda itu. Namun, tentu tidak adil jika walikota diwawancarai, sementara dari kalangan DPRD hanya anggota biasa, meskipun kedua belah pihak juga dikupas. Yang adil tentunya adalah pimpinan tertinggi kedua lembaga itu yang harus diwawancarai. Di sinilah peliputan yang berimbang perlu didukung oleh prinsip keadilan.
Dalam kasus Marcella, sangat terasa tiadanya prinsip keadilan yang dimaksud. Karena kasus itu menyangkut Mercella (artis terkenal), dan Agung (orang biasa), infotainment punya kecenderungan meliput mereka yang dekat dengan Marcella. Ini bisa dimaklumi karena orang yang dekat dengan Marcella mempunyai nilai berita tinggi. Orang dekat ini tentu akan membela Mercellla dalam kuantitas yang besar. Jadi, secara tidak langsung, infoteinment membela Marcella. Bisa jadi tiada kesengajaan, tetapi tanpa pertimbangan keadilan hal itu akan menjadikan infotainment sebagai tertuduh biang keladi permasalahan yang semakin memburuk.
Masalahnya, infotainment itu berita atau bukan? Jika berita, maka ia juga harus mematuhi aturan yang selama ini ada dalam proses peliputan dan pembuatan berita. Bahkan saat ini reportase juga sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa.
Barangkali kita perlu belajar dari C.P Scott (The Manchester Guardian) bahwa reportase yang berkembang saat ini adalah reportase faktual. Yakni laporan yang memisahkan antara fakta dan opini berkembang sebagai reportase interpretatif, mendalam, investigatif dan reportase yang komprehensif. Bukan sekadar fakta menurut kejadiannya dan fakta linear, tetapi fakta yang mencakup.
Infotainment seperti kasus Mercella, berada dalam ranah abu-abu. Acara itu penuh dengan opini yang menggiring penonton untuk menyetujui dan tidak menyetujui kasus yang disodorkan. Jika acara infotainment banyak mengupas seorang artis yang terkena masalah, sementara dia dan lingkingan di sekitarnya lebih mempunyai nilai berita, ada kesan membela sang artis. Maka, apa yang dikatakan C.P Scott jelas jauh dari kenyataan. Apalagi, diikuti penyajian fakta-fakta yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kasus yang sedang jadi perbincangan. Benar bahwa Marcella pernah punya masalah percintaan yang “buruk”, juga benar bahwa Agung punya sejarah yang tak kalah buruknya, tetapi tidak lantas dieksploitasi untuk menggirng penonton ke arah yang bukan substansi.
Jadi, memang meliput secara cover both sides dalam era jurnalisme infotainment tidak gampang. Infotainment adalah acara yang mendasarkan diri pada sensasional, kepentingan pasar, dan belum dilandasi dengan kecerdasan dalam peliputan berita. Maka, meliput secara cover both sides itu tidak gampang, rumit, pelik, dan penuh tanggung jawab.
Sumber: Harian Malang Post, 11 Januari 2009.
Readmore »»
Kasus pun kian melebar. Kasus yang awalnya memberitakan penganiayaan seksual atas diri Agung dan menjadikan Marcella terdakwa kasus itu berubah drastis. Acara-acara infotainment yang awalnya menyelidiki kasus itu justru berbalik arah untuk mengupas dan menyudutkan Agus. Tak berhenti di situ saja, latar belakang hubungan Ananda Mikola dengan Mercella juga dikupas habis.
Yang lebih mengejutkan, Agus yang awalnya sebagai orang yang dianiaya, berubah menjadi orang pesakitan. Infotainment kemudian menginvestigasi latar balakang Agus sebagai orang yang pernah berbuat jahat dan punya kelainan seksual. Bahkan ada acara infotainment yang harus mendatangi rumah orang tua Agus di Bantul, Yogyakarta. Berita bahwa Agus juga pernah menghuni LP Wirogunan juga tak kalah dahsyatnya.
Berimbang Saja?
Mengapa acara infotainment yang awalnya mengupas tindak kekerasan Marcella, kemudian menjadikan Agung sebagai terduduh juga dalam kasus tersebut? Alasan klasik yang seringkali kita dengar adalah televisi ingin menyajikan laporan berimbang. Artinya, ia tidak ingin dituduh masyarakat sebagai pihak yang terlalu membela Agus dan menyudutkan Marcella. Alasan inilah yang kemudian dijadikan pembenar untuk melakukan investigasi dua pihak yang berbeda secara seimbang (cover both sides). Namun demikian, permasalahan cover both sides ternyata tidak berhenti ketika media massa telah melakukan laporan berimbang.
Setidak-tidaknya, beberapa problem baru yang muncul antara lain. Pertama, infotainment tidak sadar jika pemberitaannya justru memperlebar permasalahan dari konteks sebenarnya. Permasalahan Marcella dan Agung adalah soal pelecehan seksual dan tindak kekerasan. Di sini, Marcella dan Ananda sebagai tertuduh, sementara Agung sebagai korban. Sudah jelas persoalan itu sebenarnya, tinggal dicari bukti-bukti di lapangan.
Tetapi, persoalan semakin ruwet ketika infotainment mengupas latar belakang kedua orang itu (Marcella dan Agung), menyangkut kehidupan pribadinya. Baik menyangkut percintaan atau masalah seks dan lain-lainya. Masalah pelecehan seksual dan kekerasan yang menjadi fokus utamanya, akhirnya menjadi kabur. Pihak Marcella tentu akan membela habis-habisan terdakwa itu, bagaimanapun caranya.
Kedua, peliputan berita yang hanya mengandalkan cover both sides kadang juga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kasus Marcella di atas bisa dijadikan contoh. Pihak pengelola infotainment atau televisi yang menyiarkan acara itu bisa jadi sudah terhindar dengan mengatakan ia telah melakukan reportase berimbang. Misalnya, ia tidak hanya mengupas Marcella, tetapi juga Agung.
Peliputan yang berimbang hanya menekankan pada kuantitas saja, sementara kualitas dan orientasi permasalahan sebenarnya kurang ditekankan. Bagaimana mungkin infotainment sampai mengupas masalah pribadi kedua orang itu (Marcella dan Agung) berkaitan dengan masa lalunya? Jawaban yang membuat orang sering maklum karena infotainment memang “menjual” sensasi dan berorientasi pada kepentingan pasar saja. Infotainment sudah merasa bertanggung jawab ketika sudah menampilkan dua sisi yang berbeda, padahal tidak sesederhana itu.
Prinsip Keadilan
Bagaimana dengan prinsip keadilan? Di sinilah cover both sides sering menemukan batu sandungannya. Misalnya, terjadi konflik antara walikota dengan anggota dewan di daerah. Kalau peliputan hanya mengandalkan cover both sides, maka media massa sudah merasa cukup jika meliput dua sisi yang berbeda itu. Namun, tentu tidak adil jika walikota diwawancarai, sementara dari kalangan DPRD hanya anggota biasa, meskipun kedua belah pihak juga dikupas. Yang adil tentunya adalah pimpinan tertinggi kedua lembaga itu yang harus diwawancarai. Di sinilah peliputan yang berimbang perlu didukung oleh prinsip keadilan.
Dalam kasus Marcella, sangat terasa tiadanya prinsip keadilan yang dimaksud. Karena kasus itu menyangkut Mercella (artis terkenal), dan Agung (orang biasa), infotainment punya kecenderungan meliput mereka yang dekat dengan Marcella. Ini bisa dimaklumi karena orang yang dekat dengan Marcella mempunyai nilai berita tinggi. Orang dekat ini tentu akan membela Mercellla dalam kuantitas yang besar. Jadi, secara tidak langsung, infoteinment membela Marcella. Bisa jadi tiada kesengajaan, tetapi tanpa pertimbangan keadilan hal itu akan menjadikan infotainment sebagai tertuduh biang keladi permasalahan yang semakin memburuk.
Masalahnya, infotainment itu berita atau bukan? Jika berita, maka ia juga harus mematuhi aturan yang selama ini ada dalam proses peliputan dan pembuatan berita. Bahkan saat ini reportase juga sudah mengalami perkembangan sedemikian rupa.
Barangkali kita perlu belajar dari C.P Scott (The Manchester Guardian) bahwa reportase yang berkembang saat ini adalah reportase faktual. Yakni laporan yang memisahkan antara fakta dan opini berkembang sebagai reportase interpretatif, mendalam, investigatif dan reportase yang komprehensif. Bukan sekadar fakta menurut kejadiannya dan fakta linear, tetapi fakta yang mencakup.
Infotainment seperti kasus Mercella, berada dalam ranah abu-abu. Acara itu penuh dengan opini yang menggiring penonton untuk menyetujui dan tidak menyetujui kasus yang disodorkan. Jika acara infotainment banyak mengupas seorang artis yang terkena masalah, sementara dia dan lingkingan di sekitarnya lebih mempunyai nilai berita, ada kesan membela sang artis. Maka, apa yang dikatakan C.P Scott jelas jauh dari kenyataan. Apalagi, diikuti penyajian fakta-fakta yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kasus yang sedang jadi perbincangan. Benar bahwa Marcella pernah punya masalah percintaan yang “buruk”, juga benar bahwa Agung punya sejarah yang tak kalah buruknya, tetapi tidak lantas dieksploitasi untuk menggirng penonton ke arah yang bukan substansi.
Jadi, memang meliput secara cover both sides dalam era jurnalisme infotainment tidak gampang. Infotainment adalah acara yang mendasarkan diri pada sensasional, kepentingan pasar, dan belum dilandasi dengan kecerdasan dalam peliputan berita. Maka, meliput secara cover both sides itu tidak gampang, rumit, pelik, dan penuh tanggung jawab.
Sumber: Harian Malang Post, 11 Januari 2009.
Readmore »»
Langganan:
Postingan (Atom)