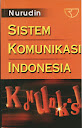(Tulisan ini salah satu bahasan dalam buku "Opini Publik Sebagai The Fifth Estate)
Kasus “Cicak vs Buaya” menjadi semakin ruwet. Keruwetan ini muncul setelah menyeret banyak pihak yang terkait. Kasus itu semakin mendapat perhatian masyarakat luas setelah dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kapolri beberapa waktu lalu.
Terungkap, Kapolri membela dan ingin mengembalikan kewibawaan institusi Polri, Susno Duadji (mantan Kabareskrim) merasa tidak terlibat dalam kasus itu, bahkan sampai bersumpah sekalipun. Sementara dalam rekaman yang diungkap di Mahkamah Konstitusi (MK), nama dia justru sering disebut. Pertanyaannya adalah apakah Anggodo sedang melakukan “dramatisasi” sebuah perkara? Sementara itu, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah juga mengatakan tidak pernah menerima suap. Lalu, siapa yang bersalah dan siapa yang benar?
Peran media massa
Berbagai rentetan peristiwa di atas kemudian diberitakan oleh media massa (cetak dan elektronik). Rentetan peristiwa itu kemudian diikuti oleh opini-opini yang dibangun di atas fakta-fakta yang berasal dari opini narasumber. Jadi, media massa memberitakan fakta-fakta yang berasal dari pendapat para narasumber tertentu atas fakta perseteruan antara “Cicak vs Buaya”.
Jika opini-opini itu diberitakan oleh media massa, pengaruhnya juga sampai ke pembaca, penonton atau pendengarnya – sebut saja audiens. Jika audiens tersebut terpengaruh oleh pemberitaan dari media massa itu, jadilah yang disebut dengan public opinion (opini publik).
Opini publik adalah opini yang berkembang karena pengaruh pemberitaan dari media massa, meskipun ada juga opini publik yang bisa dibangun bukan dari media massa. Masalahnya, media massa mempunyai kekuatan untuk memperkuat dan mempercepat tersebarnya sebuah opini.
Publik hanya mereaksi dari apa yang diakses audiens lewat media massa. Dalam posisi ini, opini bisa berkembang dengan baik atau tidak sangat tergantung dari pemberitaan apa yang disiarkan media massa itu.
Tak heran, jika opini publik bisa disebabkan oleh dua hal, direncanakan (planned opinion) dan tidak direncanakan (unplanned opinion). Opini publik yang direncanakan dikemukakan karena memang ada sebuah rencana tertentu yang disebarkan media massa agar menjadi opini publik. Ia mempunyai organisasi, kinerja dan target yang jelas. Misalnya, opini yang sengaja dibuat oleh elite politik tertentu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ide ini dikemukakan di media massa secara gencar dengan perencanaan matang.
Lain halnya dengan opini publik yang tidak direncanakan. Ia muncul dengan sendirinya tanpa rekayasa. Media hanya sekadar memuat sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian diperbincangkan di tengah masyarakat. Dalam posisi ini, media massa hanya mengagendakan sebuah peristiwa dan memberitakannya, hanya itu. Ia kemudian menjadi pembicaraan publik karena publik menganggap isu itu penting untuk diperbincangkan. Karena menjadi pembicaraan di masyarakat, media massa kemudian memberi penekanan tertentu atas sebuah isu. Akhirnya, ia menjadi opini publik juga.
Tahapan opini publik
Untuk menjadi opini publik, kemunculannya melalui berbagai proses yang tidak gampang dan singkat. Ferdinand Tonnies (Nurudin, 2001:56-57) dalam bukunya Die Offentlichen Meinung pernah mengungkapkan bahwa opini publik terbentuk melalui tiga tahapan; pertama, die luftartigen position. Pada tahap ini, opini publik masih semrawut seperti angin ribut. Masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengetahuan, kepentingan, pengalaman dan faktor lain untuk mendukung opini yang diciptakannya.
Kedua, die fleissigen position. Pada tahap ini, opini publik sudah menunjukkan ke arah pembicaraan lebih jelas dan bisa dianggap bahwa pendapat-pendapat tersebut mulai mengumpul ke arah tertentu secara jelas. Artinya, sudah mengarah, mana opini mayoritas yang akan mendominasi dan mana opini minoritas yang akan tenggelam.
Ketiga, die festigen position. Pada tahap ketiga ini, opini publik telah menunjukkan bahwa pembicaraan dan diskusi telah mantap dan suatu pendapat telah terbentuk dan siap untuk dinyatakan. Dengan kata lain, siap untuk diyakini kebenarannya setelah melalui perdebatan dan perbedaan pendapat yang tajam sebelumnya.
Menunggu ending
Perseteruan antara KPK dengan Polri jelas akan berdampak luar biasa bagi masyarakat. Tidak saja karena melibatkan dua institusi yang seharusnya memberikan contoh penegakan hukum, tetapi sudah mengarah pada gengsi antar lembaga. Polisi gengsi dan harus membela diri karena (merasa) dipojokkan, sementara itu KPK bisa menjadi besar kepala karena merasa didukung semua elemen masyarakat (demonstrasi, Facebook dan dukungan lain).
Namun, perseteruan ini menyisakan persoalan karena semakin membuat ruwet opini yang berkembang di masyarakat. Pihak kepolisian membela diri, sementara KPK juga tidak jauh berbeda. Masyarakat yang tidak kritis tentu akan menelan mentah-mentah berita-berita yang berasal dari media massa. Jika begini, media massa harus punya agenda mendasar untuk memberikan perspektif cerdas berkaitan dengan persoalan itu. Misalnya, media massa tentu tidak pada tempatnya ikut-ikutan membela kepolisian gara-gara kebanyakan anggota Komisi III beberapa waktu lalu cenderung membela Polri. Perhelatan dengar pendapat bak sebuah dagelan politik.
Semakin ruwet persoalan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pembentukan opini publik, bisa masuk dalam tahapan pertama yakni opini publik masih semrawut sebab masing-masing pihak yang bertikai saling merasa benar sendiri dan cenderung menyalahkan pihak lain. Yang jelas, kepentingan masing-masing pihak sangat transparan.
Soal bagaimana ending (akhir) “drama politik” terbesar tahun ini, biarlah isu itu terus bergulir. Biarlah nanti opini publik melalui tahapan selanjutnya. Biarlah media massa punya agenda tersendiri tanpa campur tangan kepentingan pihak-pihak lain. Dan akhirnya, biarlah masyarakat menilai mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Opini publik seperti itu akan memberikan pelajaran berharga, betapa setiap kejahatan saat ini akan menjadi sorotan masyarakat karena semua kejadian bisa diekspos media massa.
Barangkali, dukungan masyarakat atas KPK dan cenderung memojokkan Polri menjadi puncak gunung es kekecewaan perilaku masyarakat atas anggota Polri selama ini – lepas dari siapa nantinya yang bersalah. Dari sini, semua pihak tentu harus berpikir jernih dan cerdas. Mereka boleh melakukan apa saja, tetapi opini publik masyarakat tidak bisa direkayasa, apalagi mereka dibohongi. Biarlah opini publik menjadi hukuman sosial (social punishment) atas keserakahan mereka. - Oleh : Nurudin Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), penulis buku Jurnalisme Masa Kini
(artikel ini pengembangan dari tulisan saya di Solo Pos, 11 November 2009)
Readmore »»