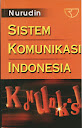Sudah banyak diskusi tentang pentingnya pendidikan multikultur di Indonesia. Tetapi dari diskusi yang terungkap jarang yang melihat betapa besarnya peran pers (cetak dan elektronik) dalam menciptakan terwujudnya pendidikan multikultur tersebut.
Mengapa harus pers? Harold D Laswell pernah sampai pada kesimpulan karena pers punya fungsi transmission of the social heritage from one generation to the next. Fungsi ini diimplementasikan dalam fungsi pendidikan yang dimunculkan oleh pers. Artinya, jika pers mentransmisikan nilai-nilai persatuan dan bukan konflik, maka pers sedang menjalankan fungsi menekankan pentingnya persatuan dan jangan melulu konflik. Di sinilah pentingnya pers memegang peranan penting bagi keberhasilan pendidikan multikultur.
Apa yang disajikan pers, menjadi sebuah alat ampuh untuk melakukan pendidikan multikultur. Labelling yang dilakukan pers bisa jadi akan menjadi sumbu ledak bagi usaha munculnya konflik multikultur.
Misalnya, sebuah koran yang ada di Kalimantan pernah memberikan sebutan yang bisa membakar semangat untuk terus berkonflik. Sebut saja kata-kata “menjajah” dan “sarang kaum begal bergundal etnis Madura” (Eriyanto dkk., 2004). Munculnya, atau tepatnya keberpihakan kepentingan pers, menjadi cermin gagalnya pendidikan multikultur yang dilakukan pers itu sendiri.
Meskipun dalam bangku sekolah telah diajarkan pendidikan multikultur, memandang sebelah mata peran media yang sebenarnya mendukung gerakan pendidikan multikultur adalah tindakan yang tak bijaksana. Pendidikan di bangku sekolah seringkali justru sekadar menjadi hiasan formalitas anak didik. Sementara dalam kehidupan sehari-harinya, sikap dan perilakunya tak lepas dari pengaruh pers. Alasannya, masyarakat modern saat ini menjadikan pers sebagai alat utama sumber informasi.
Apa yang Harus Dilakukan
Oleh kerenanya, akan pentingnya pers itu sudah sepantasnya ia harus ditempatkan pada posisi paling depan dalam usaha membangun pendidikan berbasis multikultur. Lalu apa yang harus dilakukan pers, terutama di daerah yang rawan konflik, bagi terwujudnya pendidikan multikultur?
Pertama, pers mau tidak mau harus berdiri diluar dari mereka yang berkonflik. Masalahnya, seringkali pers terlibat atau sengaja melibatkan dirinya pada kelompok yang berkonflik. Tentu saja ini akan mengurangi objektivitas pemberitaannya. Bahkan seringkali pers menikmati keuntungan dibalik keterlibatannya. Jika media masih memihak seperti itu, apapun alasannya usaha untuk memperkuat basis pendidikan multikultur masih gagal. Itulah kenapa pendidikan multikultur tanpa memperhatikan peran pers menjadi pekerjaan yang sangat berat.
Kedua, ketidaklibatan pers dalam konflik akan memberikan otonomi pers untuk memilih dan memilah kalimat, kata-kata secara lebih jernih sesuai untuk kepentingan semua pihak. Kata-kata “menjajah”, “begal begundal” (untuk menyebut contoh) tidak akan muncul manakala pers tak melibatkan diri dalam konflik tersebut. Itulah sebenarnya, mengelola pers yang diserahkan pada mereka yang tak punya sense of news hanya akan menjadikan pers itu sebagai alat untuk mencapai keuntungan dan kepentingan sepihak.
Tidak Mudah
Tentu saja, melibatkan pers dalam membangun pendidikan multikultur tidaklah mudah. Dibutuhkan kemauan pers untuk secara aktif memerankan diri di posisi depan dalam membangun pendidikan tersebut. Sebab, bisa jadi harapan, dan usulan masyarakat agar pers berperan dalam membangun pendidikan berbasis multikultur tidak surut. Tetapi, manakala pers tidak punya kemauan untuk itu semua akan sia-sia.
Pers yang memposisikan diri sebagai pendorong pendidikan multikultur tidak perlu takut dianggap sebagai “pers banci”. Misalnya, dengan kesadaran penuh melakukan peliputan cover both sides (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang) atau bahkan all sides. Teknik liputan ini, bagi sementara orang dianggap banci karena tidak jelas pemihakannya. Pers dituduh hanya mendahulukan safety first dan mau gampangnya saja. Tetapi justru pers seperti itu yang secara tidak langsung sedang memerankan jurnalisme multikultur. Artinya, ia berusaha menjadi watcher (pengamat) dan tidak melibatkan diri pada kelompok yang sedang bertikai. Pers tugasnya adalah melihat, memperkaya fakta dan data kemudian melaporkannya saja. Interpretasi diserahkan pada masyarakat.
Masih jauh untuk mencapai tujuan pers berperan sebagai pelopor pendidikan multikultur. Tetapi, usaha ke arah itu tentu harus didorong dan dipupuk. Maka, berikan informasi yang benar dan berimbang, pers akan melaporkan apa adanya. Memberikan laporan yang benar dan berimbang tak lain mendorong pers memerankan diri sebagai pendorong gerakan pendidikan multikultur.
Readmore »»
Menghentikan Teror TV pada Anak
Orang boleh saja mengatakan bahwa Anda cukup mematikan layar kaca,
tetapi tidak ada cara yang mudah untuk melakukannya”
(Teresa Orange dan Louise O’Flynn).
Minggu lalu, saya melihat running text di Metro TV yang menginformasikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana akan menerapkan larangan menoton televisi pada pukul 18.30-20.30 WIB. Ini dilakukan karena pada jam tersebut anak-anak sedang dan seharusnya belajar, bukan menonton televisi.
Pemerintah daerah Yogyakarta pada tahun 90-an juga pernah menggalakkan program itu dengan nama Jam Belajar Masyarakat (JBM) pada pukul 18.00-21.00 WIB. Bahkan himbauan itu disosialisasikan dengan ditulis di berbagai tempat. Setelah JBM diterapkan, ada penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang dosen IKIP Yogyakarta (sekarang UNY). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa JBM ternyata tidak efektif. Bahkan JBM berubah menjadi Jam Belajar Menonton Televisi (JBMT). Artinya, kebanyakan masyarakat justru menonton televisi jada jam itu, meskipun ada larangan (Nurudin, 1997:63).
Niat untuk memberikan peringatan masyarakat seperti yang dilakukan di kota Solo dan Yogyakarta tersebut memang baik. Tetapi, himbauan untuk mematikan televisi -- yang sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat -- juga tidaklah gampang dilaksanakan. Sebab ada banyak variabel yang ikut memengaruhinya.
Sebenarnya, orang tua juga tidak kalah cerewetnya untuk melarang anak-anaknya menonton televisi. Alasannya, televisi kita saat ini disesaki dengan tayangan-tayangan sinetron dan hiburan lain yang tidak mencerdaskan. Anehnya, tema tayangan seperti sinetron hampir seragam; kalau tidak urusan cinta, atau konflik orang tua dengan anak, ya persoalan hamil di luar nikah. Yang berbahaya, seolah-olah tayangan televisi itu dianggap masyarakat sebagai kejadian yang sebenarnya.
Diperlukan Diet Media
Anak-anak memang sangat rentan terhadap pengaruh media. Namun, tidak semua anak-anak bisa terpengaruh. Menurut Teresa Orange dan Louise O’Flynn dalam bukunya The Media Diet for Kids (2007), ditemukan bahwa ada beberapa tipe anak yang gampang terpengaruh media. Misalnya, tipe anak yang suka bersolek atau memperhatikan penampilan, anak yang sedang bingung, anak yang tak punya teman untuk bermain atau merasa minder. Semua jenis tipe anak tersebut sangat mudah terpengaruh media, terutama televisi.
Bahkan orang tua juga berperan serta membuka peluang anak terpengaruh televisi. Orang tua yang punya waktu sedikit untuk anak-anaknya, anak yang sedang mengalami periode tak tenang (misalnya teror, perceraian dan kematian orang tua), anak yang biasa terkurung dalam rumah, anak yang sering menghabiskan waktunya sendirian di rumah, orang tua yang kecanduan media, dan anak yang terjepit diantara orang tua yang berpisah berpotensi besar terpengaruh. Dampaknya, anak-anak seperti itu akan punya peluang untuk melampiaskan diri mengonsumsi media hiburan terlalu besar.
Jika kemunculan dampak negatif tayangan televisi itu dibebankan pada orang tua ada beberapa cara yang harus dilakukan mereka. Orange dan O’Flynn (2007) memberikan kiat bahwa tak ada cara ampuh selain orang tua harus selalu mengontrol konsumsi media anak alias melakukan diet ketat media pada anak-anak.
Tak terkecuali, jangan menaruh televisi di kamar anak yang belum berusia 12 tahun. Yang lainnya, jangan biasakan waktu makan dengan menonton televisi, dan jangan biasakan anak menonton televisi sebelum dan sesudah tidur. Dan yang paling penting membuat jadwal dimana keluarga sepakat untuk tidak menonton televisi.
Bagaimana dengan Anjuran itu?
Dengan demikian, anjuran agar masyarakat mematikan televisi pada pukul 18.30-20.30 WIB tidak saja tak efektif tetapi juga akan sulit dilaksanakan. Ada beberapa alasan, pertama, ketergantungan masyarakat pada televisi selama ini sangatlah tinggi. Ini sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Mayoritas pecandu sinetron kita umumnya adalah mereka yang tingkat intelektualnya tidak begitu tinggi. Alasannya, menonton acara-acara seperti itu tidak membutuhkan perangkat kecerdasan tertentu. Asal secara inderawi sempurna. Televisi juga biasanya ditonton hanya untuk hiburan semata. Itu pulalah kenapa acara-acara sinetron dan bentuk hiburan lain ditayangkan pada jam prime time.
Kedua, terkait dengan kebaradaan anak-anak, bisa jadi anak-anak menurut saja keinginan orang tua untuk tidak menonton televisi. Ini disebabkan karena mereka umumnya takut. Coba seandainya anak-anak tidak begitu takut sama mereka atau orang tua tidak ada di rumah, tak ada yang bisa menjamin mereka tidak menonton televisi.
Ketiga, anak-anak tergantung televisi karena orang tua juga pencandu televisi. Bagaimana mungkin orang tua akan melarang anak-anaknya agar tak menonton “Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi?)” di SCTV, “Candy” di RCTI, yang disiarkan setiap jam prime time kalau ibunya juga kecanduan pada acara tersebut? Tentu, anak tidak mudah untuk dilarang menonton televisi, bukan?
Yang Perlu Dilakukan
Jika pemerintah kota Solo serius agar anak-anak di kota ini tidak terpengaruh tayangan negatif televisi ada beberapa pilihan yang bisa dijadikan prioritas. Pertama, melakukan kampanye anti televisi. Karena televisi punya dampak negatif yang besar, perlu dilakukan kampanye anti televisi. Langkah ini tak bermaksud melarang masyarakat tak boleh menonton televisi, tetapi bertujuan memberikan penyadaran mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan ceramah, simulasi, atau bentuk-bentuk kampanye yang lain. Tentu saja, jika memang pemeritah kota Solo serius memikirkan dampak negatif tayangan televisi pada anak-anak.
Kedua, investasikan dana untuk media literacy. Ini kegiatan yang tak kalah pentingnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang melek media. Bahwa masyarakat bisa menimbang, memilih acara atau media apa yang berguna bagi dirinya menjadi target penting.
Pasang iklan, spanduk, himbauan, membina lembaga-lembaga non pemerintah untuk teribat aktif sangat baik dilakukan. Tentu saja, ini tidak akan lepas dari dana. Pemerintah kota jelas harus punya keberanian menginvestasikan dananya untuk kegiatan tersebut. Lembaga independen seperti LSM misalnya, perlu didanai untuk melakukan riset yang bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan apa yang baik untuk langkah antisipasi ke depan. Bukankah dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah ini sudah meningkat tajam?
Ketiga, memberikan social punishment pada televisi. Artinya, masyarakat harus terus dihimbau untuk memboikot televisi. Tentu saja, kegiatan ini tidak mudah dilakukan. Hanya mereka yang benar-benar sadar akan pengaruh negatif televisi pada anak-anaklah yang berani dan mampu melakukannya. Masalahnya, tidak semua masyarakat mau melakukan boikot pada televisi. Artinya juga, jangan ngomong kalau tidak suka sinetron, tetapi diam-diam menontonya.
Dari kegiatan ini televisi telah terkena hukuman sosial masyarakat. Pemkot jelas punya kepentingan atas hal ini. Program kebijakan terhadap dampak negatif televisi pada anak-anak juga harus mengarah ke situ. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mengajak anggota DPRD untuk ikut ambil bagian dalam program tersebut. Bukankah mereka wakil rakyat yang tugasnya melindungi masyarakat (termasuk dampak negatif tayangan televisi)? Inilah beberapa catatan yang layak direnungkan. Yang jelas, jangan sampai ada anggapan masyarakat, bahwa pelarangan itu dilakukan karena Pemkot punya kepentingan teselubung dibaliknya. Readmore »»
tetapi tidak ada cara yang mudah untuk melakukannya”
(Teresa Orange dan Louise O’Flynn).
Minggu lalu, saya melihat running text di Metro TV yang menginformasikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana akan menerapkan larangan menoton televisi pada pukul 18.30-20.30 WIB. Ini dilakukan karena pada jam tersebut anak-anak sedang dan seharusnya belajar, bukan menonton televisi.
Pemerintah daerah Yogyakarta pada tahun 90-an juga pernah menggalakkan program itu dengan nama Jam Belajar Masyarakat (JBM) pada pukul 18.00-21.00 WIB. Bahkan himbauan itu disosialisasikan dengan ditulis di berbagai tempat. Setelah JBM diterapkan, ada penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang dosen IKIP Yogyakarta (sekarang UNY). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa JBM ternyata tidak efektif. Bahkan JBM berubah menjadi Jam Belajar Menonton Televisi (JBMT). Artinya, kebanyakan masyarakat justru menonton televisi jada jam itu, meskipun ada larangan (Nurudin, 1997:63).
Niat untuk memberikan peringatan masyarakat seperti yang dilakukan di kota Solo dan Yogyakarta tersebut memang baik. Tetapi, himbauan untuk mematikan televisi -- yang sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat -- juga tidaklah gampang dilaksanakan. Sebab ada banyak variabel yang ikut memengaruhinya.
Sebenarnya, orang tua juga tidak kalah cerewetnya untuk melarang anak-anaknya menonton televisi. Alasannya, televisi kita saat ini disesaki dengan tayangan-tayangan sinetron dan hiburan lain yang tidak mencerdaskan. Anehnya, tema tayangan seperti sinetron hampir seragam; kalau tidak urusan cinta, atau konflik orang tua dengan anak, ya persoalan hamil di luar nikah. Yang berbahaya, seolah-olah tayangan televisi itu dianggap masyarakat sebagai kejadian yang sebenarnya.
Diperlukan Diet Media
Anak-anak memang sangat rentan terhadap pengaruh media. Namun, tidak semua anak-anak bisa terpengaruh. Menurut Teresa Orange dan Louise O’Flynn dalam bukunya The Media Diet for Kids (2007), ditemukan bahwa ada beberapa tipe anak yang gampang terpengaruh media. Misalnya, tipe anak yang suka bersolek atau memperhatikan penampilan, anak yang sedang bingung, anak yang tak punya teman untuk bermain atau merasa minder. Semua jenis tipe anak tersebut sangat mudah terpengaruh media, terutama televisi.
Bahkan orang tua juga berperan serta membuka peluang anak terpengaruh televisi. Orang tua yang punya waktu sedikit untuk anak-anaknya, anak yang sedang mengalami periode tak tenang (misalnya teror, perceraian dan kematian orang tua), anak yang biasa terkurung dalam rumah, anak yang sering menghabiskan waktunya sendirian di rumah, orang tua yang kecanduan media, dan anak yang terjepit diantara orang tua yang berpisah berpotensi besar terpengaruh. Dampaknya, anak-anak seperti itu akan punya peluang untuk melampiaskan diri mengonsumsi media hiburan terlalu besar.
Jika kemunculan dampak negatif tayangan televisi itu dibebankan pada orang tua ada beberapa cara yang harus dilakukan mereka. Orange dan O’Flynn (2007) memberikan kiat bahwa tak ada cara ampuh selain orang tua harus selalu mengontrol konsumsi media anak alias melakukan diet ketat media pada anak-anak.
Tak terkecuali, jangan menaruh televisi di kamar anak yang belum berusia 12 tahun. Yang lainnya, jangan biasakan waktu makan dengan menonton televisi, dan jangan biasakan anak menonton televisi sebelum dan sesudah tidur. Dan yang paling penting membuat jadwal dimana keluarga sepakat untuk tidak menonton televisi.
Bagaimana dengan Anjuran itu?
Dengan demikian, anjuran agar masyarakat mematikan televisi pada pukul 18.30-20.30 WIB tidak saja tak efektif tetapi juga akan sulit dilaksanakan. Ada beberapa alasan, pertama, ketergantungan masyarakat pada televisi selama ini sangatlah tinggi. Ini sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Mayoritas pecandu sinetron kita umumnya adalah mereka yang tingkat intelektualnya tidak begitu tinggi. Alasannya, menonton acara-acara seperti itu tidak membutuhkan perangkat kecerdasan tertentu. Asal secara inderawi sempurna. Televisi juga biasanya ditonton hanya untuk hiburan semata. Itu pulalah kenapa acara-acara sinetron dan bentuk hiburan lain ditayangkan pada jam prime time.
Kedua, terkait dengan kebaradaan anak-anak, bisa jadi anak-anak menurut saja keinginan orang tua untuk tidak menonton televisi. Ini disebabkan karena mereka umumnya takut. Coba seandainya anak-anak tidak begitu takut sama mereka atau orang tua tidak ada di rumah, tak ada yang bisa menjamin mereka tidak menonton televisi.
Ketiga, anak-anak tergantung televisi karena orang tua juga pencandu televisi. Bagaimana mungkin orang tua akan melarang anak-anaknya agar tak menonton “Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi?)” di SCTV, “Candy” di RCTI, yang disiarkan setiap jam prime time kalau ibunya juga kecanduan pada acara tersebut? Tentu, anak tidak mudah untuk dilarang menonton televisi, bukan?
Yang Perlu Dilakukan
Jika pemerintah kota Solo serius agar anak-anak di kota ini tidak terpengaruh tayangan negatif televisi ada beberapa pilihan yang bisa dijadikan prioritas. Pertama, melakukan kampanye anti televisi. Karena televisi punya dampak negatif yang besar, perlu dilakukan kampanye anti televisi. Langkah ini tak bermaksud melarang masyarakat tak boleh menonton televisi, tetapi bertujuan memberikan penyadaran mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan ceramah, simulasi, atau bentuk-bentuk kampanye yang lain. Tentu saja, jika memang pemeritah kota Solo serius memikirkan dampak negatif tayangan televisi pada anak-anak.
Kedua, investasikan dana untuk media literacy. Ini kegiatan yang tak kalah pentingnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang melek media. Bahwa masyarakat bisa menimbang, memilih acara atau media apa yang berguna bagi dirinya menjadi target penting.
Pasang iklan, spanduk, himbauan, membina lembaga-lembaga non pemerintah untuk teribat aktif sangat baik dilakukan. Tentu saja, ini tidak akan lepas dari dana. Pemerintah kota jelas harus punya keberanian menginvestasikan dananya untuk kegiatan tersebut. Lembaga independen seperti LSM misalnya, perlu didanai untuk melakukan riset yang bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan apa yang baik untuk langkah antisipasi ke depan. Bukankah dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah ini sudah meningkat tajam?
Ketiga, memberikan social punishment pada televisi. Artinya, masyarakat harus terus dihimbau untuk memboikot televisi. Tentu saja, kegiatan ini tidak mudah dilakukan. Hanya mereka yang benar-benar sadar akan pengaruh negatif televisi pada anak-anaklah yang berani dan mampu melakukannya. Masalahnya, tidak semua masyarakat mau melakukan boikot pada televisi. Artinya juga, jangan ngomong kalau tidak suka sinetron, tetapi diam-diam menontonya.
Dari kegiatan ini televisi telah terkena hukuman sosial masyarakat. Pemkot jelas punya kepentingan atas hal ini. Program kebijakan terhadap dampak negatif televisi pada anak-anak juga harus mengarah ke situ. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mengajak anggota DPRD untuk ikut ambil bagian dalam program tersebut. Bukankah mereka wakil rakyat yang tugasnya melindungi masyarakat (termasuk dampak negatif tayangan televisi)? Inilah beberapa catatan yang layak direnungkan. Yang jelas, jangan sampai ada anggapan masyarakat, bahwa pelarangan itu dilakukan karena Pemkot punya kepentingan teselubung dibaliknya. Readmore »»
Media Massa, Penentu Suara dalam Pilkada
Karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara langsung, calon kepala daerah tidak akan bisa lepas dari strategi Public Relations (PR) modern. Ini tak lain karena kita sudah hidup dalam dunia media massa yang kian canggih. Bahkan dalam bukunya The Fall of Advertising and the Rise of PR, Al Ries & Laura Ries (2003) pernah mengatakan, saat ini era periklanan sudah mati, yang muncul adalah era PR.
Calon kepala daerah ibarat sebuah barang dan merek. Kita tidak akan bisa meluncurkan sebuah merek hanya dengan iklan saja. Iklan punya kredibilitas rendah bahkan dianggap membohongi, sementara PR punya persepsi positif.
Contoh dalam kasus pemasaran misalnya begini. Manakah diantara merek dibawah ini yang sering Anda dengar? Cardinal Halth, Delphi Automotive, Ingram Micro, Lehman Brother Holdings, McKesson HBOC, Liant Energy Southern , Tosco, TIA CREF, Utilicorp United atau Microsoft?
Tidak perlu diragukan lagi, bahwa nama Microsoft lebih akrab di telinga kita. Padahal sepuluh perusahaan selain Microsoft di atas lebih besar. Tetapi, kesepuluh perusahaan tersebut tidak satupun yang membangun merek sebanding dengan Microsoft. Padahal, TIA-CREF (misalnya) beberapa tahun lalu pernah mempunyai pemasukan sebesar $38 milyar, sedangkan Microsoft hanya $23 milyar. Tetapi Microsoft adalah sebuah merek.
Media Relations
Itu pulalah kenapa calon kepala daerah tidak hanya bisa mengandalkan iklan sebagai salah satu cara untuk mempopulerkan dirinya di tengah masyarakat. Saat ini masyarakat juga semakin rasional sehingga hubungan emosional dan psikologis bukan satu-satunya cara jitu untuk meraih simpati masyarakat. Misalnya, mentang-mentang seorang kandidat adalah pemuka keagamaan otomatis akan memudahkan dirinya menjadi kepala daerah. Itu belum merupakan garansi.
Satu strategi PR yang saat ini populer adalah media relations (hubungan media). Dalam komunikasi pemasaran, cara ini sedang digalakkan dan menjadi program cerdas perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan kecil biasanya hanya mengandalkan iklan dengan isi yang persuasif tetapi penuh dengan tipu muslihat. Yang dijadikan orientasi hanya barangnya terkenal dan laku dijual. Mereka umumnya tidak mempertahankan loyalitas konsumen dan hubungan personal.
Calon kepala daerah ibarat sebuah merek yang perlu dijajakan ke masyarakat. Oleh karena itu, karena ia sebuah produk baru ia perlu dikenalkan ke masyarakat, diungkapkan kelebihan yang dimiliki. Tentunya, “perusahaan” yang mensponsorinya tidak hanya mengenalkan “merek” itu tanpa mengetahui atau menggaransi bahwa “barangnya” memang berkualitas.
Cara modern yang sedang menjadi program perusahaan adalah media relations di atas. Calon kepala daerah mau tidak mau harus melakukan strategi PR seperti halnya perusahaan itu.
Mengapa? Saat ini kita hidup dengan media massa (cetak dan elektronik). Apa yang kita pikir, kita perbuat, kita beli, kita sosialisasikan, kita ungkapkan tak lepas dari peran media massa itu. Bahkan bisa dikatakan media telah membentuk hidup kita sehari-hari. Jika kita mau jujur apa yang kita beli, kita pakai, kita kemukakan lebih banyak berdasar dari media massa. Ini realitas dari perkembangan masyarakat modern kita.
Akan arti pentingnya media massa Marshall McLuhan dalam buknya terkenal Understanding Media, The Extension of Man (1999) pernah mengatakan bahwa media adalah the extension of man (media adalah ekstensi/perluasan) manusia. Artinya, apa yang dipikirkan, diinginkan manusia bisa diperluas perwujudannya melalui media massa. Bahkan media massa berbuat lebih dari apa yang bisa dilakukan manusia.
Jika manusia hanya bisa berpidato dihadapan ribuan orang, media massa melakukannya ke jutaan orang. Akan berbeda dampaknya seandainya apa yang dipidatokan itu kemudian disiarkan media massa, meskipun hanya dihadapan puluhan orang saja. Sama artinya, buat apa demonstrasi besar-besaran tetapi media massa tidak menyiarkannya/memberitakannya? Lebih berdampak hebat jika demonstrasi kecil-kecilan tetapi bisa disiarkan media massa.
Begitu hebatnya media massa sampai Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, “Jika media dibiarkan saja, saya tidak akan bisa berkuasa lebih dari tiga bulan”. Atau simak pendapat bapak kemerdekaan Amerika, Thomas Jefferson, “Seandainya saya harus memilih antara kehidupan pemerintahan tanpa surat kabar dengan adanya surat kabar tanpa pemerintahan, saya -- tidak ragu-ragu lagi -- akan memilih yang terakhir; ada surat kabar tanpa adanya pemerintah". Pernyataan Bonaparte atau Jefferson itu tentu bukan bualan seorang anak kecil di siang bolong semata, tetapi dipikir secara dalam karena hebatnya pengaruh media massa bagi masyarakat.
Bagaimana Dengan Kandidat?
Calon kepala daerah bisa juga melakukan strategi media relations. Kita bisa mengambil contoh kasus kesuksesan presiden SBY dalam pemilihan presiden tahun lalu. Ia berhasil menuduki RI-1 tak lain karena kemampuannya membangun citra di media massa.
Untuk mewujudkan itu semua, para calon kepala daerah itu bisa melakukan kegiatan sebagai berikut; pertama, para calon harus menjalin hubungan dekat dengan media massa. Ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke dapur redaksi media yang bersangkutan. Media, karena dikunjungi calon kepala daerah, ada kemungkinan besar untuk memberitakannya. Ini pulalah yang dahulu pernah dilakukan SBY dan Amien Rais untuk menyaingi kepopuleran Megawati karena kedudukannya sebagai presiden sudah menarik perhatian media massa.
Kedua, undanglah media massa dimana calon itu melakukan kegiatan politik seperti kampanye, pidato politik, kebijakan yang akan diputuskan. Bisa jadi media tanpa diundangpun ingin meliputnya, tetapi mengundang mereka bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua calon.
Ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan kandidat bisa diketahui masyarakat. Paling tidak, masyarakat tahu bahwa “seseorang” itu calon kepala daerah.
Ketiga, sering-seringlah membuat press release (siaran pers). Entah memang ada kebijakan atau keinginan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau hal lain. Tetapi yang jelas, calon kepala daerah tidak boleh “menyakiti” pers. Atau membuat pernyataan yang membuat jengkel wartawan. Sebab, begitu sang kandidat membuat “kesalahan” seperti itu Anda mungkin tetap muncul di media massa tetapi dengan berita yang justru merugikan Anda sendiri. Termasuk di sini, menghindari untuk mengatakan “no comment”. Pernyataan seperti itu jelas tidak disukai oleh wartawan. Anda juga akan dicitrakan sebagai orang yang tertutup.
Tetapi ada satu hal lain yang harus dilakukan jika ia terpilih menjadi kepala daerah. Tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan. Umumnya, para politisi kita pada awalnya berhubungan baik dengan wartawan, tetapi ketika sudah “mapan” ia lupa bahkan menghindar dari wartawan. Biasanya, politisi itu takut karena “dosanya” diketahui umum.
Maka, mengaja hubungan baik dengan media massa tidak saja akan memuluskan langkah sang calon menjadi kepala daerah tetapi juga akan menentukan “hidup matinya” pemerintahan daerah yang dipimpinnya nanti. Sudah saatnya, menempatkan media massa di depan dan bukan dipolitisir untuk tujuan yang mementingkan kepentingannya sendiri.
Media massa punya mata dan telinga. Sang kandidat akan diberitakan baik manakala ia baik, tetapi akan diberitakan jelek jika sebaliknya. Jadi, saat ini hidup matinya calon kepala daerah sangat mungkin ditentukan oleh media massa. Readmore »»
Calon kepala daerah ibarat sebuah barang dan merek. Kita tidak akan bisa meluncurkan sebuah merek hanya dengan iklan saja. Iklan punya kredibilitas rendah bahkan dianggap membohongi, sementara PR punya persepsi positif.
Contoh dalam kasus pemasaran misalnya begini. Manakah diantara merek dibawah ini yang sering Anda dengar? Cardinal Halth, Delphi Automotive, Ingram Micro, Lehman Brother Holdings, McKesson HBOC, Liant Energy Southern , Tosco, TIA CREF, Utilicorp United atau Microsoft?
Tidak perlu diragukan lagi, bahwa nama Microsoft lebih akrab di telinga kita. Padahal sepuluh perusahaan selain Microsoft di atas lebih besar. Tetapi, kesepuluh perusahaan tersebut tidak satupun yang membangun merek sebanding dengan Microsoft. Padahal, TIA-CREF (misalnya) beberapa tahun lalu pernah mempunyai pemasukan sebesar $38 milyar, sedangkan Microsoft hanya $23 milyar. Tetapi Microsoft adalah sebuah merek.
Media Relations
Itu pulalah kenapa calon kepala daerah tidak hanya bisa mengandalkan iklan sebagai salah satu cara untuk mempopulerkan dirinya di tengah masyarakat. Saat ini masyarakat juga semakin rasional sehingga hubungan emosional dan psikologis bukan satu-satunya cara jitu untuk meraih simpati masyarakat. Misalnya, mentang-mentang seorang kandidat adalah pemuka keagamaan otomatis akan memudahkan dirinya menjadi kepala daerah. Itu belum merupakan garansi.
Satu strategi PR yang saat ini populer adalah media relations (hubungan media). Dalam komunikasi pemasaran, cara ini sedang digalakkan dan menjadi program cerdas perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan kecil biasanya hanya mengandalkan iklan dengan isi yang persuasif tetapi penuh dengan tipu muslihat. Yang dijadikan orientasi hanya barangnya terkenal dan laku dijual. Mereka umumnya tidak mempertahankan loyalitas konsumen dan hubungan personal.
Calon kepala daerah ibarat sebuah merek yang perlu dijajakan ke masyarakat. Oleh karena itu, karena ia sebuah produk baru ia perlu dikenalkan ke masyarakat, diungkapkan kelebihan yang dimiliki. Tentunya, “perusahaan” yang mensponsorinya tidak hanya mengenalkan “merek” itu tanpa mengetahui atau menggaransi bahwa “barangnya” memang berkualitas.
Cara modern yang sedang menjadi program perusahaan adalah media relations di atas. Calon kepala daerah mau tidak mau harus melakukan strategi PR seperti halnya perusahaan itu.
Mengapa? Saat ini kita hidup dengan media massa (cetak dan elektronik). Apa yang kita pikir, kita perbuat, kita beli, kita sosialisasikan, kita ungkapkan tak lepas dari peran media massa itu. Bahkan bisa dikatakan media telah membentuk hidup kita sehari-hari. Jika kita mau jujur apa yang kita beli, kita pakai, kita kemukakan lebih banyak berdasar dari media massa. Ini realitas dari perkembangan masyarakat modern kita.
Akan arti pentingnya media massa Marshall McLuhan dalam buknya terkenal Understanding Media, The Extension of Man (1999) pernah mengatakan bahwa media adalah the extension of man (media adalah ekstensi/perluasan) manusia. Artinya, apa yang dipikirkan, diinginkan manusia bisa diperluas perwujudannya melalui media massa. Bahkan media massa berbuat lebih dari apa yang bisa dilakukan manusia.
Jika manusia hanya bisa berpidato dihadapan ribuan orang, media massa melakukannya ke jutaan orang. Akan berbeda dampaknya seandainya apa yang dipidatokan itu kemudian disiarkan media massa, meskipun hanya dihadapan puluhan orang saja. Sama artinya, buat apa demonstrasi besar-besaran tetapi media massa tidak menyiarkannya/memberitakannya? Lebih berdampak hebat jika demonstrasi kecil-kecilan tetapi bisa disiarkan media massa.
Begitu hebatnya media massa sampai Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, “Jika media dibiarkan saja, saya tidak akan bisa berkuasa lebih dari tiga bulan”. Atau simak pendapat bapak kemerdekaan Amerika, Thomas Jefferson, “Seandainya saya harus memilih antara kehidupan pemerintahan tanpa surat kabar dengan adanya surat kabar tanpa pemerintahan, saya -- tidak ragu-ragu lagi -- akan memilih yang terakhir; ada surat kabar tanpa adanya pemerintah". Pernyataan Bonaparte atau Jefferson itu tentu bukan bualan seorang anak kecil di siang bolong semata, tetapi dipikir secara dalam karena hebatnya pengaruh media massa bagi masyarakat.
Bagaimana Dengan Kandidat?
Calon kepala daerah bisa juga melakukan strategi media relations. Kita bisa mengambil contoh kasus kesuksesan presiden SBY dalam pemilihan presiden tahun lalu. Ia berhasil menuduki RI-1 tak lain karena kemampuannya membangun citra di media massa.
Untuk mewujudkan itu semua, para calon kepala daerah itu bisa melakukan kegiatan sebagai berikut; pertama, para calon harus menjalin hubungan dekat dengan media massa. Ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke dapur redaksi media yang bersangkutan. Media, karena dikunjungi calon kepala daerah, ada kemungkinan besar untuk memberitakannya. Ini pulalah yang dahulu pernah dilakukan SBY dan Amien Rais untuk menyaingi kepopuleran Megawati karena kedudukannya sebagai presiden sudah menarik perhatian media massa.
Kedua, undanglah media massa dimana calon itu melakukan kegiatan politik seperti kampanye, pidato politik, kebijakan yang akan diputuskan. Bisa jadi media tanpa diundangpun ingin meliputnya, tetapi mengundang mereka bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua calon.
Ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan kandidat bisa diketahui masyarakat. Paling tidak, masyarakat tahu bahwa “seseorang” itu calon kepala daerah.
Ketiga, sering-seringlah membuat press release (siaran pers). Entah memang ada kebijakan atau keinginan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau hal lain. Tetapi yang jelas, calon kepala daerah tidak boleh “menyakiti” pers. Atau membuat pernyataan yang membuat jengkel wartawan. Sebab, begitu sang kandidat membuat “kesalahan” seperti itu Anda mungkin tetap muncul di media massa tetapi dengan berita yang justru merugikan Anda sendiri. Termasuk di sini, menghindari untuk mengatakan “no comment”. Pernyataan seperti itu jelas tidak disukai oleh wartawan. Anda juga akan dicitrakan sebagai orang yang tertutup.
Tetapi ada satu hal lain yang harus dilakukan jika ia terpilih menjadi kepala daerah. Tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan. Umumnya, para politisi kita pada awalnya berhubungan baik dengan wartawan, tetapi ketika sudah “mapan” ia lupa bahkan menghindar dari wartawan. Biasanya, politisi itu takut karena “dosanya” diketahui umum.
Maka, mengaja hubungan baik dengan media massa tidak saja akan memuluskan langkah sang calon menjadi kepala daerah tetapi juga akan menentukan “hidup matinya” pemerintahan daerah yang dipimpinnya nanti. Sudah saatnya, menempatkan media massa di depan dan bukan dipolitisir untuk tujuan yang mementingkan kepentingannya sendiri.
Media massa punya mata dan telinga. Sang kandidat akan diberitakan baik manakala ia baik, tetapi akan diberitakan jelek jika sebaliknya. Jadi, saat ini hidup matinya calon kepala daerah sangat mungkin ditentukan oleh media massa. Readmore »»
Menyoal Jurnalisme Sensasional
Ketidakpuasan atas pembebasan Erwin Arnada, Pemimpin Redaksi (Pemred) majalah Play Boy atas semua tuduhan dan tuntutan jaksa tentang penyebaran tindak kesusilaan belum berhenti. Atas pembebasan tersebut, majalah yang pertama kali terbit pada 6 April 2006 itu secara hukum sah untuk diterbitkan kembali dan bahkan punya proteksi secara hukum.
Namun demikian, kelompok yang tidak suka dengan majalah lisensi Amerika tersebut akan terus melakukan perlawanan. Bahkan razia dan protes keras tinggal menunggu waktu. Dengan nada kecewa kelompok penentang ini mengucapkan, “Selamat datang di negeri porno” saat setelah putusan dibacakan.
Lepas dari perdebatan bahwa Play Boy menyebarkan pornografi atau bukan, yang layak untuk diperhatian adalah esensi semakin menguatnya jurnalisme sensasional di Indonesia. Jurnalisme ini lebih menentingkan segi yang menarik dan kurang memperhatikan sesuatu yang relevan. Mau bukti? Lihat saja televisi kita.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel pernah membuat sebuah analogi menarik kaitannya dengan jurnalisme sensasional ini. Bagi penulis buku The Element of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect itu, media sensasional diibaratkan dengan perilaku seseorang yang ingin menarik perhatian orang dengan pergi ke tempat umum, lalu melucuti semua yang dikenakaannya alias telanjang. Bisa jadi ada beberapa orang di sekitar yang ikut menikmati “tontotan” tersebut. Tetapi yang dipertanyakan oleh Kovach dan Rosenstiel adalah bagaimana orang telanjang tersebut menjaga kesetiaan penontonnya? Diperinci menjadi begini, bagaimana (apakah sanggup) media sensasional bisa menjamin kesetiaan pembacanya?
Ini tentu berbeda dengan media yang proporsional. Media yang proporsional diibaratkan sebagai seorang pemain gitar dengan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Tidak seperti orang yang telanjang tersebut dengan jumlah penonton yang banyak. Namun demikian, seiring dengan peningkatan kualitas dia bermain gitar, semakin lama semakin banyak orang yang memperhatikannya dan mendengarkannya. Media yang proporsional adalah media yang membangun kualitas beritanya sedikit demi sedikit, akhirnya memunculkan kesetiaan pembacanya bener-benar dibutuhkan.
Koran New York Times (NYT) adalah koran yang bisa dijadikan contoh media proporsional. Adolph Ochs pemilik NYT adalah orang yang anti terhadap sesuatu yang berbau populer dan sensasional. Populer dan sensasional ini di Amerika pernah disebut dengan koran kuning yang hanya menampilkan berbagai cerita-cerita sensasional, komik, dan juga gambar-gambar yang menuruti “selera rendah”. Ia hendak mengelola koran itu menjadi surat kabar yang serius, dan mengutamakan kepentingan publik. Tak heran karena ambisinya ia pernah menjual NTY dengan harga murah seharga 1 sen (sebelumnya koran itu dijual dengan 3 sen). Ini tentu bukan keputusan mudah. Tetapi perkembanganya sangat mengejutkan, dari sirkulasi 9000 eksemplar pada tahun 1896 menjadi 75.000 eksemplar tiga tahun kemudian (1899). Dua tahun sesudahnya (1902) oplahnya menjadi 100.000 eksemplar dan pemasukan iklannya menjadi dua kali lipat. Pada tahun 1980-an oplahnya mencapai 900.000 eksemplar dengan penghasilan 3,15 juta dollar per tahun. Inilah sejarah proporsionalitas koran yang sudah berumur 100 tahun lebih dan telah mengawal 20 presiden Amerika (Haryanto, 1996).
Ini juga pernah dilakukan oleh Eugene Meyer pada tahun 1933. Ia membeli harian The Washington Post sambil mengatakan, “Dalam rangka menyajikan kebenaran, surat kabar ini kalau perlu perlu akan mengorbankan keuntungan materialnya, jika tindakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat”. Keinginan kuat Meyer (sama dengan yang diyakini Ochs) ternyata benar bahwa proporsionalitas ternyata bukanlah omong kosong. Mereka menjadikan korannya prestisius sekaligus menguntungkan secara bisnis.
Masa Depan
Kenyataan yang terjadi di Amerika tersebut sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia. Media-media di Indonesia masih mengembangkan jurnalisme sensasional yang sarat dengan hiburan dan hal-hal yang menuruti selera masyarakat “kebanyakan”. Di televisi kita penuh dengan tayangan infotainment, ada yang menyebutnya dengan gosiptainment atau idiottainment. Semua berita dibingkai secara populer.
Kemenangan Play Boy di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu semakin menguatkan bahwa jurnalisme sensasional sedang menjadi pilihan alternatif meskipun belum tentu menjamin kelangsungannya dalam jangka panjang. Play Boy akhirnya akan merasa menjadi “pemenang” dan kelompok lain yang selama ini masih takut-takut membuat media seperti itu punya legitimasi kuat dan alasan yang lebih rasional. Play Boy tentu saja akan melahirkan “anak-anak” yang meniru perilaku “orang tuanya” itu.
Ini tentu saja logis. Di Indonesia ketika sebuah media atau acara tertentu di televisi sukses akan ditiru oleh media lain. Akamedi Fantasi Indosiar (AFI) memunculkan saingan Indonesian Idol, Pildacil, KDI, dan lain-lain. Acara sinetron religius yang “berbau mistik” pertama kali di TPI, kemudian diikuti oleh stasiun televisi lain. Lihat misalnya, Astaghfirullah dan Kuasa Ilahi (SCTV), Azab Ilahi dan Padamu Ya Rabb (Lativi), Taubat dan Hidayah (Trans TV), dan Titipan Ilahi (Indosiar) dan lain-lain.
Dampak lain yang akan sangat terasa adalah semakin menguatnya eskalasi kekerasan akibat “kemenangan” Play Boy atas FPI. FPI tentu saja belum sepenuhnya menerima kenyataan itu. Seperti yang selama ini dilakukan, mereka dengan dalih agama akan terus melakukan “razia” terhadap pornografi dan pornoaksi. Kalau perlu, harus ditempuh dengan jalan kekerasan mewujudkan keyakinannya tersebut. Tentu saja ini akan menjadi problem dan pekerjaan rumah bagi aparat keamanan, penegak hukum dan pemerintah sendiri.
Sementara itu, karena Play Boy punya landasan hukum kuat dan selaku pemenang akan semakin “tinggi hati” untuk terus melawan kegiatan FPI dengan terus menyebarkan majalah-majalahnya. Yang terjadi kemudian bukan lagi rasionalitas berpikir yang dikedepankan, tetapi emosi dan ego masing-masing kelompok yang kemudian melandasi setiap perilaku mereka. Bukan tidak mustahil, sebagaimana yang pernah saya tulis di harian Solo Pos, semakin dilarang, Play Boy justru akan semakin tersebar.
Yang jelas, Play Boy akhirnya akan menjadi dasar semakin menguatnya jurnalisme sensasional di Indonesia. Tetapi, suatu saat jurnalisme ini akan kehilangan simpati dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Sama seperti orang telanjang di tempat keramaian. Ia akhirnya tidak lagi mendapatkan popularitas, tetapi justru caci maki, hinaan dan rasa muak orang yang melihatnya. Readmore »»
Namun demikian, kelompok yang tidak suka dengan majalah lisensi Amerika tersebut akan terus melakukan perlawanan. Bahkan razia dan protes keras tinggal menunggu waktu. Dengan nada kecewa kelompok penentang ini mengucapkan, “Selamat datang di negeri porno” saat setelah putusan dibacakan.
Lepas dari perdebatan bahwa Play Boy menyebarkan pornografi atau bukan, yang layak untuk diperhatian adalah esensi semakin menguatnya jurnalisme sensasional di Indonesia. Jurnalisme ini lebih menentingkan segi yang menarik dan kurang memperhatikan sesuatu yang relevan. Mau bukti? Lihat saja televisi kita.
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel pernah membuat sebuah analogi menarik kaitannya dengan jurnalisme sensasional ini. Bagi penulis buku The Element of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect itu, media sensasional diibaratkan dengan perilaku seseorang yang ingin menarik perhatian orang dengan pergi ke tempat umum, lalu melucuti semua yang dikenakaannya alias telanjang. Bisa jadi ada beberapa orang di sekitar yang ikut menikmati “tontotan” tersebut. Tetapi yang dipertanyakan oleh Kovach dan Rosenstiel adalah bagaimana orang telanjang tersebut menjaga kesetiaan penontonnya? Diperinci menjadi begini, bagaimana (apakah sanggup) media sensasional bisa menjamin kesetiaan pembacanya?
Ini tentu berbeda dengan media yang proporsional. Media yang proporsional diibaratkan sebagai seorang pemain gitar dengan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Tidak seperti orang yang telanjang tersebut dengan jumlah penonton yang banyak. Namun demikian, seiring dengan peningkatan kualitas dia bermain gitar, semakin lama semakin banyak orang yang memperhatikannya dan mendengarkannya. Media yang proporsional adalah media yang membangun kualitas beritanya sedikit demi sedikit, akhirnya memunculkan kesetiaan pembacanya bener-benar dibutuhkan.
Koran New York Times (NYT) adalah koran yang bisa dijadikan contoh media proporsional. Adolph Ochs pemilik NYT adalah orang yang anti terhadap sesuatu yang berbau populer dan sensasional. Populer dan sensasional ini di Amerika pernah disebut dengan koran kuning yang hanya menampilkan berbagai cerita-cerita sensasional, komik, dan juga gambar-gambar yang menuruti “selera rendah”. Ia hendak mengelola koran itu menjadi surat kabar yang serius, dan mengutamakan kepentingan publik. Tak heran karena ambisinya ia pernah menjual NTY dengan harga murah seharga 1 sen (sebelumnya koran itu dijual dengan 3 sen). Ini tentu bukan keputusan mudah. Tetapi perkembanganya sangat mengejutkan, dari sirkulasi 9000 eksemplar pada tahun 1896 menjadi 75.000 eksemplar tiga tahun kemudian (1899). Dua tahun sesudahnya (1902) oplahnya menjadi 100.000 eksemplar dan pemasukan iklannya menjadi dua kali lipat. Pada tahun 1980-an oplahnya mencapai 900.000 eksemplar dengan penghasilan 3,15 juta dollar per tahun. Inilah sejarah proporsionalitas koran yang sudah berumur 100 tahun lebih dan telah mengawal 20 presiden Amerika (Haryanto, 1996).
Ini juga pernah dilakukan oleh Eugene Meyer pada tahun 1933. Ia membeli harian The Washington Post sambil mengatakan, “Dalam rangka menyajikan kebenaran, surat kabar ini kalau perlu perlu akan mengorbankan keuntungan materialnya, jika tindakan itu diperlukan demi kepentingan masyarakat”. Keinginan kuat Meyer (sama dengan yang diyakini Ochs) ternyata benar bahwa proporsionalitas ternyata bukanlah omong kosong. Mereka menjadikan korannya prestisius sekaligus menguntungkan secara bisnis.
Masa Depan
Kenyataan yang terjadi di Amerika tersebut sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia. Media-media di Indonesia masih mengembangkan jurnalisme sensasional yang sarat dengan hiburan dan hal-hal yang menuruti selera masyarakat “kebanyakan”. Di televisi kita penuh dengan tayangan infotainment, ada yang menyebutnya dengan gosiptainment atau idiottainment. Semua berita dibingkai secara populer.
Kemenangan Play Boy di PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu semakin menguatkan bahwa jurnalisme sensasional sedang menjadi pilihan alternatif meskipun belum tentu menjamin kelangsungannya dalam jangka panjang. Play Boy akhirnya akan merasa menjadi “pemenang” dan kelompok lain yang selama ini masih takut-takut membuat media seperti itu punya legitimasi kuat dan alasan yang lebih rasional. Play Boy tentu saja akan melahirkan “anak-anak” yang meniru perilaku “orang tuanya” itu.
Ini tentu saja logis. Di Indonesia ketika sebuah media atau acara tertentu di televisi sukses akan ditiru oleh media lain. Akamedi Fantasi Indosiar (AFI) memunculkan saingan Indonesian Idol, Pildacil, KDI, dan lain-lain. Acara sinetron religius yang “berbau mistik” pertama kali di TPI, kemudian diikuti oleh stasiun televisi lain. Lihat misalnya, Astaghfirullah dan Kuasa Ilahi (SCTV), Azab Ilahi dan Padamu Ya Rabb (Lativi), Taubat dan Hidayah (Trans TV), dan Titipan Ilahi (Indosiar) dan lain-lain.
Dampak lain yang akan sangat terasa adalah semakin menguatnya eskalasi kekerasan akibat “kemenangan” Play Boy atas FPI. FPI tentu saja belum sepenuhnya menerima kenyataan itu. Seperti yang selama ini dilakukan, mereka dengan dalih agama akan terus melakukan “razia” terhadap pornografi dan pornoaksi. Kalau perlu, harus ditempuh dengan jalan kekerasan mewujudkan keyakinannya tersebut. Tentu saja ini akan menjadi problem dan pekerjaan rumah bagi aparat keamanan, penegak hukum dan pemerintah sendiri.
Sementara itu, karena Play Boy punya landasan hukum kuat dan selaku pemenang akan semakin “tinggi hati” untuk terus melawan kegiatan FPI dengan terus menyebarkan majalah-majalahnya. Yang terjadi kemudian bukan lagi rasionalitas berpikir yang dikedepankan, tetapi emosi dan ego masing-masing kelompok yang kemudian melandasi setiap perilaku mereka. Bukan tidak mustahil, sebagaimana yang pernah saya tulis di harian Solo Pos, semakin dilarang, Play Boy justru akan semakin tersebar.
Yang jelas, Play Boy akhirnya akan menjadi dasar semakin menguatnya jurnalisme sensasional di Indonesia. Tetapi, suatu saat jurnalisme ini akan kehilangan simpati dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Sama seperti orang telanjang di tempat keramaian. Ia akhirnya tidak lagi mendapatkan popularitas, tetapi justru caci maki, hinaan dan rasa muak orang yang melihatnya. Readmore »»
Ada Apa dengan Iklan Aa Gym?
Anda mungkin diantara penonton televisi yang pernah melihat iklan Aa Gym (KH Abdullah Gymnastiar) yang membintangi sebuah iklan tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ternyata iklan tersebut mendapat protes masyarakat luas. Paling tidak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, dan Pelajar Islam Indonesia (PII) mempermasalahkan iklan itu.
Ceritanya, ada seorang bapak mematikan televisi yang tengah ditonton bersama keluarganya. Di layar muncul gambar unjuk rasa antikenaikan harga BBM. Disela-sela demonstrasi ada teriakan histeris perempuan lanjut usia memegang jerigen minyak tanah. Sambil terjepit antri ia berujar, “Kasihan Pak, yang kecil Pak”.
Adegan selanjutnya, di depan pintu sebuah rumah keluarga tersebut muncul Aa Gym. Ia berkata, “Saudaraku, kenaikan minyak dunia menjadi cobaan luar biasa bagi bangsa, termasuk kita. Kita harus siap menghadapi kenyataan”.
“Jadi gimana nasib orang miskin?” tanya si Bapak yang punya rumah.
Kiai itu menjawab, “Kita harus siap menghadapi kenyataan. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting kita kompak, bersatu, sabar, dan gigih mencari solusi. Kita harus dekat dengan Allah. Ingat kesabaran, pengorbanan, kalau ikhlas tidak disia-siakan Allah”.
Iklan tersebut ternyata adalah iklan yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) tentang kenaikan harga BBM lewat Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2005 belum lama ini.
Mengapa Diprotes?
Ada beberapa masalah mendasar mengapa iklan Aa Gym tersebut diprotes masyarakat. Pertama, Aa Gym telah menyeret wilayah profan yang bersifat keduniawian menjadi wilayah sakral yang bersifat keakhiratan. Kenaikan harga BBM adalah dampak dari kebijakan manusia, disebabkan manusia dan dilakukan oleh manusia. Dalam tataran kebijakan publik, kenaikan harga BBM adalah murni dilakukan oleh negara. Tetapi, wilayah negara ini diseret ke wilayah agama.
Iklan itu, lewat pernyataan Aa Gym, dianggap sebagai sebuah kehendak Tuhan. Kenaikan itu merupakan bagian dari rencana Illahi. Maka tak ada cara lain yang dilakukan manusia kecuali dengan menerima apa yang sudah digariskanNya dengan diimbangi oleh sikap sabar, ikhlas, dan rela berkorban.
Bahkan Aa Gym tidak lupa mengutip surat Al Baqoroh yang menyatakan bahwa “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya”. Tafsirannya adalah bahwa kekenaikan harga BBM sebagai rencana Illahi itu tidak akan membebani masyarakat. Tuhan sudah tahu bahwa kenaikan harga BBM sudah berada dalam kemampuan daya beli manusia Indonesia.
Di sinilah kemudian agama menjadi alat untuk legitimasi kepentingan politik pemerintah. Agama tidak ditempatkan sebagai ajaran kemanusiaan (terciptanya keadilan, kesejahteraan), tetapi digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah saja. Padahal kenaikan harga BBM itu lebih banyak karena peran pemerintah. Jika terjadi protes tidak harus mengembalikan kepada urusan Tuhan, tetapi ke pemerintah. Dalam hal ini ada pendangkalan masalah yang terjadi. Seolah urusan agama adalah urusan negara saja untuk mendukung dan tidak mendukung kekuasaan dirinya.
Kedua, protes masyarakat atas iklan Aa Gym tersebut karena iklan yang dikeluarkan Depkominfo itu telah mengerdilkan peran KH Abdullah Gymnastiar sebagai seorang kiai pengayom umat. Aa Gym cenderung membela pemerintah lewat Depkominfo dan justru tidak membela kepentingan orang banyak yang jelas merasa tersiksa dengan kenaikan harga BBM.
Dari sini ada disorientasi peran kiai. Ia yang dikenal dekat dengan rakyat, memberdayakan rakyat lewat kegiatan ekonominya justru lebih memihak pemerintah. Bukan tidak boleh, hanya akan merugikan dirinya dan masyarakat pada umumnya.
Maka, protes yang dilakukan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah perilaku kecintaan mereka pada pemimpin pesantren Darut Tauhid tersebut. Mereka tentu tidak ingin peran kiainya menjadi kerdil hanya gara-gara membintangi iklan. Dan tentu saja, perilakunya jangan-jangan diikuti kiai-kiai yang lebih muda. Kalau begitu, jabatan kiai benar-benar sangat politis sekali.
Ketiga, iklan dalam banyak hal setengahnya adalah bohong. Sementara itu, meskipun apa yang dilakukan Aa Gym itu Iklan Layanan Masyarakat (ILM), tetap mengandung setengahnya bohong. Coba kita simak iklan-iklan di televisi yanga hanya mengejar asal laku dan tidak banyak yang memberikan informasi secara benar. Iklan mutlak bersifat persuasif. Misalnya, mana ada obat pusing yang bisa menghilangkan sakit kepala dalam waktu satu menit?
Keterlibatan kiai dalam iklan telah menurunkan citra kiai pula sebagai pemimpin umat. Kiai akan dituduh mementingkan kepentingan pribadi karena iklan lebih punya popularitas dan punya dampak keuntungan materi lebih banyak dari pada memberikan nasihat keagamaan pada masyarakat.
Tentu saja ini tak menuduh bahwa kiai model tersebut sangat materialistis. Tetapi yang jelas, kiai adalah sebutan yang diberikan masyarakat karena kelebihannya dalam pemahaman masalah keagamaan yang bisa dijadikan acuan masyarakat awam. Kalau kiai sudah memihak, maka sebutan kiai jelas sudah mulai digerogoti dari dirinya. Apalagi, Padahal, Aa Gym adalah kiai yang cukup dekat dengan rakyat dan punya pengikut yang banyak selama ini.
Sakralisasi
Dari permasalahan di atas, layak kiranya masyarakat memprotes iklan kenaikan harga BBM yang dibintangi oleh Aa Gym tersebut. Kenaikan harga BBM memang sebuah keniscayaan, tetapi keniscayaan tersebut tidak perlu menyeret persoalan agama. Agama punya wilayah tersendiri yang berbeda dengan wilayah politik. Biarlah politik diurusi oleh pemerintah, sementara kalangan agamawan tidak perlu untuk ikut-ikutan terlibat di dalamnya.
Yang menjadi kekhawatiran adalah jika politik dicampuradukkan dengan agama adalah terjadinya sakralisasi kebijakan. Bukan tidak mustahil karena dilegitimasi kiai kondang seperti Aa Gym, kenaikan harga BBM menjadi sesuatu yang harus diterima. Sesuatu yang harus diterima ini lebih berbahaya jika masyarakat menganggap kenaikan harga BBM sebagai ajaran agama karena dilegitimasi oleh seorang kiai. Ini hampir sama kasusnya dengan dukungan kiai pada salah satu partai politik (parpol) yang mensakralkan wilayah politik (parpol) karena dukungan agama (para kiai).
Kalau wilayah politik mengalami sakralisasi, berbagai perubahan akan sulit dilakukan karena kebijakan negara berlindung dibalik “jubah” agama. Memprotes kebijakan pemerintah (salah satunya kenaikan harga BBM) tidak akan dilakukan masyarakat karena dianggap memprotes ajaran agamanya pula.
Dari sinilah agama akan mengalami penurunan maknanya yang suci. Yang dikhawatirkan adalah agama mengalami materialisasi. Artinya orang akan memeluk agama bukan karena ajarannya, tetapi karena memberikan keuntungan materi. Dari sinilah protes terhadap iklan yang dibintangi Aa Gym harus ditempatkan dan dipahami secara bijak. Readmore »»
Ceritanya, ada seorang bapak mematikan televisi yang tengah ditonton bersama keluarganya. Di layar muncul gambar unjuk rasa antikenaikan harga BBM. Disela-sela demonstrasi ada teriakan histeris perempuan lanjut usia memegang jerigen minyak tanah. Sambil terjepit antri ia berujar, “Kasihan Pak, yang kecil Pak”.
Adegan selanjutnya, di depan pintu sebuah rumah keluarga tersebut muncul Aa Gym. Ia berkata, “Saudaraku, kenaikan minyak dunia menjadi cobaan luar biasa bagi bangsa, termasuk kita. Kita harus siap menghadapi kenyataan”.
“Jadi gimana nasib orang miskin?” tanya si Bapak yang punya rumah.
Kiai itu menjawab, “Kita harus siap menghadapi kenyataan. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang penting kita kompak, bersatu, sabar, dan gigih mencari solusi. Kita harus dekat dengan Allah. Ingat kesabaran, pengorbanan, kalau ikhlas tidak disia-siakan Allah”.
Iklan tersebut ternyata adalah iklan yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) tentang kenaikan harga BBM lewat Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2005 belum lama ini.
Mengapa Diprotes?
Ada beberapa masalah mendasar mengapa iklan Aa Gym tersebut diprotes masyarakat. Pertama, Aa Gym telah menyeret wilayah profan yang bersifat keduniawian menjadi wilayah sakral yang bersifat keakhiratan. Kenaikan harga BBM adalah dampak dari kebijakan manusia, disebabkan manusia dan dilakukan oleh manusia. Dalam tataran kebijakan publik, kenaikan harga BBM adalah murni dilakukan oleh negara. Tetapi, wilayah negara ini diseret ke wilayah agama.
Iklan itu, lewat pernyataan Aa Gym, dianggap sebagai sebuah kehendak Tuhan. Kenaikan itu merupakan bagian dari rencana Illahi. Maka tak ada cara lain yang dilakukan manusia kecuali dengan menerima apa yang sudah digariskanNya dengan diimbangi oleh sikap sabar, ikhlas, dan rela berkorban.
Bahkan Aa Gym tidak lupa mengutip surat Al Baqoroh yang menyatakan bahwa “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya”. Tafsirannya adalah bahwa kekenaikan harga BBM sebagai rencana Illahi itu tidak akan membebani masyarakat. Tuhan sudah tahu bahwa kenaikan harga BBM sudah berada dalam kemampuan daya beli manusia Indonesia.
Di sinilah kemudian agama menjadi alat untuk legitimasi kepentingan politik pemerintah. Agama tidak ditempatkan sebagai ajaran kemanusiaan (terciptanya keadilan, kesejahteraan), tetapi digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah saja. Padahal kenaikan harga BBM itu lebih banyak karena peran pemerintah. Jika terjadi protes tidak harus mengembalikan kepada urusan Tuhan, tetapi ke pemerintah. Dalam hal ini ada pendangkalan masalah yang terjadi. Seolah urusan agama adalah urusan negara saja untuk mendukung dan tidak mendukung kekuasaan dirinya.
Kedua, protes masyarakat atas iklan Aa Gym tersebut karena iklan yang dikeluarkan Depkominfo itu telah mengerdilkan peran KH Abdullah Gymnastiar sebagai seorang kiai pengayom umat. Aa Gym cenderung membela pemerintah lewat Depkominfo dan justru tidak membela kepentingan orang banyak yang jelas merasa tersiksa dengan kenaikan harga BBM.
Dari sini ada disorientasi peran kiai. Ia yang dikenal dekat dengan rakyat, memberdayakan rakyat lewat kegiatan ekonominya justru lebih memihak pemerintah. Bukan tidak boleh, hanya akan merugikan dirinya dan masyarakat pada umumnya.
Maka, protes yang dilakukan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah perilaku kecintaan mereka pada pemimpin pesantren Darut Tauhid tersebut. Mereka tentu tidak ingin peran kiainya menjadi kerdil hanya gara-gara membintangi iklan. Dan tentu saja, perilakunya jangan-jangan diikuti kiai-kiai yang lebih muda. Kalau begitu, jabatan kiai benar-benar sangat politis sekali.
Ketiga, iklan dalam banyak hal setengahnya adalah bohong. Sementara itu, meskipun apa yang dilakukan Aa Gym itu Iklan Layanan Masyarakat (ILM), tetap mengandung setengahnya bohong. Coba kita simak iklan-iklan di televisi yanga hanya mengejar asal laku dan tidak banyak yang memberikan informasi secara benar. Iklan mutlak bersifat persuasif. Misalnya, mana ada obat pusing yang bisa menghilangkan sakit kepala dalam waktu satu menit?
Keterlibatan kiai dalam iklan telah menurunkan citra kiai pula sebagai pemimpin umat. Kiai akan dituduh mementingkan kepentingan pribadi karena iklan lebih punya popularitas dan punya dampak keuntungan materi lebih banyak dari pada memberikan nasihat keagamaan pada masyarakat.
Tentu saja ini tak menuduh bahwa kiai model tersebut sangat materialistis. Tetapi yang jelas, kiai adalah sebutan yang diberikan masyarakat karena kelebihannya dalam pemahaman masalah keagamaan yang bisa dijadikan acuan masyarakat awam. Kalau kiai sudah memihak, maka sebutan kiai jelas sudah mulai digerogoti dari dirinya. Apalagi, Padahal, Aa Gym adalah kiai yang cukup dekat dengan rakyat dan punya pengikut yang banyak selama ini.
Sakralisasi
Dari permasalahan di atas, layak kiranya masyarakat memprotes iklan kenaikan harga BBM yang dibintangi oleh Aa Gym tersebut. Kenaikan harga BBM memang sebuah keniscayaan, tetapi keniscayaan tersebut tidak perlu menyeret persoalan agama. Agama punya wilayah tersendiri yang berbeda dengan wilayah politik. Biarlah politik diurusi oleh pemerintah, sementara kalangan agamawan tidak perlu untuk ikut-ikutan terlibat di dalamnya.
Yang menjadi kekhawatiran adalah jika politik dicampuradukkan dengan agama adalah terjadinya sakralisasi kebijakan. Bukan tidak mustahil karena dilegitimasi kiai kondang seperti Aa Gym, kenaikan harga BBM menjadi sesuatu yang harus diterima. Sesuatu yang harus diterima ini lebih berbahaya jika masyarakat menganggap kenaikan harga BBM sebagai ajaran agama karena dilegitimasi oleh seorang kiai. Ini hampir sama kasusnya dengan dukungan kiai pada salah satu partai politik (parpol) yang mensakralkan wilayah politik (parpol) karena dukungan agama (para kiai).
Kalau wilayah politik mengalami sakralisasi, berbagai perubahan akan sulit dilakukan karena kebijakan negara berlindung dibalik “jubah” agama. Memprotes kebijakan pemerintah (salah satunya kenaikan harga BBM) tidak akan dilakukan masyarakat karena dianggap memprotes ajaran agamanya pula.
Dari sinilah agama akan mengalami penurunan maknanya yang suci. Yang dikhawatirkan adalah agama mengalami materialisasi. Artinya orang akan memeluk agama bukan karena ajarannya, tetapi karena memberikan keuntungan materi. Dari sinilah protes terhadap iklan yang dibintangi Aa Gym harus ditempatkan dan dipahami secara bijak. Readmore »»
Langganan:
Postingan (Atom)