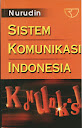Karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan secara langsung, calon kepala daerah tidak akan bisa lepas dari strategi Public Relations (PR) modern. Ini tak lain karena kita sudah hidup dalam dunia media massa yang kian canggih. Bahkan dalam bukunya The Fall of Advertising and the Rise of PR, Al Ries & Laura Ries (2003) pernah mengatakan, saat ini era periklanan sudah mati, yang muncul adalah era PR.
Calon kepala daerah ibarat sebuah barang dan merek. Kita tidak akan bisa meluncurkan sebuah merek hanya dengan iklan saja. Iklan punya kredibilitas rendah bahkan dianggap membohongi, sementara PR punya persepsi positif.
Contoh dalam kasus pemasaran misalnya begini. Manakah diantara merek dibawah ini yang sering Anda dengar? Cardinal Halth, Delphi Automotive, Ingram Micro, Lehman Brother Holdings, McKesson HBOC, Liant Energy Southern , Tosco, TIA CREF, Utilicorp United atau Microsoft?
Tidak perlu diragukan lagi, bahwa nama Microsoft lebih akrab di telinga kita. Padahal sepuluh perusahaan selain Microsoft di atas lebih besar. Tetapi, kesepuluh perusahaan tersebut tidak satupun yang membangun merek sebanding dengan Microsoft. Padahal, TIA-CREF (misalnya) beberapa tahun lalu pernah mempunyai pemasukan sebesar $38 milyar, sedangkan Microsoft hanya $23 milyar. Tetapi Microsoft adalah sebuah merek.
Media Relations
Itu pulalah kenapa calon kepala daerah tidak hanya bisa mengandalkan iklan sebagai salah satu cara untuk mempopulerkan dirinya di tengah masyarakat. Saat ini masyarakat juga semakin rasional sehingga hubungan emosional dan psikologis bukan satu-satunya cara jitu untuk meraih simpati masyarakat. Misalnya, mentang-mentang seorang kandidat adalah pemuka keagamaan otomatis akan memudahkan dirinya menjadi kepala daerah. Itu belum merupakan garansi.
Satu strategi PR yang saat ini populer adalah media relations (hubungan media). Dalam komunikasi pemasaran, cara ini sedang digalakkan dan menjadi program cerdas perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan kecil biasanya hanya mengandalkan iklan dengan isi yang persuasif tetapi penuh dengan tipu muslihat. Yang dijadikan orientasi hanya barangnya terkenal dan laku dijual. Mereka umumnya tidak mempertahankan loyalitas konsumen dan hubungan personal.
Calon kepala daerah ibarat sebuah merek yang perlu dijajakan ke masyarakat. Oleh karena itu, karena ia sebuah produk baru ia perlu dikenalkan ke masyarakat, diungkapkan kelebihan yang dimiliki. Tentunya, “perusahaan” yang mensponsorinya tidak hanya mengenalkan “merek” itu tanpa mengetahui atau menggaransi bahwa “barangnya” memang berkualitas.
Cara modern yang sedang menjadi program perusahaan adalah media relations di atas. Calon kepala daerah mau tidak mau harus melakukan strategi PR seperti halnya perusahaan itu.
Mengapa? Saat ini kita hidup dengan media massa (cetak dan elektronik). Apa yang kita pikir, kita perbuat, kita beli, kita sosialisasikan, kita ungkapkan tak lepas dari peran media massa itu. Bahkan bisa dikatakan media telah membentuk hidup kita sehari-hari. Jika kita mau jujur apa yang kita beli, kita pakai, kita kemukakan lebih banyak berdasar dari media massa. Ini realitas dari perkembangan masyarakat modern kita.
Akan arti pentingnya media massa Marshall McLuhan dalam buknya terkenal Understanding Media, The Extension of Man (1999) pernah mengatakan bahwa media adalah the extension of man (media adalah ekstensi/perluasan) manusia. Artinya, apa yang dipikirkan, diinginkan manusia bisa diperluas perwujudannya melalui media massa. Bahkan media massa berbuat lebih dari apa yang bisa dilakukan manusia.
Jika manusia hanya bisa berpidato dihadapan ribuan orang, media massa melakukannya ke jutaan orang. Akan berbeda dampaknya seandainya apa yang dipidatokan itu kemudian disiarkan media massa, meskipun hanya dihadapan puluhan orang saja. Sama artinya, buat apa demonstrasi besar-besaran tetapi media massa tidak menyiarkannya/memberitakannya? Lebih berdampak hebat jika demonstrasi kecil-kecilan tetapi bisa disiarkan media massa.
Begitu hebatnya media massa sampai Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, “Jika media dibiarkan saja, saya tidak akan bisa berkuasa lebih dari tiga bulan”. Atau simak pendapat bapak kemerdekaan Amerika, Thomas Jefferson, “Seandainya saya harus memilih antara kehidupan pemerintahan tanpa surat kabar dengan adanya surat kabar tanpa pemerintahan, saya -- tidak ragu-ragu lagi -- akan memilih yang terakhir; ada surat kabar tanpa adanya pemerintah". Pernyataan Bonaparte atau Jefferson itu tentu bukan bualan seorang anak kecil di siang bolong semata, tetapi dipikir secara dalam karena hebatnya pengaruh media massa bagi masyarakat.
Bagaimana Dengan Kandidat?
Calon kepala daerah bisa juga melakukan strategi media relations. Kita bisa mengambil contoh kasus kesuksesan presiden SBY dalam pemilihan presiden tahun lalu. Ia berhasil menuduki RI-1 tak lain karena kemampuannya membangun citra di media massa.
Untuk mewujudkan itu semua, para calon kepala daerah itu bisa melakukan kegiatan sebagai berikut; pertama, para calon harus menjalin hubungan dekat dengan media massa. Ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke dapur redaksi media yang bersangkutan. Media, karena dikunjungi calon kepala daerah, ada kemungkinan besar untuk memberitakannya. Ini pulalah yang dahulu pernah dilakukan SBY dan Amien Rais untuk menyaingi kepopuleran Megawati karena kedudukannya sebagai presiden sudah menarik perhatian media massa.
Kedua, undanglah media massa dimana calon itu melakukan kegiatan politik seperti kampanye, pidato politik, kebijakan yang akan diputuskan. Bisa jadi media tanpa diundangpun ingin meliputnya, tetapi mengundang mereka bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua calon.
Ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan kandidat bisa diketahui masyarakat. Paling tidak, masyarakat tahu bahwa “seseorang” itu calon kepala daerah.
Ketiga, sering-seringlah membuat press release (siaran pers). Entah memang ada kebijakan atau keinginan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau hal lain. Tetapi yang jelas, calon kepala daerah tidak boleh “menyakiti” pers. Atau membuat pernyataan yang membuat jengkel wartawan. Sebab, begitu sang kandidat membuat “kesalahan” seperti itu Anda mungkin tetap muncul di media massa tetapi dengan berita yang justru merugikan Anda sendiri. Termasuk di sini, menghindari untuk mengatakan “no comment”. Pernyataan seperti itu jelas tidak disukai oleh wartawan. Anda juga akan dicitrakan sebagai orang yang tertutup.
Tetapi ada satu hal lain yang harus dilakukan jika ia terpilih menjadi kepala daerah. Tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan. Umumnya, para politisi kita pada awalnya berhubungan baik dengan wartawan, tetapi ketika sudah “mapan” ia lupa bahkan menghindar dari wartawan. Biasanya, politisi itu takut karena “dosanya” diketahui umum.
Maka, mengaja hubungan baik dengan media massa tidak saja akan memuluskan langkah sang calon menjadi kepala daerah tetapi juga akan menentukan “hidup matinya” pemerintahan daerah yang dipimpinnya nanti. Sudah saatnya, menempatkan media massa di depan dan bukan dipolitisir untuk tujuan yang mementingkan kepentingannya sendiri.
Media massa punya mata dan telinga. Sang kandidat akan diberitakan baik manakala ia baik, tetapi akan diberitakan jelek jika sebaliknya. Jadi, saat ini hidup matinya calon kepala daerah sangat mungkin ditentukan oleh media massa.
Readmore »»
Rendahnya Pengaruh Media Massa dalam Pilpres 2004
Tak satupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menyangsikan kekuatan media massa dalam mempengaruhi perilaku pemilih pada Pemilu 2004 tahun ini. Hal ini terbukti bahwa semua kandidat merasa perlu untuk melakukan kegiatan yang punya dampak diliput media massa. Bahkan, ratusan juta rupiah sudah dikeluarkan untuk memasang iklan sebelum kampanye resmi diperbolehkan. Ini membuktikan bahwa media massa dianggap sangat penting dalam mempengaruhi opini publik.
Yang menjadi persoalan kita kemudian adalah apakah media massa punya pengaruh sangat kuat (unlimited effect) dalam mengubah perilaku pemilih pada Pemilihan Presiden (pilpres) 5 Juli 2004 nanti?
Media massa memang diyakini punya pengaruh kuat dalam mempengaruhi opini mayarakat itu tidak bisa dibantah. Tetapi, mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat dalam Pilpres nanti masih perlu dikaji lebih jauh. Ini tak bermaksud mengecilkan peran media massa. Masalahnya, perubahan perilaku pemilih sangat berkait erat dengan banyak faktor. Tulisan ini akan membahas berbagai faktor yang ikut mempengaruhi kenapa media massa punya peran kecil dalam mengubah perilaku pemilih.
Survei Membuktikan
Di Amerika Serikat (AS) pernah dibuktikan bahwa media massa tak punya pengaruh kuat pada diri audience dalam perubahan pilihan mereka. CBS News Release pada bulan Oktober 1980 pernah menyelenggarakan polling secara langsung setelah terjadi debat kandidat presiden antara Jimmy Carter dan Ronald Reagen. Ternyata, hanya 7 persen pendukung Carter yang pindah untuk mendukung Reagen. Dengan kata lain, ada perubahan perilaku pemilih tetapi tak besar-besaran (massive).
Paul Lazarfeld, Bernard Barelson dan H Gudet dalam tulisannya “The People’s Choice” (pilihan rakyat) pernah juga menunjukkan bahwa media massa punya pengaruh terbatas (limited effect) dalam mempengaruhi masyarakat, terutama dalam masalah pemilihan presiden.
Perhatian para peneliti tersebut adalah memfokuskan pengaruh kampanye pada perilaku pemberian suara. Mereka mencari bukti seberapa jauh “perubahan” yang terjadi pada diri para pemilih. Misalnya, berapa besar dari para pemilih itu “membelot” dari pilihannya semula setelah adanya kampanye politik tadi. Ternyata, hanya sekitar 8 persen para pemilih itu membuat perubahan pilihan sepanjang waktu penelitian. Ini artinya bahwa perubahan tersebut relatif kecil. Dengan kata lain, efek media massa sangatlah kecil. Studi di Elmira, Rovere dan Decatur juga menjadi bukti bahwa media massa punya efek terbatas.
Mengapa ini terjadi? Peranan pemimpin opini (opinion leader) ikut andil dalam menentukan pilihan masyarakat. Artinya, pengaruh yang mengenai audience tidak disebabkan oleh terpaan media massa, tetapi pemimpin opini tadi. Jadi pemimpin opini di sini berfungsi sebagai penerusan pesan-pesan media massa. Bahkan pesan-pesan yang diterima audience sudah diinterpretasikan oleh para pemimpin opini tersebut.
Media Massa dan Pilpres Indonesia
Sekarang masalahnya adalah jika media massa punya pengaruh yang terbatas dalam Pilpres 5 Juli 2004 mendatang apa yang menyebabkannya? Pertama, munculnya pengaruh pemimpin opini (kiai, dukun, pemuka adat, key person masyarakat) di Indonesia yang kian menguat. Sebab tanpa bisa dipungkiri, peran pemimpin opini ini masih dijadikan rujukan utama seseorang akan menentukan pilihan mendukung kadidat tertentu atau tidak. Masyarakat Indonesia mayoritas masih tinggal di pedesaan. Sehingga dasar pilihannya bukan pada pertimbangan rasional tetapi masih berdasarkan pada ikatan emosional dan primordial.
Perilaku memilih massa Nahdlatul Ulama (NU) sangat ditentukan oleh “himbauan” para kiai. Apalagi massa ini juga mayoritas tinggal di pesesaan. Menjadikan kata kiai sebagai bahan rujukan untuk memilih masih ditempatkan pada posisi depan. Itu pulalah kenapa, para kandidat presiden merasa perlu untuk mendekati atau “minta restu” para kiai. Itu tak lain karena para kiai tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pemilih dalam Pemilu tahun ini.
Bagaimana dengan Muhammadiyah? Warga ini juga tidak jauh berbeda. Meskipun sering dikatakan lebih rasional dalam berpikir dan banyak yang bertempat tinggal di perkotaan tetapi dasar pilihan masih tetap pada apa yang sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah. Karena Buya Syafii Ma’arif selaku Ketua PP Muhammadiyah sudah memutuskan untuk mendukung pasangan Amien Rais-Siswono, warga Muhammadiyah tentu tak jauh berbeda perilaku pilihannya. Kalaupun ada perubahan tidaklah begitu besar. Ikatan primordial keorganisasian masih menjadi faktor dominan yang ikut menentukan perilaku memilih warga Muhammadiyah.
Kenyataan ini juga berlaku untuk kandidat lain. Massa PDI-P tentu masih akan setia dengan Megawati, apapun kelemahannya. Faktor keaderahan (luar Jawa) tentu akan menjadikan alasan kuat untuk memilih Yusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Sementara Wiranto, SBY dan Agum Gumelar akan mendulang suara dari kalangan militer serta didukung oleh swing voters.
Kedua, audience lebih banyak menyukai acara hiburan daripada pembicaraan politik. Maka dalam urusan politik prosentase yang diraih oleh penonton sangat sedikit. Bahkan secara provokatif Searson dan Chaffe (1979) mengatakan, “Perubahan besar-besaran akibat pemberitaan politik pemilihan presiden bisa jadi tidak mungkin”.
Fenomena ini memang terjadi di Amerika, tetapi sangat mungkin terjadi pula di Indonesia. Apalagi, tingkat melek huruf masyarakat kita relatif masih kecil. Artinya pula, pengaruh media massa dalam mempegaruhi perilaku pemilih tidaklah besar. Alasannya, acara politik seperti debat calon presiden dan kampanye presiden biasa dinikmati oleh mereka yang taraf pendidikannya tinggi, itupun belum tentu semua dari mereka menyukainya.
Dengan demikian, mengandalkan liputan media massa dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilpres 2004 ini bukan menjadi jaminan terjadi perubahan besar-besaran pada diri pemilih. Media sekadar menjadi alat yang ikut mempengaruhi opini publik. Mungkin benar, bahwa opini masyarakat mengatakan calon tertentu layak untuk dipilih karena berdasar pemberitaan positif dari media massa. Tetapi, soal memilih itu masalah lain. Jadi belum tentu apa yang diopinikan masyarakat mewakili pilihan yang dilakukan pada Pilpres 2004. Tetapi meskipun begitu, media massa tetap punya andil besar dalam menciptakan citra seorang kandidat. Citra buruk yang dibangun dan diberitakan media massa bukan mustahil akan mempengaruhi pilihan masyarakatnya. Readmore »»
Yang menjadi persoalan kita kemudian adalah apakah media massa punya pengaruh sangat kuat (unlimited effect) dalam mengubah perilaku pemilih pada Pemilihan Presiden (pilpres) 5 Juli 2004 nanti?
Media massa memang diyakini punya pengaruh kuat dalam mempengaruhi opini mayarakat itu tidak bisa dibantah. Tetapi, mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat dalam Pilpres nanti masih perlu dikaji lebih jauh. Ini tak bermaksud mengecilkan peran media massa. Masalahnya, perubahan perilaku pemilih sangat berkait erat dengan banyak faktor. Tulisan ini akan membahas berbagai faktor yang ikut mempengaruhi kenapa media massa punya peran kecil dalam mengubah perilaku pemilih.
Survei Membuktikan
Di Amerika Serikat (AS) pernah dibuktikan bahwa media massa tak punya pengaruh kuat pada diri audience dalam perubahan pilihan mereka. CBS News Release pada bulan Oktober 1980 pernah menyelenggarakan polling secara langsung setelah terjadi debat kandidat presiden antara Jimmy Carter dan Ronald Reagen. Ternyata, hanya 7 persen pendukung Carter yang pindah untuk mendukung Reagen. Dengan kata lain, ada perubahan perilaku pemilih tetapi tak besar-besaran (massive).
Paul Lazarfeld, Bernard Barelson dan H Gudet dalam tulisannya “The People’s Choice” (pilihan rakyat) pernah juga menunjukkan bahwa media massa punya pengaruh terbatas (limited effect) dalam mempengaruhi masyarakat, terutama dalam masalah pemilihan presiden.
Perhatian para peneliti tersebut adalah memfokuskan pengaruh kampanye pada perilaku pemberian suara. Mereka mencari bukti seberapa jauh “perubahan” yang terjadi pada diri para pemilih. Misalnya, berapa besar dari para pemilih itu “membelot” dari pilihannya semula setelah adanya kampanye politik tadi. Ternyata, hanya sekitar 8 persen para pemilih itu membuat perubahan pilihan sepanjang waktu penelitian. Ini artinya bahwa perubahan tersebut relatif kecil. Dengan kata lain, efek media massa sangatlah kecil. Studi di Elmira, Rovere dan Decatur juga menjadi bukti bahwa media massa punya efek terbatas.
Mengapa ini terjadi? Peranan pemimpin opini (opinion leader) ikut andil dalam menentukan pilihan masyarakat. Artinya, pengaruh yang mengenai audience tidak disebabkan oleh terpaan media massa, tetapi pemimpin opini tadi. Jadi pemimpin opini di sini berfungsi sebagai penerusan pesan-pesan media massa. Bahkan pesan-pesan yang diterima audience sudah diinterpretasikan oleh para pemimpin opini tersebut.
Media Massa dan Pilpres Indonesia
Sekarang masalahnya adalah jika media massa punya pengaruh yang terbatas dalam Pilpres 5 Juli 2004 mendatang apa yang menyebabkannya? Pertama, munculnya pengaruh pemimpin opini (kiai, dukun, pemuka adat, key person masyarakat) di Indonesia yang kian menguat. Sebab tanpa bisa dipungkiri, peran pemimpin opini ini masih dijadikan rujukan utama seseorang akan menentukan pilihan mendukung kadidat tertentu atau tidak. Masyarakat Indonesia mayoritas masih tinggal di pedesaan. Sehingga dasar pilihannya bukan pada pertimbangan rasional tetapi masih berdasarkan pada ikatan emosional dan primordial.
Perilaku memilih massa Nahdlatul Ulama (NU) sangat ditentukan oleh “himbauan” para kiai. Apalagi massa ini juga mayoritas tinggal di pesesaan. Menjadikan kata kiai sebagai bahan rujukan untuk memilih masih ditempatkan pada posisi depan. Itu pulalah kenapa, para kandidat presiden merasa perlu untuk mendekati atau “minta restu” para kiai. Itu tak lain karena para kiai tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pemilih dalam Pemilu tahun ini.
Bagaimana dengan Muhammadiyah? Warga ini juga tidak jauh berbeda. Meskipun sering dikatakan lebih rasional dalam berpikir dan banyak yang bertempat tinggal di perkotaan tetapi dasar pilihan masih tetap pada apa yang sudah diputuskan oleh PP Muhammadiyah. Karena Buya Syafii Ma’arif selaku Ketua PP Muhammadiyah sudah memutuskan untuk mendukung pasangan Amien Rais-Siswono, warga Muhammadiyah tentu tak jauh berbeda perilaku pilihannya. Kalaupun ada perubahan tidaklah begitu besar. Ikatan primordial keorganisasian masih menjadi faktor dominan yang ikut menentukan perilaku memilih warga Muhammadiyah.
Kenyataan ini juga berlaku untuk kandidat lain. Massa PDI-P tentu masih akan setia dengan Megawati, apapun kelemahannya. Faktor keaderahan (luar Jawa) tentu akan menjadikan alasan kuat untuk memilih Yusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Sementara Wiranto, SBY dan Agum Gumelar akan mendulang suara dari kalangan militer serta didukung oleh swing voters.
Kedua, audience lebih banyak menyukai acara hiburan daripada pembicaraan politik. Maka dalam urusan politik prosentase yang diraih oleh penonton sangat sedikit. Bahkan secara provokatif Searson dan Chaffe (1979) mengatakan, “Perubahan besar-besaran akibat pemberitaan politik pemilihan presiden bisa jadi tidak mungkin”.
Fenomena ini memang terjadi di Amerika, tetapi sangat mungkin terjadi pula di Indonesia. Apalagi, tingkat melek huruf masyarakat kita relatif masih kecil. Artinya pula, pengaruh media massa dalam mempegaruhi perilaku pemilih tidaklah besar. Alasannya, acara politik seperti debat calon presiden dan kampanye presiden biasa dinikmati oleh mereka yang taraf pendidikannya tinggi, itupun belum tentu semua dari mereka menyukainya.
Dengan demikian, mengandalkan liputan media massa dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilpres 2004 ini bukan menjadi jaminan terjadi perubahan besar-besaran pada diri pemilih. Media sekadar menjadi alat yang ikut mempengaruhi opini publik. Mungkin benar, bahwa opini masyarakat mengatakan calon tertentu layak untuk dipilih karena berdasar pemberitaan positif dari media massa. Tetapi, soal memilih itu masalah lain. Jadi belum tentu apa yang diopinikan masyarakat mewakili pilihan yang dilakukan pada Pilpres 2004. Tetapi meskipun begitu, media massa tetap punya andil besar dalam menciptakan citra seorang kandidat. Citra buruk yang dibangun dan diberitakan media massa bukan mustahil akan mempengaruhi pilihan masyarakatnya. Readmore »»
Mendesak, Strategi Media Calon Kepala Daerah
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung Jawa Tengah (Jateng) dalam waktu dekat akan digelar. Hiruk pikuk untuk menyambut perhelatan demokrasi di daerah itu sudah dirasakan dimana-mana. Berbagai spanduk, stiker, baliho identitas para kandidat sudah bermunculan hampir di setiap tempat. Model kampanye terselubung seperti itu juga dilakukan oleh masing-masing kandidat dengan berbagai cara agar dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi, kampanye itu tidak akan populer dan berdampak kuat tanpa peran media massa. Inilah kunci pemenangan Pilkada Jatim.
McGinniss (1969) dalam The Selling of The President 1968 menyebutkan adanya kekuatan menentukan yang diperankan oleh media massa dalam pemilihan. Alasannya, media massa dalam praktiknya ikut menentukan pilihan seseorang setelah ikut membentuk, manipulasi citra yang dilakukan seorang kandidat. Terbukti, ada peningkatan jumlah pemilih secara drastis terhadap seorang kandidat setelah dipublikasi media massa.
Maka, media juga secara sengaja telah memainkan peran besar dalam menjadikan sejumlah kandidat, dengan sifat-sifat tertentu yang dipunyai kandidat itu. Bahkan, seorang kandidat bisa ditonjolkan lebih mencolok dibanding dengan kandidat lain dalam sebuah media massa.
Dengan demikian, tak ada cara lain yang harus dilakukan oleh para kandidat dan para tim suksesnya kecuali dengan melihat dengan mata kepalanya akan kekuatan yang dipunyai media massa. Memainkan peran strategis media massa akan mendulang keberhasilan, sementara menjauhkan diri dari media massa berarti “kiamat”.
Mengapa? Saat ini adalah era media massa yang berbicara. Bahkan secara bombastis, Al dan Laura Ries dalam bukunya The Fall of Advertising and the Rise of PR (2003) pernah mengatakan, saat ini era periklanan sudah mati, yang muncul adalah era Public Relations (PR). Era PR modern adalah dengan memakai media relations (hubungan media) yang cerdas.
Ini tak berarti menganggap rendah faktor lain seperti kapasitas kepemimpinan, atau ikatan emosional dengan kandidat. Media bisa membentuk bagaimana citra kepemimpinan seorang kandidat ditampilkan. Artinya pula, apa yang kurang pada diri kandidat bisa ditutupi, dan dicitrakan secara baik lewat media massa. Karenanya, media massa mampu membentuk seperti apa sosok seorang gubernur Jatim mendatang.
Dalam kajian komunikasi massa, hal itu bisa dijelaskan dengan teori agenda setting. Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dalam tulisannya berjudul “The Agenda Setting Function of The Mass Media” menemukan bahwa ada hubungan yang tinggi antara penekanan berita dan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi khalayaknya. Artinya, apa yang terus diekspos media akan dianggap layak baca, tonton, dengar oleh masyarakat.
Media (khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang harus dipikir seseorang, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu seseorang apa yang harus dipikirkannya. Akibatnya, media massa selalu mengarahkan pada masyarakat apa yang harus mereka lakukan.
Media akan memberikan agenda-agenda lewat pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Menurut asumsi teori itu, media punya kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun mengatur apa yang harus kita lihat, tokoh siapa yang harus kita dukung dalam pemilihan.
Dengan demikian, apa yang menjadi agenda pembicaraan masyarakat, jelas dipengaruhi oleh agenda media massa. Karenanya, para kandidat akan memandang media punya kekuatan hebat sehingga dengan berbagai macam cara akan mereka lakukan. Dengan kata lain, di tahun 2008 ini, para kandidat berada di bawah “ketiak” media massa. Medialah yang akan bisa memuluskan keinginan dirinya untuk mencapai Jateng-1.
Strategi Media
Dengan demikian, para kandidat harus bisa memainkan peran media relations secara baik. Lalu apa yang bisa dilakukan kandidat?
Pertama, para calon harus bisa menjalin hubungan dekat dengan media massa. Ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke dapur redaksi media yang bersangkutan. Media, karena dikunjungi calon kepala daerah, ada kemungkinan besar untuk memberitakannya. Ini pulalah yang dahulu pernah dilakukan SBY dan Amien Rais untuk menyaingi kepopuleran Megawati karena kedudukannya sebagai presiden sudah menarik perhatian media massa.
Media yang dikunjungi kandidat tersebut biasanya akan menurunkan berita atau bahkan memuat foto kunjungan seorang kandidat. Disamping itu, sang kandidat juga bisa lebih dekat dengan para wartawan yang akan ikut menentukan bagaimana berita-berita seputar kandidat diframe (dibingkai).
Kedua, kandidat juga bisa sering-sering mengundang media massa dimana calon itu melakukan kegiatan politik seperti kampanye, pidato politik, kebijakan yang akan diputuskan. Bisa jadi media tanpa diundangpun ingin meliputnya, tetapi mengundang mereka bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua calon. Ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan kandidat bisa diketahui masyarakat. Paling tidak, masyarakat tahu bahwa “seseorang” itu calon kepala daerah.
Ketiga, sering membuat press release (siaran pers). Entah memang ada kebijakan atau keinginan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau hal lain. Tetapi yang jelas, calon kepala daerah tidak boleh “menyakiti” pers. Atau membuat pernyataan yang membuat jengkel wartawan. Sebab, begitu sang kandidat membuat “kesalahan” seperti itu kandidat mungkin tetap muncul di media massa tetapi dengan berita yang justru merugikan. Termasuk di sini, menghindari untuk mengatakan “no comment”. Pernyataan seperti itu jelas tidak disukai oleh wartawan. Seorang kandidat akan dicitrakan sebagai orang yang tertutup.
Tetapi ada satu hal lain yang harus dilakukan jika ia terpilih menjadi seorang kepala daerah yakni tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan. Umumnya, para politisi kita pada awalnya berhubungan baik dengan wartawan (ketika sedang mencari popularitas), tetapi ketika sudah “mapan” ia lupa bahkan menghindar dari wartawan. Biasanya, politisi itu takut karena “dosanya” diketahui umum.
Maka, menjaga hubungan baik dengan media massa tidak saja akan memuluskan langkah sang calon, tetapi juga akan menentukan “hidup matinya” kebijakan daerah yang akan dipimpinnya nanti.
Sudah saatnya, menempatkan media massa di depan dan bukan dipolitisir untuk tujuan yang mementingkan kepentingannya sendiri. Media massa punya mata dan telinga. Sang kandidat akan diberitakan baik manakala ia baik, tetapi akan diberitakan jelek jika sebaliknya. Jadi, saat ini hidup matinya calon kepala daerah sangat ditentukan oleh media massa, bukan? Readmore »»
McGinniss (1969) dalam The Selling of The President 1968 menyebutkan adanya kekuatan menentukan yang diperankan oleh media massa dalam pemilihan. Alasannya, media massa dalam praktiknya ikut menentukan pilihan seseorang setelah ikut membentuk, manipulasi citra yang dilakukan seorang kandidat. Terbukti, ada peningkatan jumlah pemilih secara drastis terhadap seorang kandidat setelah dipublikasi media massa.
Maka, media juga secara sengaja telah memainkan peran besar dalam menjadikan sejumlah kandidat, dengan sifat-sifat tertentu yang dipunyai kandidat itu. Bahkan, seorang kandidat bisa ditonjolkan lebih mencolok dibanding dengan kandidat lain dalam sebuah media massa.
Dengan demikian, tak ada cara lain yang harus dilakukan oleh para kandidat dan para tim suksesnya kecuali dengan melihat dengan mata kepalanya akan kekuatan yang dipunyai media massa. Memainkan peran strategis media massa akan mendulang keberhasilan, sementara menjauhkan diri dari media massa berarti “kiamat”.
Mengapa? Saat ini adalah era media massa yang berbicara. Bahkan secara bombastis, Al dan Laura Ries dalam bukunya The Fall of Advertising and the Rise of PR (2003) pernah mengatakan, saat ini era periklanan sudah mati, yang muncul adalah era Public Relations (PR). Era PR modern adalah dengan memakai media relations (hubungan media) yang cerdas.
Ini tak berarti menganggap rendah faktor lain seperti kapasitas kepemimpinan, atau ikatan emosional dengan kandidat. Media bisa membentuk bagaimana citra kepemimpinan seorang kandidat ditampilkan. Artinya pula, apa yang kurang pada diri kandidat bisa ditutupi, dan dicitrakan secara baik lewat media massa. Karenanya, media massa mampu membentuk seperti apa sosok seorang gubernur Jatim mendatang.
Dalam kajian komunikasi massa, hal itu bisa dijelaskan dengan teori agenda setting. Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dalam tulisannya berjudul “The Agenda Setting Function of The Mass Media” menemukan bahwa ada hubungan yang tinggi antara penekanan berita dan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih. Meningkatnya nilai penting suatu topik berita pada media massa menyebabkan meningkatnya nilai penting topik tersebut bagi khalayaknya. Artinya, apa yang terus diekspos media akan dianggap layak baca, tonton, dengar oleh masyarakat.
Media (khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang harus dipikir seseorang, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu seseorang apa yang harus dipikirkannya. Akibatnya, media massa selalu mengarahkan pada masyarakat apa yang harus mereka lakukan.
Media akan memberikan agenda-agenda lewat pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Menurut asumsi teori itu, media punya kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. Media pun mengatur apa yang harus kita lihat, tokoh siapa yang harus kita dukung dalam pemilihan.
Dengan demikian, apa yang menjadi agenda pembicaraan masyarakat, jelas dipengaruhi oleh agenda media massa. Karenanya, para kandidat akan memandang media punya kekuatan hebat sehingga dengan berbagai macam cara akan mereka lakukan. Dengan kata lain, di tahun 2008 ini, para kandidat berada di bawah “ketiak” media massa. Medialah yang akan bisa memuluskan keinginan dirinya untuk mencapai Jateng-1.
Strategi Media
Dengan demikian, para kandidat harus bisa memainkan peran media relations secara baik. Lalu apa yang bisa dilakukan kandidat?
Pertama, para calon harus bisa menjalin hubungan dekat dengan media massa. Ini bisa dilakukan dengan kunjungan ke dapur redaksi media yang bersangkutan. Media, karena dikunjungi calon kepala daerah, ada kemungkinan besar untuk memberitakannya. Ini pulalah yang dahulu pernah dilakukan SBY dan Amien Rais untuk menyaingi kepopuleran Megawati karena kedudukannya sebagai presiden sudah menarik perhatian media massa.
Media yang dikunjungi kandidat tersebut biasanya akan menurunkan berita atau bahkan memuat foto kunjungan seorang kandidat. Disamping itu, sang kandidat juga bisa lebih dekat dengan para wartawan yang akan ikut menentukan bagaimana berita-berita seputar kandidat diframe (dibingkai).
Kedua, kandidat juga bisa sering-sering mengundang media massa dimana calon itu melakukan kegiatan politik seperti kampanye, pidato politik, kebijakan yang akan diputuskan. Bisa jadi media tanpa diundangpun ingin meliputnya, tetapi mengundang mereka bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua calon. Ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan kandidat bisa diketahui masyarakat. Paling tidak, masyarakat tahu bahwa “seseorang” itu calon kepala daerah.
Ketiga, sering membuat press release (siaran pers). Entah memang ada kebijakan atau keinginan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau hal lain. Tetapi yang jelas, calon kepala daerah tidak boleh “menyakiti” pers. Atau membuat pernyataan yang membuat jengkel wartawan. Sebab, begitu sang kandidat membuat “kesalahan” seperti itu kandidat mungkin tetap muncul di media massa tetapi dengan berita yang justru merugikan. Termasuk di sini, menghindari untuk mengatakan “no comment”. Pernyataan seperti itu jelas tidak disukai oleh wartawan. Seorang kandidat akan dicitrakan sebagai orang yang tertutup.
Tetapi ada satu hal lain yang harus dilakukan jika ia terpilih menjadi seorang kepala daerah yakni tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan. Umumnya, para politisi kita pada awalnya berhubungan baik dengan wartawan (ketika sedang mencari popularitas), tetapi ketika sudah “mapan” ia lupa bahkan menghindar dari wartawan. Biasanya, politisi itu takut karena “dosanya” diketahui umum.
Maka, menjaga hubungan baik dengan media massa tidak saja akan memuluskan langkah sang calon, tetapi juga akan menentukan “hidup matinya” kebijakan daerah yang akan dipimpinnya nanti.
Sudah saatnya, menempatkan media massa di depan dan bukan dipolitisir untuk tujuan yang mementingkan kepentingannya sendiri. Media massa punya mata dan telinga. Sang kandidat akan diberitakan baik manakala ia baik, tetapi akan diberitakan jelek jika sebaliknya. Jadi, saat ini hidup matinya calon kepala daerah sangat ditentukan oleh media massa, bukan? Readmore »»
Media Massa dan Penanggulangan Bencana
Saat memberikan kuliah beberapa waktu lalu, saya ditanya seorang mahasiswa, “Apakah media massa bisa mengatasi bencana? Apakah tidak justru menakut-nakuti masyarakat?”.
Persuasi Media
Sebenarnya, diakui atau tidak, media massa (cetak dan elektronik) punya pengaruh kuat yang membekas dalam pikiran masyarakat. Bahkan bisa dikatakan, media massa punya kekuatan penuh untuk membentuk seperti apa masyarakat. Tidak itu saja, media juga bisa menentukan wajah seperti apa masyarakat di masa depan. Dengan kata lain, media massa berperan dalam memajukan sejarah peradaban manusia.
Asumsi tersebut juga berarti bahwa media massa berperan besar dalam memulihkan bencana alam (termasuk banjir yang melanda di kota Solo dan sekitarnya). Artinya, media langsung atau tidak, ikut ambil bagian dalam memulihkan trauma masyarakat, mengembalikan kondisi seperti semula atas banjir tersebut. Dengan kekuatannya media telah memberitakan bencana itu sampai usaha penggalangan dana.
Karena peran medialah kemudian masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan doa, tenaga dan materi. Lewat peristiwa yang memilukan tersebut seluruh komponen masyarakat menaruh perhatian besar terhadap bencana yang melanda di sebagian wilayah Indonesia itu. Tak hanya mahasiswa, tetapi juga pelajar, pengamen masyarakat umum ikut ambil bagian dalam penggalangan dana. Sungguh sebuah pemandangan yang menyentuh perasaan kita.
Setiap ada bencana alam atau lingkungan, yang sering menjadi perhatian masyarakat kita adalah jumlah bantuan dana yang tersalurkan ke lokasi bencana, sabotase bantuan, korupsi bantuan, dan bagaimana lambannya pemerintah memulihkan kondisi pasca bencana karena terlalu birokratis Tetapi, di luar itu semua, tidak banyak yang mengakui bahwa media massa berperan besar dalam membantu memulihkan kondisi akibat bencana.
Kekuatan Media Massa
Dalam merespon soal bencana alam, peran dan sumbangan media massa jelas dan nyata. Sebagai mana dikatakan oleh Harold D. Laswell (1948), media massa punya fungsi surveillance of the environment (pengawasan lingkungan). Pengawasan lingkungan ini beroperasi dalam dua cara yakni warning or beware surveillance (pengawasan peringatan) dan instrumental surveillance (pengawasan instrumental) (Nurudin, 2007).
Pengawasan peringatan wujud nyatanya adalah pemberitaan media massa tentang akan munculnya gejala bencana alam. Pemberitaan tentang banjir seringkali akan diikuti ulasan atau pendapat mengapa bencana itu bisa terjadi. Misalnya, saluran sungai tersumbat, penebangan pohon yang semakin liar, atau tiadanya peresapan air yang cukup di kota karena sudah diaspal dan banyaknya bangunan tanpa mengindahkan analisis dampak lingkungannya (AMDAL).
Dalam hal ini media massa justru berposisi sebagai alat preventif sejak awal. Ia telah memberikan pengawasan peringatan sebelum bencana alam terjadi. Kalau bencana akhirnya terjadi, media telah bertindak tidak saja memberikan bantuan dana (lewat dompet bencana yang dibuka di medianya) atau mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan, tetapi telah berupaya mencegah korban yang lebih dahsyat dengan usaha preventif sebelum munculnya bencana tersebut.
Sementara itu, pengawasan instrumental wujud kongkritnya adalah pemberitaan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Pemberitaan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat drastis akibat bencana, dimana masyarakat bisa mencari bantuan dana untuk membangun sarana pendidikan yang hancur masuk dalam fungsi pengawasan instrumental ini. Sementara itu pemberitaan semakin langkanya kebutuhan sehari-hari akibat bencana alam juga tak luput dari pelaksanaan fungsi media sebagai pengawasan instrumental ini.
Media Massa Telah Berbuat, Bagaimana Kita?
Disamping peristiwa bencana banjir itu memang mempunyai nilai berita (news value) tinggi, media telah mampu pula untuk menggerakkan masyarakat menaruh perhatian pada sebuah bencana.. Media telah menjadi sarana penghubung antara mereka yang terkena korban bencana dengan keluarga yang masih hidup. Buktinya, tak sedikit keluarga yang sudah mengetahui apakah anggota keluarganya masih hidup atau sudah meninggal, dan sebagainya.
Fakta kuat lain yang memperkuat bahwa media lewat fungsi pengawasannnya ikut menyelesaikan kasus itu adalah pemberitaan yang gencar dan dibukanya “dompet peduli gempa banjir” di beberapa media massa kita. Dalam waktu yang relatif singkat sudah banyak media yang dijadikan sarana untuk mengumpulkan bantuan. Ratusan juta bahkan sampai puluhan milyar pun sudah dikumpulkan.
Apa yang dilakukan media massa tersebut dampaknya sungguh terasa. Masyarakat bersatu padu untuk memberikan sumbangan. Mereka tidak mempedulikan perbedaan yang konflik kepentingan yang selama ini terjadi di tengah mereka. Rasa kemanusiaan telah melunturkan sikap ego masing-masing pihak untuk hanya mau menang sendiri.
Perhatian masyarakat saat ini tertuju ke bencana banjir. Ini sesuai pula dengan asumsi teori agenda setting (agenda setting theory). Bahwa agenda media (media agenda) akan mempengaruhi agenda masyarakat (public agenda). Agenda media akhir-akhir ini adalah musibah banjir dan tanah lonsor, maka agenda pembicaraan masyarakat juga tidak jauh dari masalah tersebut.
Tidak itu saja, agenda media juga mempengaruhi agenda kebijakan (policy agenda). Pemerintah mau tidak mau wajib mengeluarkan kebijakan baru yang berkaitan dengan alokasi bantuan dana untuk mengatasi korban bencana alam itu. Ini memperkuat bukti bahwa media telah memainkan peranan yang tidak sedikit dalam menyelesaikan bencana banjir dan tanah longsor.
Peran media tidak sebatas sampai di situ sebenarnya. Memang media telah mampu menghimbau masyarakat untuk memberikan bantuan. Tetapi, media masih punya tugas berat. Tugas itu adalah ikut mengawasi perbaikan infrastruktur di wilayah yang terkena bencana. Bukan tidak mustahil, perbaikan infrastruktur akan membuka peluang “tangan-tangan tersembunyi” (invisible hand) ikut bermain di dalamnya. Artinya, jangan sampai uang dan bantuan yang sudah terkumpul itu dikorupsi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.
Masalahnya, sejarah di negeri ini belum menunjukkan bahwa bantuan dana lepas dari “penyunatan” tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga LSM yang seringkali berteriak “atas nama” rakyat. Media massa punya tugas untuk terus mengawasinya. Media tidak saja menjadi anjing penjaga (watch dog), tetapi media harus berani membuka peluang bagi proses penegakan hukum akibat kecurangan dalam bantuan bencana tersebut. Tentu saja dengan tetap mengibarkan bendera anti trial by the press dan semangat jurnalisme all sides (meliput dari banyak sisi yang berbeda secara seimbang) dan adil.Media massa telah berbuat, bagaimana dengan kita? (pernah dipublikasikan harian Solo Pos, 2008) Readmore »»
Persuasi Media
Sebenarnya, diakui atau tidak, media massa (cetak dan elektronik) punya pengaruh kuat yang membekas dalam pikiran masyarakat. Bahkan bisa dikatakan, media massa punya kekuatan penuh untuk membentuk seperti apa masyarakat. Tidak itu saja, media juga bisa menentukan wajah seperti apa masyarakat di masa depan. Dengan kata lain, media massa berperan dalam memajukan sejarah peradaban manusia.
Asumsi tersebut juga berarti bahwa media massa berperan besar dalam memulihkan bencana alam (termasuk banjir yang melanda di kota Solo dan sekitarnya). Artinya, media langsung atau tidak, ikut ambil bagian dalam memulihkan trauma masyarakat, mengembalikan kondisi seperti semula atas banjir tersebut. Dengan kekuatannya media telah memberitakan bencana itu sampai usaha penggalangan dana.
Karena peran medialah kemudian masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan doa, tenaga dan materi. Lewat peristiwa yang memilukan tersebut seluruh komponen masyarakat menaruh perhatian besar terhadap bencana yang melanda di sebagian wilayah Indonesia itu. Tak hanya mahasiswa, tetapi juga pelajar, pengamen masyarakat umum ikut ambil bagian dalam penggalangan dana. Sungguh sebuah pemandangan yang menyentuh perasaan kita.
Setiap ada bencana alam atau lingkungan, yang sering menjadi perhatian masyarakat kita adalah jumlah bantuan dana yang tersalurkan ke lokasi bencana, sabotase bantuan, korupsi bantuan, dan bagaimana lambannya pemerintah memulihkan kondisi pasca bencana karena terlalu birokratis Tetapi, di luar itu semua, tidak banyak yang mengakui bahwa media massa berperan besar dalam membantu memulihkan kondisi akibat bencana.
Kekuatan Media Massa
Dalam merespon soal bencana alam, peran dan sumbangan media massa jelas dan nyata. Sebagai mana dikatakan oleh Harold D. Laswell (1948), media massa punya fungsi surveillance of the environment (pengawasan lingkungan). Pengawasan lingkungan ini beroperasi dalam dua cara yakni warning or beware surveillance (pengawasan peringatan) dan instrumental surveillance (pengawasan instrumental) (Nurudin, 2007).
Pengawasan peringatan wujud nyatanya adalah pemberitaan media massa tentang akan munculnya gejala bencana alam. Pemberitaan tentang banjir seringkali akan diikuti ulasan atau pendapat mengapa bencana itu bisa terjadi. Misalnya, saluran sungai tersumbat, penebangan pohon yang semakin liar, atau tiadanya peresapan air yang cukup di kota karena sudah diaspal dan banyaknya bangunan tanpa mengindahkan analisis dampak lingkungannya (AMDAL).
Dalam hal ini media massa justru berposisi sebagai alat preventif sejak awal. Ia telah memberikan pengawasan peringatan sebelum bencana alam terjadi. Kalau bencana akhirnya terjadi, media telah bertindak tidak saja memberikan bantuan dana (lewat dompet bencana yang dibuka di medianya) atau mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan, tetapi telah berupaya mencegah korban yang lebih dahsyat dengan usaha preventif sebelum munculnya bencana tersebut.
Sementara itu, pengawasan instrumental wujud kongkritnya adalah pemberitaan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Pemberitaan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat drastis akibat bencana, dimana masyarakat bisa mencari bantuan dana untuk membangun sarana pendidikan yang hancur masuk dalam fungsi pengawasan instrumental ini. Sementara itu pemberitaan semakin langkanya kebutuhan sehari-hari akibat bencana alam juga tak luput dari pelaksanaan fungsi media sebagai pengawasan instrumental ini.
Media Massa Telah Berbuat, Bagaimana Kita?
Disamping peristiwa bencana banjir itu memang mempunyai nilai berita (news value) tinggi, media telah mampu pula untuk menggerakkan masyarakat menaruh perhatian pada sebuah bencana.. Media telah menjadi sarana penghubung antara mereka yang terkena korban bencana dengan keluarga yang masih hidup. Buktinya, tak sedikit keluarga yang sudah mengetahui apakah anggota keluarganya masih hidup atau sudah meninggal, dan sebagainya.
Fakta kuat lain yang memperkuat bahwa media lewat fungsi pengawasannnya ikut menyelesaikan kasus itu adalah pemberitaan yang gencar dan dibukanya “dompet peduli gempa banjir” di beberapa media massa kita. Dalam waktu yang relatif singkat sudah banyak media yang dijadikan sarana untuk mengumpulkan bantuan. Ratusan juta bahkan sampai puluhan milyar pun sudah dikumpulkan.
Apa yang dilakukan media massa tersebut dampaknya sungguh terasa. Masyarakat bersatu padu untuk memberikan sumbangan. Mereka tidak mempedulikan perbedaan yang konflik kepentingan yang selama ini terjadi di tengah mereka. Rasa kemanusiaan telah melunturkan sikap ego masing-masing pihak untuk hanya mau menang sendiri.
Perhatian masyarakat saat ini tertuju ke bencana banjir. Ini sesuai pula dengan asumsi teori agenda setting (agenda setting theory). Bahwa agenda media (media agenda) akan mempengaruhi agenda masyarakat (public agenda). Agenda media akhir-akhir ini adalah musibah banjir dan tanah lonsor, maka agenda pembicaraan masyarakat juga tidak jauh dari masalah tersebut.
Tidak itu saja, agenda media juga mempengaruhi agenda kebijakan (policy agenda). Pemerintah mau tidak mau wajib mengeluarkan kebijakan baru yang berkaitan dengan alokasi bantuan dana untuk mengatasi korban bencana alam itu. Ini memperkuat bukti bahwa media telah memainkan peranan yang tidak sedikit dalam menyelesaikan bencana banjir dan tanah longsor.
Peran media tidak sebatas sampai di situ sebenarnya. Memang media telah mampu menghimbau masyarakat untuk memberikan bantuan. Tetapi, media masih punya tugas berat. Tugas itu adalah ikut mengawasi perbaikan infrastruktur di wilayah yang terkena bencana. Bukan tidak mustahil, perbaikan infrastruktur akan membuka peluang “tangan-tangan tersembunyi” (invisible hand) ikut bermain di dalamnya. Artinya, jangan sampai uang dan bantuan yang sudah terkumpul itu dikorupsi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.
Masalahnya, sejarah di negeri ini belum menunjukkan bahwa bantuan dana lepas dari “penyunatan” tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga LSM yang seringkali berteriak “atas nama” rakyat. Media massa punya tugas untuk terus mengawasinya. Media tidak saja menjadi anjing penjaga (watch dog), tetapi media harus berani membuka peluang bagi proses penegakan hukum akibat kecurangan dalam bantuan bencana tersebut. Tentu saja dengan tetap mengibarkan bendera anti trial by the press dan semangat jurnalisme all sides (meliput dari banyak sisi yang berbeda secara seimbang) dan adil.Media massa telah berbuat, bagaimana dengan kita? (pernah dipublikasikan harian Solo Pos, 2008) Readmore »»
Ketika “Kambing Hitam” Kekerasan Milik Pers
KEKERASAN yang dimaksud dalam tulisan ini tidak hanya kekerasan dalam arti fisik dan langsung seperti memukul, merobek, menembak, membakar, melukai, membom, memperkosa, melakukan kerusuhan dan konflik sosial lainnya. Tetapi, kekerasan di sini harus juga meliputi kekerasan kultural dan struktural yang pernah dikemukakan oleh Johan Galtung, Direktur Trascend Peace and Development Network.
Kekerasan yang tergolong kultural antara lain adalah tulisan yang menuturkan kebencian, xenophobia/kebencian terhadap orang asing, kompleks penyiksaan/ persecution complex, mitos dan legenda, pahlawan perang, agama sebagai pembenaran untuk berperang dan perasaan sebagai “kelompok terpilih”. Sedangkan kekerasan struktural meliputi kemiskinan, sistem yang berdasar, eksploitasi, kesenjangan pemilikan materi secara mencolok, aphartheid, kolonialisme, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pengasingan dan represi politik, serta situasi yang membuat orang terpisah walaupun mereka ingin tetap berkumpul.
Sedangkan media massa dalam hal ini mencakup pengertian luas yakni meliputi media cetak dan elektronik. Meskipun media massa secara sempit hanya berarti media cetak. Dengan demikian, apa yang kita perbincangkan dalam tulisan ini meliputi apa yang bisa disaksikan, didengar atau dibaca lewat berbagai sarana media massa.
Karena media massa produknya adalah berupa audio visual, tulisan/ foto, dan audio maka pembahasan ini juga mencakup hal tersebut. Dengan kata lain, tulisan yang bisa menuturkan kebencian sudah masuk dalam wilayah kekerasan. Tak terkecuali dengan gambar/foto atau suara yang didengar lewat radio.
Demikian juga aktualisasi yang bisa menimbulkan kekerasan; fisik, kultural atau struktural. Penilaian sepihak menganggap bahwa media massa (cetak dan elektronik) tidak ikut andil dalam menyulut tindak kekerasan, adalah tindakan yang terburu-buru. Tetapi menjadikan media sebagai satu-satunya alat yang membakar kemarahan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kita perlu mendudukkan media secara wajar dan menilainya secara adil pula.
Penyebabnya adalah, selama ini ketika media dianggap turut menyulut tindak kekerasan di masyarakat; publik mereaksinya dengan ekspresi yang beragam: mengkritik, memberi masukan, menyudutkan sampai menghujatnya. Sebaliknya, sangatlah sedikit orang yang menganggap bahwa media juga ikut mempertinggi derajat kemanusiaan, membuat cerdas masyarakat dan mendorong kemajuan peradaban masyarakat.
Tuduhan bahwa media punya andil dalam menyulut kekerasan tidaklah salah. Tetapi menjadikan media satu-satunya penyulut kekerasan tidak sepenuhnya benar. Sebab sebenamya, media juga punya potensi ikut mendinginkan suasana "panas" di masyarakat. Media adalah agen. Dengan demikian, media massa adalah salah satu di antara pihak yang ikut menyulut, sekaligus mendinginkan suasana politik atau kecenderungan masyarakat pada tindak kekerasan. Sedangkan faktor di luar itu (yang ikut punya andil menyulut kekerasan) ada kemajemukan masyarakat, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), peran pemerintah, provokator, aktor intelektual dan lain-lain.
Memasuki masa kebebasan pers pasca Orde Baru, kecenderungan media massa ikut menyulut kekerasan semakin transparan. Keadaan itu juga memunculkan kecenderungan media untuk berperilaku menurut keinginannya sendiri, lepas dari keinginan masyarakat. Media akhimya lebih memilih apa yang dibutuhkan masyarakat (what's the people need) dan bukan pada apa yang masyarakat inginkan (what's the people want). Masyarakat membutuhkan hiburan atau informasi lain yang mengarah pada pemuasan kebutuhannya. Sementara itu kodrat masyarakat juga menginginkan suasana tenteram, damai, harmonis dan tanpa konflik.
Hidup tidaknya media akhirnya sangat ditentukan oleh masyarakat. Dampaknya, media akan memformat apa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan informasi politik di era kebebasan dan reformasi, media politik banyak bermunculan. Tetapi kemudian, banyak media “tiarap” pelan-pelan ketika masyarakat sudah “bosan” dengan persoalan politik. Kemudian beberapa media politik atau media baru memformat diri atau memfokuskan pada "eksploitasi" seks.
Fenomena semacam itu, merupakan satu bukti di mana media massa hanya menuruti keinginan "pasar" tanpa mengindahkan nilai-nilai sosial masyarakat yang seharusnya juga harus dikedepankan.
Kasus-kasus di mana media massa hanya menuruti kehendak pasar inilah yang kemudian dijadikan legitimasi masyarakat bahwa media massa tidak lepas dari katalisator munculnya kekerasan di masyarakat. Menurut analisis Freudian, pada diri manusia punya potensi untuk hidup dan mati. jika pendapat ini kita teruskan, maka pada diri manusia mempunyai potensi untuk bertindak amoral, kekerasan sekaligus untuk bertindak baik.
Media dan Tindak Kekerasan
Tak bisa dipungkiri pengaruh media dalam mengubah dan perilaku masyarakatnya juga berkorelasi erat dalam kasus munculnya kekerasan selama ini. Paling tidak bisa diidentifikasi sebab-sebab sebagai berikut;
Pertama, bias yang terjadi dalam pola liputan. Seperti diketahui, peristiwa yang terjadi dilapangan itu direkam oleh seorang wartawan, kemudian diolah di "otaknya" lalu ditulis dalam media massa. Dari proses pengamatan peristiwa yang terjadi di lapangan sampai munculnya pemberitaan itulah berbagai referensi dan persepsi wartawan akan ikut menentukan seperti apa berita dikonstruksikan.
Sama-sama meliput konflik yang ada di Maluku, masing-masing orang berbeda dalam mengkonstruk sebuah berita. Apalagi sistem media yang bersangkutan juga ikut menentukan aktualisasi apa yang dituangkan seorang wartawan.
Sama-sama meliput daerah konflik, media yang berafiliasi pada Islam dengan media independen atau media non Islam jelas akan berbeda nuansa pemberitaannya. Penelitian yang dilakukan Agus Sudibyo, dkk. (2001) terhadap empat media cetak nasional yakni Kompas, Suara Pembaruan, Media Dakwah dan Republika pada kasus Konflik di Maluku, Bentrok di Katapang, Kerusuhan Kupang dan Pengeboman masjid Istiqlal menunjukkan perbedaan. (Konflik di Maluku, misalnya, yang melibatkan orang Islam dan Kristen akan disikapi berlainan oleh masing-masing media cetak tersebut.
Meskipun berbeda dalam aktualisasi di media masing-masing, penelitian itu mengatakan ada persamaan nuansa dalam peliputannya. Yakni munculnya prasangka (prejudice) yang berlebihan dari media massa terhadap kasus konflik tersebut. Koran Islam akan cenderung mengungkapkan korban yang berada di pihak kaum Muslimin dan menganggap kalangan non Islam menjadi pihak yang bertanggung jawab, tanpa mau tahu berapa pula jumlah korban yang diakibatkan oleh umat Islam sendiri.
Dengan meneliti Medan Wacana (Apa yang Terjadi), Penyampaian Wacana (Siapa yang Berbicara), Mode Wacana (Peran Bahasa yang Digunakan), terungkap adanya prasangka itu. Sehubungan dengan Mode Wacana yang dikembangkan oleh masing-masing media penuh dengan pilihan kata yang sangat tendensius, sebagai contoh, caption photo yang digunakan sebagai berikut; "Korban pembantaian terhadap umat Islam di Tobelo. Setelah Jantungnya Diambil"; "Korban Pembantaian Terhadap Umat Islam Dibakar Hidup-hidup di dalam Masjid Al Ikhlas di Desa Togolia Kecamatan Tobelo"; "Muslimah pun jadi korban Kesadisan Kristen Tobelo".
Termasuk pula pilihan kata antara lain; cincang, seret, bantai, gantung dan sejenisnya; menunjukkan betapa media punya andil dalam menciptakan kecenderungan memancing sikap dan perilaku kekerasan pada sebuah kelompok tertentu di masyarakat. Tak terkecuali pilihan kata yang disiarkan televisi, misalnya: "Kau aja Don, makan tu sop. Biar badan lu kaya' Kingkong" (Warkop Millenium, Indosiar, 3/6/01), "Kemarin kambing saya melahirkan. Anaknya mirip dia!" (Ketoprak Humor, RCTI, 9/6/01).
Simak juga pilihan judul yang dilakukan oleh sebuah harian di Jakarta, "Dia juga Presiden Provokator" (22/4/01), “Alvin lie itu Mickey Mouse" (24/4/01), "Lopa Mabuk Jabatan" (28/4/01), "Maklumat = Maklum Sudah Mau Tamat" (30/5/0 1) dan lain-lain.
Kedua, kebijakan media yang bersangkutan. Di samping akan mempengaruhi bagaimana wartawan menuang berita, ia juga berkait dengan kebijakan umum yang dilakukan. Kesuksesan Layar Emas yang pemah ditayangkan RCTI yang penuh adegan kekerasan dan berhasil meraup iklan, menimbulkan keinginan stasiun yang lain untuk memunculkan film serupa. Muncullah acara lain yang serupa. Bahkan RCTI sendiri pernah menayangkan Layar Emas tiga kali seminggu.
Contoh perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak setelah menonton sinetron Joshua juga membuktikan itu semua. Tak lain karena adanya orientasi media yang lebih mementingkan pasar ketimbang orientasi ideal. Meskipun dalam beberapa hal ini harus dimaklumi. Tetapi apakah nanti media mau bertanggung jawab seandainya keterpurukan di masyarakat terjadi yang secara langsung juga diakibatkan oleh apa yang disiarkan media massa? Sebab, ada kecenderungan pihak media untuk berkilah terhadap kenyataan ini.
Ketiga, pencampuradukkan antara fakta dan opini. Tak bisa dipungkiri sebuah ulasan penting dilakukan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah berita (cetak khususnya). Namun, jika hal itu dilakukan secara berlebihan jelas akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Inginnya memberitahukan kepada khalayak kalau terjadi sebuah peristiwa. Tetapi secara tidak langsung justru menggiring pembaca untuk bertindak sesuatu.
Ini akan mengakibatkan munculnya penokohan (profiling) yang berlebihan. Masalahnya, penokohan yang berhubungan dengan fisik sering menimbulkan masalah. Penokohan fisik misalnya bibir sensual, tubuh sintal, montok, mata nakal. Sedangkan penokohan non fisik lain misalnya ia adalah guru, seorang bapak, ketua RT dan sebagainya.
Menyebutkan korban perkosaan bertubuh sintal, montok, berparas cantik, wama kulit kuning seolah ingin mempersepsikan kepada pembaca bahwa karena cantiklah wanita itu diperkosa. Perkosaan ini memperoleh pembenaran bahwa faktor utama terjadinya peristiwa itu ada pada wanita. Padahal ada juga lelaki yang nafsunya tidak kalah "beringas". Atau justru wanita itu memang punya hobby diperkosa?
Tragisnya, jika penokohan tersebut dilakukan untuk meliput sebuah kejadian yang berhubungan dengan suku, etnis, ideologi dan agama seperti tindak kekerasan atau konflik masyarakat yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso, Sambas dan daerah lain. jelas ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat akan sebuah kejadian. Peliputan yang berat sebelah dalam membela suku Dayak pada konflik Sambas tentu akan menanamkan bibit “dendam” bagi masyarakat Madura terhadap suku Dayak dan sebaliknya.
Keempat, belum dihilangkannya trial by the press. Istilah ini juga bisa disebut opini atau klaim seolah-olah sudah pasti (sebelum adanya kepastian putusan pengadilan) Misalnya, "Eurico Gutteres disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Timor-Timur.” Jelas ini bisa diklaim sebagai penghakiman media pada seseorang secara pasti. Mengapa tidak disebutkan siapa sumber yang mengatakan itu? Misalnya pejabat tinggi di Timor-Timur mengatakan hal itu. Klaim seperti ini (sebelum ada pemutusan pengadilan salah tidaknya Gutteres) akan menimbulkan kemarahan massanya. Dikhawatirkan media ikut dituduh memanas-manasi situasi. Bukankah media punya andil dalam menciptakan kekerasan? Tak terkecuali dengan katakata “perusuh Aceh”, "Preman Yogya". Seolah Aceh adalah sarang perusuh sehingga setiap ada kerusuhan akan dikaitkan dengan Aceh. Atau setiap ada kejadian yang berhubungan dengan preman akan menuduh Yogya sebagai biang keladinya. Padahal dua daerah tersebut nyaris tidak seperti digambarkan di atas.
Upaya Minimalisasi
Kekerasan memang sulit dihapuskan. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkannya. Jika kita sepakat bahwa media massa ikut andil dalam menyulut tindak kekerasan di masyarakat, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk menguranginya: pertama meskipun terbilang klasik, jurnalisme cover both sides (meliputi dua sisi yang berbeda secara seimbang) dan peliputan secara adil masih menjadi salah satu cara yang baik.
Aktualisasinya, jika terjadi konflik atau tindak kekerasan media tidak boleh membela satu pihak secara tidak seimbang, meskipun hal demikian masih relatif sifatnya. Sedangkan keadilan, media harus menampilkan sumber berita yang sepadan. Misalnya, ketika ada dua etnis yang terlibat konflik, jika jurnalis mewawancarai pimpinan salah satu pihak, pimpinan pihak lain juga harus diwawancari. Termasuk, keadilan yang dilihat dari jenis tulisan yang disajikan. Ini baru adil. Tak bisa dipungkiri, kebebasan pers yang sedang dinikmati di Indonesia saat ini memang bagai sebuah anugerah terindah yang selama ini diidam-idamkan, setelah sebelumnya dikekang dalam jangka waktu lama. Sebelumnya, peristiwa konflik di dacrah Indonesia seperti Aceh, Maluku, Ambon nyaris tidak boleh diberitakan. Saat ini, daerah tersebut bagai "selebritis" yang tak lepas dari pengamatan pers.
Kesulitan yang kadang dihadapi oleh para jumalis adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber dari dua belah pihak secara adil. Oleh karena itu, apa boleh buat terkadang media hanya bisa merekam pemberitaan konflik Maluku dari satu sisi saja. Keputusan ini terpaksa diambil mengingat tidak semua nara sumber mau diwawancarai. Padahal jurnalis hanya ingin melakukan konfirmasi sehubungan dengan berita yang berat sebelah atau data-data mentah yang didapat di lapangan.
Ketidakseimbankan yang terpaksa diambil inilah pada akhirnya membuat masyarakat marah, menuding media hanya mau menang sendiri. Padahal tak kalah sulitnya dengan mengatasi konflik itu sendiri.
Kedua, memupuk pelaksanaan jurnalisme damai (peace journalism). Ia secara sadar mengadopsi agenda perdamaian, bukan perang. Jurnalisme damai mencoba memetakan konflik pra kekerasan, mengidentifikasi banyak pihak dan berbagai penyebab, sehingga membuka jalan bagi dialog untuk menciptakan perdamaian. jurnalisme perdamaian ini memanusiawikan seluruh isi konflik dan berupaya mendokumentasikan berbagai kepalsuan dan penderitaan dan juga memprakarsai perdamaian (Lukas Luwarso dkk., 2000). Jurnalisme perdamaian mempunyai tugas utama yakni memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menganalisis tujuan-tujuan mereka dan memberikan informasi yang mereka sediakan dalam agenda khusus mereka (Zain Hae, 2000).
Tetapi jurnalisme damai hanya bisa terwujud paling tidak dengan syarat; wartawan yang tangguh dalam menegakkan kode etik dan memiliki wawasan memadai menyangkut masalah yang diliput; media pers yang serius, yang tidak mementingkan bisnis dan politis dan bukan wartawan yang hanya mengedepankan sensasi, dramatisasi dan meliput konflik serta tindak kekerasan hanya untuk kepentingan bisnis. Jurnalisme damai ini juga secara otomatis akan mengurangi dampak kekerasan di masyarakat. Sebab, tak bisa dipungkiri kekerasan juga bisa dipicu oleh media massa.
Ketiga, memberikan ruang gerak yang bebas kepada wartawan untuk meliput tanpa ketertekanan. Ini juga masih dilematis. Sebab, masa efouria memberi kecenderungan jumalis meliput apa saja dan di mana saja serta pada siapa saja. Kondisi ini akan memunculkan sikap mau menang se'ndiri dalam meliput suatu kejadian.
Tidak adanya keleluasaan tentu tidak akan memberikan ruang gerak jurnalis untuk meliput. Tak terkecuali jika ini didukung oleh pelitnya nara sumber ketika dimintai komentar. Padahal bisa jadi komentarnya itu untuk menyeimbangkan data yang sudah didapat oleh wartawan. Dan bisa jadi sebagai sarana untuk konfirmasi tentang data yang didapat di lapangan. Kalau sudah begini, karena tuntutan teknis, maka tak ada jalan lain, kecuali harus mengirimkan berita apa adanya kepada redaktur. Beruntung kalau redaktur tetap meminta keseimbangan berita, kalau tidak?
Keempat, meskipun sangat relatif, self cencorship (sensor diri) menjadi jaminan pula agar kekerasan tidak melebar. Ini bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: apakah apa yang diberitakan nanti akan menyulut kemarahan publik? Apakah yang akan diberitakan sudah seimbang dan tidak memanas-manasi situasi? Apakah berita yang akan disajikan tidak membahayakan moral publik? Apakah berita ini tidak semata hanya sensasi tetapi sudah selayaknya demikian faktanya? Apakah kami tidak punya kepentingan terselubung atas pemuatan berita tersebut? jika jawabannya ya, maka media yang bersangkutan telah melakukan sensor diri.
Kelima, dilakukan social punishment (hukuman sosial) pada media. Jika kita menganggap sebuah media massa hanya memprovokasi agar tejadi tindak kekerasan mengapa tidak "diboikot" saja? Tidak membaca media itu adalah salah satu tindakan melakukan hukuman sosial. Masalahnya, tidak semua orang sadar dan mau untuk melakukannya.
Jika seseorang mengkritik banyak media massa yang "mengumbar" jumalisme pornografi lewat foto, gambar atau tulisan yang memancing asosasi pembacanya pada seks, tetapi ia membaca bahkan berlangganan atau menonton acaranya, berarti tidak ada konsistensi antara apa yang diucapkan dengan perilakunya.
Apa yang disajikan dalam tulisan ini jelas tidak mudah untuk dilakukan. Semua juga tergantung tidak hanya pada media saja, tetapi juga kedewasaan masyarakat. Tak terkecuali dengan sikap pemerintahnya. Pelarangan oleh pemerintah justru akan semakin membuat media "garang". Diktum, "Semakin diarang semakin dilanggar" akan membuktikan itu semua. (tulisan ini pernah dimuat majalah Visi Fisip UNS, Solo, 2003) Readmore »»
Kekerasan yang tergolong kultural antara lain adalah tulisan yang menuturkan kebencian, xenophobia/kebencian terhadap orang asing, kompleks penyiksaan/ persecution complex, mitos dan legenda, pahlawan perang, agama sebagai pembenaran untuk berperang dan perasaan sebagai “kelompok terpilih”. Sedangkan kekerasan struktural meliputi kemiskinan, sistem yang berdasar, eksploitasi, kesenjangan pemilikan materi secara mencolok, aphartheid, kolonialisme, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pengasingan dan represi politik, serta situasi yang membuat orang terpisah walaupun mereka ingin tetap berkumpul.
Sedangkan media massa dalam hal ini mencakup pengertian luas yakni meliputi media cetak dan elektronik. Meskipun media massa secara sempit hanya berarti media cetak. Dengan demikian, apa yang kita perbincangkan dalam tulisan ini meliputi apa yang bisa disaksikan, didengar atau dibaca lewat berbagai sarana media massa.
Karena media massa produknya adalah berupa audio visual, tulisan/ foto, dan audio maka pembahasan ini juga mencakup hal tersebut. Dengan kata lain, tulisan yang bisa menuturkan kebencian sudah masuk dalam wilayah kekerasan. Tak terkecuali dengan gambar/foto atau suara yang didengar lewat radio.
Demikian juga aktualisasi yang bisa menimbulkan kekerasan; fisik, kultural atau struktural. Penilaian sepihak menganggap bahwa media massa (cetak dan elektronik) tidak ikut andil dalam menyulut tindak kekerasan, adalah tindakan yang terburu-buru. Tetapi menjadikan media sebagai satu-satunya alat yang membakar kemarahan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kita perlu mendudukkan media secara wajar dan menilainya secara adil pula.
Penyebabnya adalah, selama ini ketika media dianggap turut menyulut tindak kekerasan di masyarakat; publik mereaksinya dengan ekspresi yang beragam: mengkritik, memberi masukan, menyudutkan sampai menghujatnya. Sebaliknya, sangatlah sedikit orang yang menganggap bahwa media juga ikut mempertinggi derajat kemanusiaan, membuat cerdas masyarakat dan mendorong kemajuan peradaban masyarakat.
Tuduhan bahwa media punya andil dalam menyulut kekerasan tidaklah salah. Tetapi menjadikan media satu-satunya penyulut kekerasan tidak sepenuhnya benar. Sebab sebenamya, media juga punya potensi ikut mendinginkan suasana "panas" di masyarakat. Media adalah agen. Dengan demikian, media massa adalah salah satu di antara pihak yang ikut menyulut, sekaligus mendinginkan suasana politik atau kecenderungan masyarakat pada tindak kekerasan. Sedangkan faktor di luar itu (yang ikut punya andil menyulut kekerasan) ada kemajemukan masyarakat, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), peran pemerintah, provokator, aktor intelektual dan lain-lain.
Memasuki masa kebebasan pers pasca Orde Baru, kecenderungan media massa ikut menyulut kekerasan semakin transparan. Keadaan itu juga memunculkan kecenderungan media untuk berperilaku menurut keinginannya sendiri, lepas dari keinginan masyarakat. Media akhimya lebih memilih apa yang dibutuhkan masyarakat (what's the people need) dan bukan pada apa yang masyarakat inginkan (what's the people want). Masyarakat membutuhkan hiburan atau informasi lain yang mengarah pada pemuasan kebutuhannya. Sementara itu kodrat masyarakat juga menginginkan suasana tenteram, damai, harmonis dan tanpa konflik.
Hidup tidaknya media akhirnya sangat ditentukan oleh masyarakat. Dampaknya, media akan memformat apa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan informasi politik di era kebebasan dan reformasi, media politik banyak bermunculan. Tetapi kemudian, banyak media “tiarap” pelan-pelan ketika masyarakat sudah “bosan” dengan persoalan politik. Kemudian beberapa media politik atau media baru memformat diri atau memfokuskan pada "eksploitasi" seks.
Fenomena semacam itu, merupakan satu bukti di mana media massa hanya menuruti keinginan "pasar" tanpa mengindahkan nilai-nilai sosial masyarakat yang seharusnya juga harus dikedepankan.
Kasus-kasus di mana media massa hanya menuruti kehendak pasar inilah yang kemudian dijadikan legitimasi masyarakat bahwa media massa tidak lepas dari katalisator munculnya kekerasan di masyarakat. Menurut analisis Freudian, pada diri manusia punya potensi untuk hidup dan mati. jika pendapat ini kita teruskan, maka pada diri manusia mempunyai potensi untuk bertindak amoral, kekerasan sekaligus untuk bertindak baik.
Media dan Tindak Kekerasan
Tak bisa dipungkiri pengaruh media dalam mengubah dan perilaku masyarakatnya juga berkorelasi erat dalam kasus munculnya kekerasan selama ini. Paling tidak bisa diidentifikasi sebab-sebab sebagai berikut;
Pertama, bias yang terjadi dalam pola liputan. Seperti diketahui, peristiwa yang terjadi dilapangan itu direkam oleh seorang wartawan, kemudian diolah di "otaknya" lalu ditulis dalam media massa. Dari proses pengamatan peristiwa yang terjadi di lapangan sampai munculnya pemberitaan itulah berbagai referensi dan persepsi wartawan akan ikut menentukan seperti apa berita dikonstruksikan.
Sama-sama meliput konflik yang ada di Maluku, masing-masing orang berbeda dalam mengkonstruk sebuah berita. Apalagi sistem media yang bersangkutan juga ikut menentukan aktualisasi apa yang dituangkan seorang wartawan.
Sama-sama meliput daerah konflik, media yang berafiliasi pada Islam dengan media independen atau media non Islam jelas akan berbeda nuansa pemberitaannya. Penelitian yang dilakukan Agus Sudibyo, dkk. (2001) terhadap empat media cetak nasional yakni Kompas, Suara Pembaruan, Media Dakwah dan Republika pada kasus Konflik di Maluku, Bentrok di Katapang, Kerusuhan Kupang dan Pengeboman masjid Istiqlal menunjukkan perbedaan. (Konflik di Maluku, misalnya, yang melibatkan orang Islam dan Kristen akan disikapi berlainan oleh masing-masing media cetak tersebut.
Meskipun berbeda dalam aktualisasi di media masing-masing, penelitian itu mengatakan ada persamaan nuansa dalam peliputannya. Yakni munculnya prasangka (prejudice) yang berlebihan dari media massa terhadap kasus konflik tersebut. Koran Islam akan cenderung mengungkapkan korban yang berada di pihak kaum Muslimin dan menganggap kalangan non Islam menjadi pihak yang bertanggung jawab, tanpa mau tahu berapa pula jumlah korban yang diakibatkan oleh umat Islam sendiri.
Dengan meneliti Medan Wacana (Apa yang Terjadi), Penyampaian Wacana (Siapa yang Berbicara), Mode Wacana (Peran Bahasa yang Digunakan), terungkap adanya prasangka itu. Sehubungan dengan Mode Wacana yang dikembangkan oleh masing-masing media penuh dengan pilihan kata yang sangat tendensius, sebagai contoh, caption photo yang digunakan sebagai berikut; "Korban pembantaian terhadap umat Islam di Tobelo. Setelah Jantungnya Diambil"; "Korban Pembantaian Terhadap Umat Islam Dibakar Hidup-hidup di dalam Masjid Al Ikhlas di Desa Togolia Kecamatan Tobelo"; "Muslimah pun jadi korban Kesadisan Kristen Tobelo".
Termasuk pula pilihan kata antara lain; cincang, seret, bantai, gantung dan sejenisnya; menunjukkan betapa media punya andil dalam menciptakan kecenderungan memancing sikap dan perilaku kekerasan pada sebuah kelompok tertentu di masyarakat. Tak terkecuali pilihan kata yang disiarkan televisi, misalnya: "Kau aja Don, makan tu sop. Biar badan lu kaya' Kingkong" (Warkop Millenium, Indosiar, 3/6/01), "Kemarin kambing saya melahirkan. Anaknya mirip dia!" (Ketoprak Humor, RCTI, 9/6/01).
Simak juga pilihan judul yang dilakukan oleh sebuah harian di Jakarta, "Dia juga Presiden Provokator" (22/4/01), “Alvin lie itu Mickey Mouse" (24/4/01), "Lopa Mabuk Jabatan" (28/4/01), "Maklumat = Maklum Sudah Mau Tamat" (30/5/0 1) dan lain-lain.
Kedua, kebijakan media yang bersangkutan. Di samping akan mempengaruhi bagaimana wartawan menuang berita, ia juga berkait dengan kebijakan umum yang dilakukan. Kesuksesan Layar Emas yang pemah ditayangkan RCTI yang penuh adegan kekerasan dan berhasil meraup iklan, menimbulkan keinginan stasiun yang lain untuk memunculkan film serupa. Muncullah acara lain yang serupa. Bahkan RCTI sendiri pernah menayangkan Layar Emas tiga kali seminggu.
Contoh perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak setelah menonton sinetron Joshua juga membuktikan itu semua. Tak lain karena adanya orientasi media yang lebih mementingkan pasar ketimbang orientasi ideal. Meskipun dalam beberapa hal ini harus dimaklumi. Tetapi apakah nanti media mau bertanggung jawab seandainya keterpurukan di masyarakat terjadi yang secara langsung juga diakibatkan oleh apa yang disiarkan media massa? Sebab, ada kecenderungan pihak media untuk berkilah terhadap kenyataan ini.
Ketiga, pencampuradukkan antara fakta dan opini. Tak bisa dipungkiri sebuah ulasan penting dilakukan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah berita (cetak khususnya). Namun, jika hal itu dilakukan secara berlebihan jelas akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Inginnya memberitahukan kepada khalayak kalau terjadi sebuah peristiwa. Tetapi secara tidak langsung justru menggiring pembaca untuk bertindak sesuatu.
Ini akan mengakibatkan munculnya penokohan (profiling) yang berlebihan. Masalahnya, penokohan yang berhubungan dengan fisik sering menimbulkan masalah. Penokohan fisik misalnya bibir sensual, tubuh sintal, montok, mata nakal. Sedangkan penokohan non fisik lain misalnya ia adalah guru, seorang bapak, ketua RT dan sebagainya.
Menyebutkan korban perkosaan bertubuh sintal, montok, berparas cantik, wama kulit kuning seolah ingin mempersepsikan kepada pembaca bahwa karena cantiklah wanita itu diperkosa. Perkosaan ini memperoleh pembenaran bahwa faktor utama terjadinya peristiwa itu ada pada wanita. Padahal ada juga lelaki yang nafsunya tidak kalah "beringas". Atau justru wanita itu memang punya hobby diperkosa?
Tragisnya, jika penokohan tersebut dilakukan untuk meliput sebuah kejadian yang berhubungan dengan suku, etnis, ideologi dan agama seperti tindak kekerasan atau konflik masyarakat yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso, Sambas dan daerah lain. jelas ini akan mempengaruhi penilaian masyarakat akan sebuah kejadian. Peliputan yang berat sebelah dalam membela suku Dayak pada konflik Sambas tentu akan menanamkan bibit “dendam” bagi masyarakat Madura terhadap suku Dayak dan sebaliknya.
Keempat, belum dihilangkannya trial by the press. Istilah ini juga bisa disebut opini atau klaim seolah-olah sudah pasti (sebelum adanya kepastian putusan pengadilan) Misalnya, "Eurico Gutteres disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal di Timor-Timur.” Jelas ini bisa diklaim sebagai penghakiman media pada seseorang secara pasti. Mengapa tidak disebutkan siapa sumber yang mengatakan itu? Misalnya pejabat tinggi di Timor-Timur mengatakan hal itu. Klaim seperti ini (sebelum ada pemutusan pengadilan salah tidaknya Gutteres) akan menimbulkan kemarahan massanya. Dikhawatirkan media ikut dituduh memanas-manasi situasi. Bukankah media punya andil dalam menciptakan kekerasan? Tak terkecuali dengan katakata “perusuh Aceh”, "Preman Yogya". Seolah Aceh adalah sarang perusuh sehingga setiap ada kerusuhan akan dikaitkan dengan Aceh. Atau setiap ada kejadian yang berhubungan dengan preman akan menuduh Yogya sebagai biang keladinya. Padahal dua daerah tersebut nyaris tidak seperti digambarkan di atas.
Upaya Minimalisasi
Kekerasan memang sulit dihapuskan. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkannya. Jika kita sepakat bahwa media massa ikut andil dalam menyulut tindak kekerasan di masyarakat, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk menguranginya: pertama meskipun terbilang klasik, jurnalisme cover both sides (meliputi dua sisi yang berbeda secara seimbang) dan peliputan secara adil masih menjadi salah satu cara yang baik.
Aktualisasinya, jika terjadi konflik atau tindak kekerasan media tidak boleh membela satu pihak secara tidak seimbang, meskipun hal demikian masih relatif sifatnya. Sedangkan keadilan, media harus menampilkan sumber berita yang sepadan. Misalnya, ketika ada dua etnis yang terlibat konflik, jika jurnalis mewawancarai pimpinan salah satu pihak, pimpinan pihak lain juga harus diwawancari. Termasuk, keadilan yang dilihat dari jenis tulisan yang disajikan. Ini baru adil. Tak bisa dipungkiri, kebebasan pers yang sedang dinikmati di Indonesia saat ini memang bagai sebuah anugerah terindah yang selama ini diidam-idamkan, setelah sebelumnya dikekang dalam jangka waktu lama. Sebelumnya, peristiwa konflik di dacrah Indonesia seperti Aceh, Maluku, Ambon nyaris tidak boleh diberitakan. Saat ini, daerah tersebut bagai "selebritis" yang tak lepas dari pengamatan pers.
Kesulitan yang kadang dihadapi oleh para jumalis adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber dari dua belah pihak secara adil. Oleh karena itu, apa boleh buat terkadang media hanya bisa merekam pemberitaan konflik Maluku dari satu sisi saja. Keputusan ini terpaksa diambil mengingat tidak semua nara sumber mau diwawancarai. Padahal jurnalis hanya ingin melakukan konfirmasi sehubungan dengan berita yang berat sebelah atau data-data mentah yang didapat di lapangan.
Ketidakseimbankan yang terpaksa diambil inilah pada akhirnya membuat masyarakat marah, menuding media hanya mau menang sendiri. Padahal tak kalah sulitnya dengan mengatasi konflik itu sendiri.
Kedua, memupuk pelaksanaan jurnalisme damai (peace journalism). Ia secara sadar mengadopsi agenda perdamaian, bukan perang. Jurnalisme damai mencoba memetakan konflik pra kekerasan, mengidentifikasi banyak pihak dan berbagai penyebab, sehingga membuka jalan bagi dialog untuk menciptakan perdamaian. jurnalisme perdamaian ini memanusiawikan seluruh isi konflik dan berupaya mendokumentasikan berbagai kepalsuan dan penderitaan dan juga memprakarsai perdamaian (Lukas Luwarso dkk., 2000). Jurnalisme perdamaian mempunyai tugas utama yakni memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menganalisis tujuan-tujuan mereka dan memberikan informasi yang mereka sediakan dalam agenda khusus mereka (Zain Hae, 2000).
Tetapi jurnalisme damai hanya bisa terwujud paling tidak dengan syarat; wartawan yang tangguh dalam menegakkan kode etik dan memiliki wawasan memadai menyangkut masalah yang diliput; media pers yang serius, yang tidak mementingkan bisnis dan politis dan bukan wartawan yang hanya mengedepankan sensasi, dramatisasi dan meliput konflik serta tindak kekerasan hanya untuk kepentingan bisnis. Jurnalisme damai ini juga secara otomatis akan mengurangi dampak kekerasan di masyarakat. Sebab, tak bisa dipungkiri kekerasan juga bisa dipicu oleh media massa.
Ketiga, memberikan ruang gerak yang bebas kepada wartawan untuk meliput tanpa ketertekanan. Ini juga masih dilematis. Sebab, masa efouria memberi kecenderungan jumalis meliput apa saja dan di mana saja serta pada siapa saja. Kondisi ini akan memunculkan sikap mau menang se'ndiri dalam meliput suatu kejadian.
Tidak adanya keleluasaan tentu tidak akan memberikan ruang gerak jurnalis untuk meliput. Tak terkecuali jika ini didukung oleh pelitnya nara sumber ketika dimintai komentar. Padahal bisa jadi komentarnya itu untuk menyeimbangkan data yang sudah didapat oleh wartawan. Dan bisa jadi sebagai sarana untuk konfirmasi tentang data yang didapat di lapangan. Kalau sudah begini, karena tuntutan teknis, maka tak ada jalan lain, kecuali harus mengirimkan berita apa adanya kepada redaktur. Beruntung kalau redaktur tetap meminta keseimbangan berita, kalau tidak?
Keempat, meskipun sangat relatif, self cencorship (sensor diri) menjadi jaminan pula agar kekerasan tidak melebar. Ini bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: apakah apa yang diberitakan nanti akan menyulut kemarahan publik? Apakah yang akan diberitakan sudah seimbang dan tidak memanas-manasi situasi? Apakah berita yang akan disajikan tidak membahayakan moral publik? Apakah berita ini tidak semata hanya sensasi tetapi sudah selayaknya demikian faktanya? Apakah kami tidak punya kepentingan terselubung atas pemuatan berita tersebut? jika jawabannya ya, maka media yang bersangkutan telah melakukan sensor diri.
Kelima, dilakukan social punishment (hukuman sosial) pada media. Jika kita menganggap sebuah media massa hanya memprovokasi agar tejadi tindak kekerasan mengapa tidak "diboikot" saja? Tidak membaca media itu adalah salah satu tindakan melakukan hukuman sosial. Masalahnya, tidak semua orang sadar dan mau untuk melakukannya.
Jika seseorang mengkritik banyak media massa yang "mengumbar" jumalisme pornografi lewat foto, gambar atau tulisan yang memancing asosasi pembacanya pada seks, tetapi ia membaca bahkan berlangganan atau menonton acaranya, berarti tidak ada konsistensi antara apa yang diucapkan dengan perilakunya.
Apa yang disajikan dalam tulisan ini jelas tidak mudah untuk dilakukan. Semua juga tergantung tidak hanya pada media saja, tetapi juga kedewasaan masyarakat. Tak terkecuali dengan sikap pemerintahnya. Pelarangan oleh pemerintah justru akan semakin membuat media "garang". Diktum, "Semakin diarang semakin dilanggar" akan membuktikan itu semua. (tulisan ini pernah dimuat majalah Visi Fisip UNS, Solo, 2003) Readmore »»
Langganan:
Postingan (Atom)